Muchammad Afifuddin, MA
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Only Yesterday in Jakarta: Property Boom and Consumptive Trends in the Late New Order Metropolitan City
Southeast Asian Studies, Vol. 38, No.4, March 2001 Only Yesterday in Jakarta: Property Boom and Consumptive Trends in the Late New Order Metropolitan City ARAI Kenichiro* Abstract The development of the property industry in and around Jakarta during the last decade was really conspicuous. Various skyscrapers, shopping malls, luxurious housing estates, condominiums, hotels and golf courses have significantly changed both the outlook and the spatial order of the metropolitan area. Behind the development was the government's policy of deregulation, which encouraged the active involvement of the private sector in urban development. The change was accompanied by various consumptive trends such as the golf and cafe boom, shopping in gor geous shopping centers, and so on. The dominant values of ruling elites became extremely con sumptive, and this had a pervasive influence on general society. In line with this change, the emergence of a middle class attracted the attention of many observers. The salient feature of this new "middle class" was their consumptive lifestyle that parallels that of middle class as in developed countries. Thus it was the various new consumer goods and services mentioned above, and the new places of consumption that made their presence visible. After widespread land speculation and enormous oversupply of property products, the property boom turned to bust, leaving massive non-performing loans. Although the boom was not sustainable and it largely alienated urban lower strata, the boom and resulting bust represented one of the most dynamic aspect of the late New Order Indonesian society. I Introduction In 1998, Indonesia's "New Order" ended. -

FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases
ACKNOWLEDGEMENTS 3 FOREWORD 4 THEME 1 IMPROVING POULTRY HEALTH 5 THEME 2 PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP 14 THEME 3 CAPACITY BUILDING 18 The FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Dis- eases (ECTAD) Programme works closely with the Government THEME 4 of Indonesia’s Ministry of Agriculture, provincial and district STREGHTENING VETERINARY SERVICES 23 Livestock Services; the National Commission for Zoonoses Control (KOMNAS Zoonosis); the United Nations country MAP 32 team, particularly the World Health Organization, the Office ABBREVIATIONS & ACRONYMS 34 for the Coordination of Humanitarian Affairs and the United Nations Development Programme; the United States Depart- ment of Agriculture, the Australian Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF), ASEAN, the US Centers for Disease Control, the Australian Centre for International Agri- cultural Research, the Japan International Cooperation Agency and non-government partners such as the Indonesian poultry veterinarians’ association (ADPHI), the National Poultry Health Committee (KKUN), the Strategies Against Flu Emergence (SAFE) project, and the JSI Deliver project. In relation to rabies control, FAO works closely with the DGLAHS and Bali livestock services, and with DAFF, the World Society for the Protection of Animals (WSPA), the Global Alliance for Rabies Control (GARC) and the University of Glasgow, UK. Collectively, donor organizations fund some 11 international and 70 national staff contracted to FAO in Jakarta and South Sulawesi. FAO staff are responsible for technical and admin- istrative support to the HPAI Campaign Management Unit, Directorate of Animal Health, undertaking a range of activities in support of avian influenza control. Some staff members also provide strategic technical support on rabies control to the DAH and the Bali provincial and districts livestock services. -

Official Village Midwives Versus Traditional Birth Attendants in Remote Area
Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, July-September 2021, Vol. 15, No. 3 3573 The Influence of Culture in Determining Pregnancy Care: Official Village Midwives Versus Traditional Birth Attendants in Remote Area Masyudi1, Said Usman2, Tika Indiraswari1, TM Rafsanjani1, Evi Dewi Yani1, Yulidar1, Husna1 1Lecturer at Faculty of Public Health, Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Indonesia, 2Lecturer at Faculty of Medicine, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia Abstract Background: The high rate of maternal and infant mortality in Indonesia in the past year can be influenced by the habits of the community who prefer Traditional Birth Attendants (TBAs) in the childbirth. In fact, TBAs are not health profession and do not have competency standards to assist with childbirth, thus increasing the risk of maternal and infant mortality. This article aimed to determine the influence of culture on the community’s habit of choosing TBAsor official village midwives (OVMs)in childbirth process in remote areas.Methods: A cross-sectional study was used. The respondents were mothers who gave birth in the last one year in one remote sub-district in Aceh. TBAs and official village midwiveswereobserved and in- depth interviews were also conducted.Resultsand Discussions:The results of this study showed community attitudes about cultural influences during pregnancy, such as TBAs-assisted delivery is a cultural belief that must be followed.Hence, factors that influence the choice of mothers in using OVMs or TBAs:cultural beliefs and norms, and the role of the cultural leaders in making decisions. Conclusions: Culture plays an important role in influencing people who live in remote areas to chooseTBAs rather than the OVMs. -
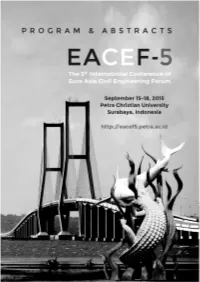
00-Program-And-Abstracs-EACEF5
2 CONTENT Welcome Message Conference Chairman ·····················································4 Welcome Message Founding Chairman of EACEF ··········································5 COMMITTEES ································································································6 GENERAL INFORMATION ···············································································8 VENUE INFORMATIONS ··············································································· 10 PROGRAM AT A GLANCE ············································································· 13 KEYNOTE SPEAKERS····················································································· 15 INVITED SPEAKERS ······················································································ 19 KEYNOTE AND INVITED SPEECHES ······························································· 21 PARALLEL SESSIONS····················································································· 23 INSTRUCTION FOR SPEAKERS ······································································ 39 SOCIAL PROGRAM ······················································································· 40 INFORMATION ABOUT SURABAYA ······························································ 49 ABSTRACTS ·································································································· 51 Construction Project and Safety Management ····································· 51 Environmental Engineering ·································································· -

Religion's Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia
H U M A N R I G H T S IN RELIGION’S NAME Abuses against Religious Minorities in Indonesia WATCH In Religion’s Name Abuses against Religious Minorities in Indonesia Copyright © 2013 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-56432-992-5 Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch is dedicated to protecting the human rights of people around the world. We stand with victims and activists to prevent discrimination, to uphold political freedom, to protect people from inhumane conduct in wartime, and to bring offenders to justice. We investigate and expose human rights violations and hold abusers accountable. We challenge governments and those who hold power to end abusive practices and respect international human rights law. We enlist the public and the international community to support the cause of human rights for all. Human Rights Watch is an international organization with staff in more than 40 countries, and offices in Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Goma, Johannesburg, London, Los Angeles, Moscow, Nairobi, New York, Paris, San Francisco, Tokyo, Toronto, Tunis, Washington DC, and Zurich. For more information, please visit our website: http://www.hrw.org FEBRUARY 2013 1-56432-992-5 In Religion’s Name Abuses against Religious Minorities in Indonesia Map .................................................................................................................................... i Glossary ............................................................................................................................ -

Indonesia: Condemned Communities
September 2006 Volume 18, No. 10 (C) Condemned Communities Forced Evictions in Jakarta I. Summary ..................................................................................................................................... 1 Key Recommendations............................................................................................................4 II. Methods..................................................................................................................................... 6 III. Background ............................................................................................................................. 8 A Legacy of Evictions and Inadequate Access to Housing for the Poor ........................ 9 Infrastructure Development and the Role of International Agencies............................13 Governor Sutiyoso’s Campaign Against the Poor and Migrants.....................................13 Public Order Officials............................................................................................................14 Urban Gangs Involved in Evictions ....................................................................................16 IV. Insecure Land Tenure..........................................................................................................19 V. What is a “Forced Eviction”? ..............................................................................................30 Legal Standards .......................................................................................................................31 -

The Tradition of Forgiveness Based on Religion As Culture Towards Human Humanization
The Tradition of Forgiveness based on Religion as Culture towards Human Humanization Christofora Megawati Tirtawinata1, Frederikus Fios1 and Petrus Hepi Witono2 1Character Building Development Center, Computer Science Department, Scholl of Computer Science, Bina Nusantara University,Jakarta, Indonesia 11480 2Character Building Development Center, Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia 11480 Keywords: Forgiveness, Religion, Humanization. Abstract: Humans are creatures of individuals who always live with others. Humans have uniqueness and differences in many dimensions: tribe, religion, race, social class, age, gender and others. In human relationships there can be personal conflicts that lead to anger and resentment among humans. For that we need forgiveness and forgiveness between humans so as to achieve inner peace individually and in social harmony. The habit of forgiving others is a noble tradition that exists in the teachings of religions in Indonesia. This study aims to find a tradition of religious-based forgiveness as a culture toward human humanization. The study focused on literary studies that depict the teachings of the tradition of forgiveness in the teachings of religions as a collection of values that are meaningful to religious man in running social life both as individual beings and social beings. The case examples of the application of forgiveness practiced by the community of Saint Laurenzo Parung Panjang, Bogor, West Java became an exciting best practice of religious-based forgiving experiences towards human humanization. The research method used qualitative method. The theoretical framework uses religious teachings relevant to the tradition of forgiveness. This research is expected to inspire every human being to forgive and forgive others to show human identity as religious beings and cultured beings in social reality. -

Indonesia – Jakarta – West Java – Ahmadiyah
Refugee Review Tribunal AUSTRALIA RRT RESEARCH RESPONSE Research Response Number: IDN31267 Country: Indonesia Date: 5 February 2007 Keywords: Indonesia – Jakarta – West Java – Ahmadiyah This response was prepared by the Country Research Section of the Refugee Review Tribunal (RRT) after researching publicly accessible information currently available to the RRT within time constraints. This response is not, and does not purport to be, conclusive as to the merit of any particular claim to refugee status or asylum. Questions 1. What is the Ahmadiyah organisation in Sydney called and where is it located? 2. Are there any reports which describe the current situation for Ahmadi in Jakarta, Indonesia? Have there been any anti-Ahmadiyah events in Jakarta since 2004? 3. Is there an Ahmadiyah Mosque and/or organisation in Jakarta? 4. What are the main beliefs of Ahmadiyah? 5. Was there an Ahmadiyah gathering at Sukabumi, Jabar (or at Parung, West Java) on 7 July 2005 at which Abdurahman Assegaf threatened the Ahmadi? 6. Was there an Ahmadiyah gathering at Kampung Neglosari on 19 September 2005 at which Abdul Rahman Assegaf threatened the Ahmadi, and which led to violence? 7. How far from Jakarta are Parung, Sukabumi and Neglosari? RESPONSE 1. What is the Ahmadiyah organisation in Sydney called and where is it located? The local Ahmadiyah organisation in Sydney is the Ahmadiyya Muslim Association of Australia (AMAA). Details follow: Ahmadiyya Muslim Association of Australia (AMAA) Al Masjid baitul Huda Lot 20 Hollinsworth Road Marsden Park NSW 2765 Website: http://www.ahmadiyya.org.au 2. Are there any reports which describe the current situation for Ahmadi in Jakarta, Indonesia. -

From Religious Exclusiveness Towards Inclusiveness in Parung
From Religious Exclusiveness towards Inclusiveness in Parung Panjang – Indonesia: Ethical Reflection on Just and Civilized Humanity of Pancasila Ideology in Digitalized Era Frederikus Fios1, Christofora Megawati Tirtawinata1, Catarina Manurung2 1Character Building Development Center, Computer Science Department, School of Computer Science, Bina Nusantara Univeristy, Jakarta, Indonesia 11480 2Language Center, English Department, Faculty of Humanities, Bina Nusantara University, Jakarta, Indonesia 11480 Keyword: Indonesia, Civilized Humanity, Pancasila Abstract: A difference in social, cultural and religious reality in Indonesia is ambiguous. In one side, the religion difference is a good thing and beautiful, but on the other it creates disharmony relationship. It appeared in the phenomenon of counter-value practices of just and civilized humanity, as already outlined in Pancasila ideology. The root of the problem caused of the lack of a proper understanding of the substance of the human being to a just and civilized, so bring the negative implication in intolerance condition that is not accordance with the ethical imperative precepts of just and civilized humanity. This study aimed to dismantle the empirical fact of religious exclusivist practices that occurred in the Kabasiran Village, ParungPanjang, Bogor, Indonesia in 2014 until now. Using the methods of philosophy (ethical reflection) on written documents were found, researchers construct moral ethical values that should be practiced in relation of different religious beliefs to the establishment inclusive ideology in Kabasiran Village, ParungPanjang, West Java, Indonesia. In the digitalized humanities era, the role of social media is very strategic and important as an effective means of channeling ethical values to society. 1 INTRODUCTION in the media because the local government asked reporters not to publish. -

In Madania School, Bogor Regency
PENDIDIKAN NILAI: DI SEKOLAH MADANIA KABUPATEN BOGOR Educational of Value: in Madania School, Bogor Regency Mulyana Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur Email: [email protected] Naskah diterima tanggal 27 Maret 2015. Naskah direvisi tanggal 30 April 2015 Naskah disetujui tanggal 03 November 2015 Abstrak Paper ini menyajikan hasil penelitian terhadap program Pendidikan Menghidupkan Nilai yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melakukan studi kasus terhadap implementasi program tersebut di Sekolah Madania, Parung, Bogor. Penelitian ini mencoba mengkaji apakah program Pendidikan Menghidupkan Nilai dapat menjadi model yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa program Pendidikan Menghidupkan Nilai telah memberi hasil positif yang teramati dalam perubahan perilaku tenaga pendidik maupun siswa terkait sejumlah nilai yang dipelajari, seperti kejujuran, penghargaan, toleransi, dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil riset ini, peneliti menyimpulkan bahwa Pendidikan Menghidupkan Nilai, terutama pada aspek pendekatan dan metodenya, dapat menjadi model bagi pembelajaran PAI di sekolah. Kata kunci: pendidikan menghidupkan nilai, pendidikan karakter, pendidikan agama Islam (PAI), Sekolah Madania Abstract This paper presents the results of the research on Education Program in Living Values conducted a number of elements of society. The study was conducted by doing a case study to the implementation of the program at Madania school, Parung, Bogor. This study investigated whether Education Program in Living Values can become useful model in improving the quality of learning of Islamic Education (PAI) at school. The results showed that this program has given positive results observed in behavior changes of the teachers and the students related to a number of values studied, such as honesty, respect, tolerance and responsibility. -

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) Jakarta International Conference on Social Sciences and Humanities (Jicossh) Vol
Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries http://ijmmu.com International Journal of Multicultural [email protected] ISSN 2364-5369 and Multireligious Understanding Volume 6, Special Issue 2 February, 2019 Jakarta International Conference on Social Sciences and Humanities Pages: 1-17 Economic Potential Mapping in Parung Subdistrict, Bogor District Suharyati; Ediwarman Faculty of Economics and Business ,UPN Veteran Jakarta, Indonesia Abstract The sector of economy in Parung Subdistrict Bogor District is dominated profoundly by agriculture, forestry and fishing, processing, providing accommodation, and food and beverages. SMEs, red: UMKM also play a capital role in the economic growth either nationally and locally. One of factors due to the significant progress of SMEs was the synergy of action between government and entrepreneurs to design competitive advantages of SMEs. This research aims to conduct economic potential mapping in Parung Subdistrict, Bogor District analyzing the internal and external factors effecting the economic potential in the territory. Bogor has forty subdistricts including Parung Subdistrict which has nine villages. Samples gathered were 54 representing all of nine villages in the district. The primary data were questionnaires and interviews with entrepreneurs of local SMEs .Data progressing method used in this research was descriptive quantitative using SPACE Matrix, SWOT matrix, and IE matrix. The result from Quadrant analysis showed that SMEs in Parung Subdistrict is in the first quadrant with strategic priority of growth. Meanwhile, the result from SPACE Matrix exposed that the alternative strategy is Aggressive. And at last, the IE Matrix result put SMEs strategy at the fifth quadrant of Hold and Maintain. -
Nature School Learning Model (Case Study at the School of Universe, Lebak Wangi Village, Parung District, Bogor Regency)
International Journal of Education, Learning and Development Vol.7, No.6, pp.41-51, June 2019 Published by European Centre for Research Training and Development UK (www.eajournals.org) NATURE SCHOOL LEARNING MODEL (CASE STUDY AT THE SCHOOL OF UNIVERSE, LEBAK WANGI VILLAGE, PARUNG DISTRICT, BOGOR REGENCY) Nanda Ayu Setiawati1, Ichwan Azhari2, Yusnadi2 1Master Student at State University of Medan (Unimed), Medan, Indonesia 2 Lecturer at State University of Medan (Unimed), Medan, Indonesia ABSTRACT: This study aimed to: (1) examine the nature school learning model at the School of Universe, Lebak Wangi Village, Parung District, Bogor Regency, (2) analyze the factors supporting the success of the learning model at the School of Universe, Lebak Wangi Village, Parung District, Bogor Regency. This study used a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques carried out in this study were: interviews, observation and documentation. Data analysis in this study used interactive models of Miles and Huberman, with steps: data reduction, data model, conclusion and verification. The findings of the study showed that: (1) the learning model in the School of Universe using the spider webb learning model was done by determining the theme. Fields of study in thematic approaches included Science, Mathematics, Indonesian, Social, Green Lab, Cooking, Business, and Morals, (2) the factors supporting the success of the learning model at SD School of Universe were: qualified teachers, the methods used included: exemplary methods, natural learning methods, outbound methods, business methods, adequate facilities and infrastructure, including teacher reading resources to add insight and produce the latest innovations in the field of education, as well as parental supports.