Analisis Bioaktivitas Bahan Irigasi Ekstrak Buah Lerak (Sapindus Rarak Dc) Terhadap Patogenesis Fusobacterium Nucleatum (Kajian
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Framework Species Approach to Forest Restoration: Using Functional Traits As Predictors of Species Performance
- 1 - The Framework Species Approach to forest restoration: using functional traits as predictors of species performance. Thesis submitted in accordance with the requirements of the University of Liverpool for the degree of Doctor in Philosophy by Hannah Betts July 2013 - 2 - - 3 - Abstract Due to forest degradation and loss, the use of ecological restoration techniques has become of particular interest in recent years. One such method is the Framework Species Approach (FSA), which was developed in Queensland, Australia. The Framework Species Approach involves a single planting (approximately 30 species) of both early and late successional species. Species planted must survive in the harsh conditions of an open site as well as fulfilling the functions of; (a) fast growth of a broad dense canopy to shade out weeds and reduce the chance of forest fire, (b) early production of flowers or fleshy fruits to attract seed dispersers and kick start animal-mediated seed distribution to the degraded site. The Framework Species Approach has recently been used as part of a restoration project in Doi Suthep-Pui National Park in northern Thailand by the Forest Restoration Research Unit (FORRU) of Chiang Mai University. FORRU have undertaken a number of trials on species performance in the nursery and the field to select appropriate species. However, this has been time-consuming and labour- intensive. It has been suggested that the need for such trials may be reduced by the pre-selection of species using their functional traits as predictors of future performance. Here, seed, leaf and wood functional traits were analysed against predictions from ecological models such as the CSR Triangle and the pioneer concept to assess the extent to which such models described the ecological strategies exhibited by woody species in the seasonally-dry tropical forests of northern Thailand. -

Natural Surfactant Saponin from Tissue of Litsea Glutinosa and Its Alternative Sustainable Production
plants Article Natural Surfactant Saponin from Tissue of Litsea glutinosa and Its Alternative Sustainable Production Jiratchaya Wisetkomolmat 1,2, Ratchuporn Suksathan 3, Ratchadawan Puangpradab 3, Keawalin Kunasakdakul 4, Kittisak Jantanasakulwong 5,6, Pornchai Rachtanapun 5,6 and Sarana Rose Sommano 2,5,7,* 1 Interdisciplinary Program in Biotechnology, Graduate School, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand; [email protected] 2 Plant Bioactive Compound Laboratory, Department of Plant and Soil Sciences, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand 3 Research and Product Development, Department of Research and Conservation, Queen Sirikit Botanic Garden, The Botanical Garden Organisation, Chiang Mai 50180, Thailand; [email protected] (R.S.); [email protected] (R.P.) 4 Department of Entomology and Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand; [email protected] 5 Cluster of Agro Bio-Circular-Green Industry (Agro BCG), Chiang Mai University, Chiang Mai 50100, Thailand; [email protected] (K.J.); [email protected] (P.R.) 6 Division of Packaging Technology, Faculty of Agro-Industry, Chiang Mai University, Chiang Mai 50100, Thailand 7 Innovative Agriculture Research Centre, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand * Correspondence: [email protected]; Tel.: +66-53944040 Received: 8 October 2020; Accepted: 6 November 2020; Published: 9 November 2020 Abstract: In this research, we assessed the detergency properties along with chemical characteristic of the surfactant extracts from the most frequently cited detergent plants in Northern Thailand, namely, Sapindus rarak, Acacia concinna, and Litsea glutinosa. Moreover, as to provide the sustainable option for production of such valuable ingredients, plant tissue culture (PTC) as alternative method for industrial metabolite cultivation was also proposed herein. -
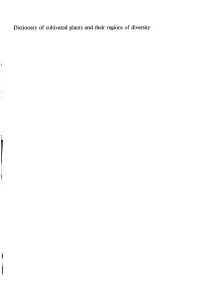
Dictionary of Cultivated Plants and Their Regions of Diversity Second Edition Revised Of: A.C
Dictionary of cultivated plants and their regions of diversity Second edition revised of: A.C. Zeven and P.M. Zhukovsky, 1975, Dictionary of cultivated plants and their centres of diversity 'N -'\:K 1~ Li Dictionary of cultivated plants and their regions of diversity Excluding most ornamentals, forest trees and lower plants A.C. Zeven andJ.M.J, de Wet K pudoc Centre for Agricultural Publishing and Documentation Wageningen - 1982 ~T—^/-/- /+<>?- •/ CIP-GEGEVENS Zeven, A.C. Dictionary ofcultivate d plants andthei rregion so f diversity: excluding mostornamentals ,fores t treesan d lowerplant s/ A.C .Zeve n andJ.M.J ,d eWet .- Wageninge n : Pudoc. -11 1 Herz,uitg . van:Dictionar y of cultivatedplant s andthei r centreso fdiversit y /A.C .Zeve n andP.M . Zhukovsky, 1975.- Me t index,lit .opg . ISBN 90-220-0785-5 SISO63 2UD C63 3 Trefw.:plantenteelt . ISBN 90-220-0785-5 ©Centre forAgricultura l Publishing and Documentation, Wageningen,1982 . Nopar t of thisboo k mayb e reproduced andpublishe d in any form,b y print, photoprint,microfil m or any othermean swithou t written permission from thepublisher . Contents Preface 7 History of thewor k 8 Origins of agriculture anddomesticatio n ofplant s Cradles of agriculture and regions of diversity 21 1 Chinese-Japanese Region 32 2 Indochinese-IndonesianRegio n 48 3 Australian Region 65 4 Hindustani Region 70 5 Central AsianRegio n 81 6 NearEaster n Region 87 7 Mediterranean Region 103 8 African Region 121 9 European-Siberian Region 148 10 South American Region 164 11 CentralAmerica n andMexica n Region 185 12 NorthAmerica n Region 199 Specieswithou t an identified region 207 References 209 Indexo fbotanica l names 228 Preface The aimo f thiswor k ist ogiv e thereade r quick reference toth e regionso f diversity ofcultivate d plants.Fo r important crops,region so fdiversit y of related wild species areals opresented .Wil d species areofte nusefu l sources of genes to improve thevalu eo fcrops . -

Effect of Some Pre-Sowing Treatments on Sapindus Trifoliatus Seed
The Pharma Innovation Journal 2019; 8(8): 438-441 ISSN (E): 2277- 7695 ISSN (P): 2349-8242 NAAS Rating: 5.03 Effect of some pre-sowing treatments on Sapindus TPI 2019; 8(8): 438-441 © 2019 TPI trifoliatus seed germination www.thepharmajournal.com Received: 23-06-2019 Accepted: 25-07-2019 Anshu Dhaka and Pradeep Chaudhary Anshu Dhaka Department of Botany, D.N. Abstract (P.G.) College, Meerut, Utter The seeds of Sapindus trifoliatus showed 100 percent viability as tested with Triphenyl tetrazolium Pradesh, India chloride (TZ test). The electrical conductivity of the seed lechate was also observed to find out the integrity of membranous system of seed. The low ions leakage value (0.045 – 0.067µmho cm-1) of EC Pradeep Chaudhary also indicated the high level of intactness of membranous system and viability of the seeds. Sapindus Department of Statistics, Ch. genus usually undergoes physical or physiological dormancy. The seeds of Sapindus trifoliatus exhibited Charan Singh University, complete dormancy i.e. no germination when placed on wet filter paper under favourable condition Meerut, Utter Pradesh, India showing the high level of seed dormancy. Seed germination increased through various seed treatments such as mechanical scarification, hot water, acid treatment and chipping plus chemical treatments (GA3, 0 KNO3 and Thiourea). The exposure of seeds to hot water at 70 C for 60 minutes recorded 10 - 12% germination, seedling vigour (10.0 – 11.0), vigour index (100-132.0) and speed of germination (1.60 – 1.81) as compared to 10, 30 min. and control. The seeds treated with 25% conc. -

Bahan Ajar Taksonomi Tumbuhan Tinggi
BAHAN AJAR TAKSONOMI TUMBUHAN TINGGI Disusun oleh MARINA SILALAHI, M.Si PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA GENAP 2013/2014 i KATA PENGANTAR Bahan Ajar ini disiapkan untuk membantu mahasiswa memahami taksonomi, klasifikasi, manfaat, dan tata nama ilmiah tumbuhan tumbuhan. Pengenalan tumbuhan secara taksonomi merupakan merupakan salah satu langka untuk meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sekitar khususnya tumbuhan. Bahan Ajar ini terdiri dari 15 bab yang membahas tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta terdiri dari 2 devisi yaitu Phinophyta dan Magnoliophyta dibahas dalam Bahan Ajar ini, namun karena luasnya cakupan taksonomi maka pembahasan disesuaikan dengan silabus yang telah disusun. Bahan Ajar ini lebih banyak membahas Magnoliophyta khususnya karena devisi tersebut mendominasi tumbuhan di permukaan bumi saat ini. Magnoliophyta terdiri dari 10 kelas. Setiap anak kelas Magnoliophyta dibahas mulai dari ordo, famili dan jenis serta manfaatnya. Ordo, famili maupun spesies yang dibahas dalam Bahan Ajar ini sebagian besar didasarkan pada manfaat dalam bidang ekonomi, obat, bahan pangan, maupun dalam ekologi. Selain manfaat faktor lain yang juga dipertimbangkan dalam pemilihan ordo maupun famili adalah penyebarannya (yang dipilih terutama yang banyak di temukan di Indonesia). Bahan Ajar ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun teknis penulisan. Penulis mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Bahan Ajar ini. -

Sapindus Rarak. Dc) Fruits in Wistar Rats
Innovare International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Academic Sciences ISSN- 0975-1491 Vol 6, Issue 11, 2014 Original Article ACUTE AND SUB-CHRONIC (28 DAYS) REPEATED ORAL TOXICITY TEST OF ETHANOL EXTRACT OF LERAK (SAPINDUS RARAK. DC) FRUITS IN WISTAR RATS INARAH FAJRIATY1,2, I. KETUT ADNYANA1, IRDA FIDRIANNY1 1School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology, Indonesia, 2Major of Pharmacy, Faculty of Medical, Tanjungpura University, Pontianak, Indonesia. Email: [email protected] Received: 21 Apr 2014 Revised and Accepted: 15 Jun 2014 ABSTRACT Objectives: Natural product which is used as medicines should in compliance with the guidelines that the drug does not cause acute or chronic toxicity and proved efficacious as a medicinal. The present study was carried out to evaluate the safety of ethanol extract of lerak (sapindus rarak. DC) fruits. Methods: Lerak fruits were extracted by continuous extraction using the Soxhlet apparatus and ethanol 96 %. Extraction results was continued to acute toxicity by using a fixed dose method and sub-chronic toxicity was performed according to the OECD guideline. In an acute toxicity study, a single dose of 2000 and 5000 mg/kg bw of lerak fruits extract was administered p. o (orally) to healthy female Wistar rats following a sighting study. The animals were observed for mortality and clinical signs for 24 hour and then daily for 14 days. In the sub-chronic toxicity study, the extract was administered orally at doses of 50, 100 and 500 mg/kg bw /day. The animals were given by ethanol extract of lerak fruits once daily for 28 days, the administrations were stopped on the 28th day, while for the satellite group still observed until 14 days during the post observation period for assessment of reversibility, persistence or delayed occurrence of toxicity. -

Diktat Sistematika Tumbuhan Tinggi
DIKTAT SISTEMATIKA TUMBUHAN TINGGI Dr. MARINA SILALAHI, M.Si PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA SEPTEMBER 2017 i DIKTAT SISTEMATIKA TUMBUHAN TINGGI MARINA SILALAHI Foto halaman sampul dari kiri ke kanan adalah Annona squamosa (Annoceae); Lantana camara (Verbenaceae); Gloriosa superba (Colchicaceae); Syngonium podophyllum (Araceae) ii KATA PENGANTAR Bahan ajar atau diktat ini disiapkan untuk membantu mahasiswa memahami taksonomi, klasifikasi, manfaat, dan tata nama ilmiah tumbuhan tumbuhan. Pengenalan tumbuhan secara taksonomi merupakan merupakan salah satu langka untuk meningkatkan rasa kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sekitar khususnya tumbuhan. Bahan Ajar ini terdiri dari 14 bab yang membahas tumbuhan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta terdiri dari 2 devisi yaitu Phinophyta dan Magnoliophyta dibahas dalam Bahan Ajar ini, namun karena luasnya cakupan taksonomi maka pembahasan disesuaikan dengan silabus yang telah disusun. Bahan Ajar ini lebih banyak membahas Magnoliophyta khususnya karena devisi tersebut mendominasi tumbuhan di permukaan bumi saat ini. Magnoliophyta terdiri dari 10 kelas. Setiap anak kelas Magnoliophyta dibahas mulai dari ordo, famili dan jenis serta manfaatnya. Ordo, famili maupun spesies yang dibahas dalam Bahan Ajar ini sebagian besar didasarkan pada manfaat dalam bidang ekonomi, obat, bahan pangan, maupun dalam ekologi. Selain manfaat faktor lain yang juga dipertimbangkan dalam pemilihan ordo maupun famili adalah penyebarannya (yang -

Ep 2588593 B1
(19) TZZ ¥_T (11) EP 2 588 593 B1 (12) EUROPEAN PATENT SPECIFICATION (45) Date of publication and mention (51) Int Cl.: of the grant of the patent: A61K 8/46 (2006.01) A61K 8/49 (2006.01) 23.08.2017 Bulletin 2017/34 A61Q 19/08 (2006.01) A61K 8/97 (2017.01) (21) Application number: 11804011.2 (86) International application number: PCT/US2011/040157 (22) Date of filing: 13.06.2011 (87) International publication number: WO 2012/005876 (12.01.2012 Gazette 2012/02) (54) COMPOSITIONS AND METHODS FOR STIMULATING MAGP-1 TO IMPROVE THE APPEARANCE OF SKIN ZUSAMMENSETZUNGENUND VERFAHREN ZUR MAGP-1-STIMULATION ZUR VERBESSERUNG DES ERSCHEINUNGSBILDES DER HAUT COMPOSITIONS ET PROCÉDÉS DE STIMULATION DE MAGP-1 POUR AMÉLIORER L’ASPECT DE LA PEAU (84) Designated Contracting States: (56) References cited: AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB WO-A1-2007/093839 WO-A1-2012/005872 GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO WO-A2-2006/068778 JP-A- 2002 087 973 PL PT RO RS SE SI SK SM TR JP-A- 2006 069 954 JP-A- 2010 090 069 US-A1- 2003 207 818 US-A1- 2006 134 231 (30) Priority: 30.06.2010 US 360083 P US-A1- 2007 161 625 US-A1- 2008 274 453 US-A1- 2009 012 273 (43) Date of publication of application: 08.05.2013 Bulletin 2013/19 • MICOR JOSERENE L. ET AL.: "BiologicalActivity of Bignay [Antidesma bunius (L.) Spreng] Crude (73) Proprietor: Avon Products, Inc. -

PEMANFAATAN LERAK (Sapindus Rarak DC) SEBAGAI SABUN NABATI YANG RAMAH LINGKUNGAN
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PEMANFAATAN LERAK (Sapindus rarak DC) SEBAGAI SABUN NABATI YANG RAMAH LINGKUNGAN BIDANG KEGIATAN : PKM GAGASAN TERTULIS Diusulkan oleh : Achmad Solikhin (E24090040/ 2009) Mujtahid Alfajri (F34090063/ 2009) Ridho Fahrorozhi Hasyim ( G64100112/ 2010) INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011 i PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PEMANFAATAN LERAK (Sapindus rarak DC) SEBAGAI SABUN NABATI YANG RAMAH LINGKUNGAN BIDANG KEGIATAN : PKM GAGASAN TERTULIS Diusulkan oleh : Achmad Solikhin (E24090040/ 2009) Mujtahid Alfajri (F34090063/ 2009) Ridho Fahrorozhi Hasyim ( G64100112/ 2010) INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011 ii LEMBAR PENGESAHAN 1. Judul : Pemanfaatan Lerak (Sapindus rarak DC) sebagai Sabun Nabati Ramah Lingkungan 2. Bidang Kegiatan : ( - ) PKM-AI ( √ ) PKM-GT 3. Ketua a. Nama Lengkap : Achmad Solikhin b. NIM : E24090040 c. Jurusan/Fakultas : Departemen Hasil Hutan/Kehutanan d. Universitas : Institut Pertanian Bogor e. Alamat Rumah/No HP : Jalan Babakan Tengah No.93/082133292991 f. Alamat Email : [email protected] 4. Anggota Pelaksana Kegiatan : 2 orang 5. Dosen Pendamping a. Nama Lengkap dan Gelar: Dr. Ir. Naresworo Nugroho, MS b. NIP : 19650122 198903 1 002 c. Alamat Rumah : Jalan Beringin V Blok B5/No.7 Taman Pagelaran Ciomas, Bogor 16610. d. No. Telp/HP : 0251 8635541/08121100132 Bogor, 21 Maret 2011 Menyetujui Ketua Departemen Teknologi Hasil Hutan Ketua Pelaksana Kegiatan Dr. Ir. I Wayan Darmawan MS Achmad Solikhin NIP. 19660212 199103 1 002 NIM. E24090040 Wakil Rektor Bidang Akademik Dosen Pendamping dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS Dr. Ir. Naresworo Nugroho, MS NIP. 19581228 198503 1 003 NIP. 19650122 198903 1 002 iii KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan program kreativitas mahasiswa yang berupa gagasan tertulis dengan judul “Pemanfaatan Lerak (Sapindus rarak DC) sebagai Sabun Nabati Ramah Lingkungan”. -

Th20 21 Thesis
Horticultural harvest waste as an alternative feed with anti- methanogenic properties for ruminants: In vitro evaluation Amriana Hifizah (Master in Animal Science and Nutrition) This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy of The University of Western Australia School of Agriculture and Environment 2019 THESIS DECLARATION I, Amriana Hifizah, certify that: This thesis has been substantially accomplished during enrolment in this degree. This thesis does not contain material which has been submitted for the award of any other degree or diploma in my name, in any university or other tertiary institution. In the future, no part of this thesis will be used in a submission in my name, for any other degree or diploma in any university or other tertiary institution without the prior approval of The University of Western Australia and where applicable, any partner institution responsible for the joint-award of this degree. This thesis does not contain any material previously published or written by another person, except where due reference has been made in the text and, where relevant, in the Authorship Declaration that follows. This thesis does not violate or infringe any copyright, trademark, patent, or other rights whatsoever of any person. The research involving fistulated sheep reported in this thesis was assessed and approved by The University of Western Australia Animal Ethics Committee. Approval #: (RA/3/100/1424), according to the recommendation of The Australian National Health and Medical Research Council. This thesis contains published work and/or work prepared for publication, some of which has been co-authored. Signature: Date: 17 July 2019 ii ABSTRACT Ruminants produce a significant amount of methane as a by-product of ruminal fermentation, thus contributing to greenhouse gas emissions. -

Sapindus Mukorossi
The Pharma Innovation Journal 2018; 7(5): 470-472 ISSN (E): 2277- 7695 ISSN (P): 2349-8242 NAAS Rating: 5.03 Sapindus mukorossi: A review article TPI 2018; 7(5): 470-472 © 2018 TPI www.thepharmajournal.com Anjali, Rita Saini and Divya Juyal Received: 05-03-2018 Accepted: 06-04-2018 Abstract Anjali Sapindus mukorossi, well known as soapnut, belong to family Sapindaceae. It is popular ingredient of Himalayan Institute of ayurvedic preparation such as shampoo, cleansers and medicine for treatment of eczema, psoriasis and Pharmacy and Research for removing for removing freckles and also have gentle insecticidal property and traditionally used for Atak-farm, Rajawala, Dehradun, removing lice from the scalp. The species is widely grown in upper reaches of the Indo-Gangetic plains, Uttarakhand, India Shivaliks and sub-Himalayan tracts at altitudes from 200m to 1500m. It is also called as Soapnut or Aritha tree, it is most valuable trees of tropical and sub-tropical region of Asia. Rita Saini Himalayan Institute of Pharmacy and Research Keywords: Sapindus mukorossi, antifungal, antibacterial Atak-farm, Rajawala, Dehradun, Uttarakhand, India Introduction Sapindus mukorossi, is also known as ‘soapnut’ or ‘aitha’, belong to family Sapindaceae. It is Divya Juyal use medicinally as an expectorant, contraceptives, and for cure of excessive salivation, Himalayan Institute of Pharmacy and Research epilepsy, chlorosis and migraine. It is also a popular ingredient for ayurvedic preparation such Atak-farm, Rajawala, Dehradun, as shampoo, cleansers and medicine for cure of eczema, psoriasis and for removing freckles Uttarakhand, India and also have moderate insecticidal property and traditionally used for removing lice from the scalp [1-3]. -

Phytochemical Analysis, Bioassays and the Identification of Drug Lead Compounds from Seven Bhutanese Medicinal Plants Phurpa Wangchuk University of Wollongong
University of Wollongong Research Online University of Wollongong Thesis Collection University of Wollongong Thesis Collections 2014 Phytochemical analysis, bioassays and the identification of drug lead compounds from seven Bhutanese medicinal plants Phurpa Wangchuk University of Wollongong Recommended Citation Wangchuk, Phurpa, Phytochemical analysis, bioassays and the identification of drug lead compounds from seven Bhutanese medicinal plants, Doctor of Philosophy thesis, School of Chemistry, University of Wollongong, 2014. http://ro.uow.edu.au/theses/4076 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Phytochemical Analysis, Bioassays and the Identification of Drug Lead Compounds from Seven Bhutanese Medicinal Plants A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the award of the degree DOCTOR OF PHILOSOPHY from UNIVERSITY OF WOLLONGONG1 Phurpa Wangchuk M.Sc. Medicinal Chemistry (Research), Post Graduate Diploma (Research Methodology), B.Sc. (Bioscience), Graduate Certificate (Administrative Management). Supervisors: Prof. Stephen G. Pyne and A/Prof. Paul A. Keller School of Chemistry University of Wollongong, Australia 2014 1 Copyright: University of Wollongong, 2014. 1 DECLARATION The ideas and the materials of this thesis, submitted in fulfillment of the requirements for the award of the Doctorate of Philosophy, in the School of Chemistry, University of Wollongong, are entirely of my own work and creation unless otherwise referenced or acknowledged. This document has not been submitted for qualifications at any other academic institutions. Phurpa Wangchuk 25th February 2014 i ACKNOWLEDGEMENTS This PhD has been a journey of life-changing experience. The achievements and successes that I have managed to accumulate were made possible by the tirelessness and the selflessness of my two great supervisors: Professor Stephen Pyne and A/Professor Paul Keller.