R.ARDIAN DWI ROY S.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pengembangan Strategi Kemitraan Perguruan Tinggi, Industri, Dan Pemerintah Di Indonesia
Pengembangan Strategi Kemitraan Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah di Indonesia Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) Pengembangan Strategi Kemitraan Perguruan Tinggi, Industri, dan Pemerintah di Indonesia Diterbitkan oleh: Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP) Gedung E lantai 19, Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Tel: +62-21-578-511000, Fax: +62-21-578-51101 Website: www.acdp-indonesia.org Email Sekretariat: [email protected] Dicetak pada bulan Oktober 2013 Pemerintah Republik Indonesia (yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Pemerintah Australia melalui Australian Aid (AusAID), Uni Eropa (UE) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah membentuk Kemitraan Pengembangan Kapasitas dan Analisis Sektor Pendidikan (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership/ACDP). ACDP adalah fasilitas untuk mendorong dialog kebijakan dan memfasilitasi reformasi kelembagaan dan organisasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan untuk mengurangi kesenjangan kinerja pendidikan. Fasilitas ini merupakan bagian integral dari Program Pendukung Sektor Pendidikan (Eduction Sector Support Program/ESSP). Dukungan UE terhadap ESSP juga termasuk dukungan anggaran sektor dan program pengembangan kapasitas tentang Standar Pelayanan Minimum. Dukungan Pemerintah Australia adalah melalui Kemitraan Pendidikan Australia dengan Indonesia. -

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jl
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Jl. Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: (021) 57946100 ext. 0433; Faks. (021) 5731846 Laman: http://dikti.go.id Nomor : 1389/E5.2/PL/2012 21 Mei 2012 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Pemberitahuan Hasil Seleksi Evaluasi Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2012 Kepada Yth. : Ketua LP/LPPM Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (terlampir) Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah melakukan Desk Evaluasi Proposal baru Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk dibiayai tahun 2012 dengan hasil sebagaimana tersebut pada lampiran. Sejalan dengan itu kami mohon perhatian Saudara terhadap beberapa hal sebagai berikut : 1. Penelitian tersebut baru dapat dibiayai apabila Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dengan para dosen/peneliti penerima Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), telah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Ketua Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi penerima hibah penugasan tersebut; 2. Untuk itu bersama ini kami sampaikan format Daftar Isian Surat Permintaan Pembayaran Hibah Penelitian untuk diisi (harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas) dan di fax kepada kami melalui nomor 021- 5731846 atau 021-57946085. Asli -

Developing Strategies for University, Industry and Government Partnership
Developing Strategies for University, Industry, and Government Partnership in Indonesia Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Developing Strategies for University, Industry, and Government Partnership in Indonesia Published by: Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Agency for Research and Developments (Balitbang), Ministry of Education and Culture Building E 19th Floor Jl. Jendral Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Tel: +62-21-578-511000, Fax: +62-21-578-51101 Website: www.acdp-indonesia.org Secretariat Email: [email protected] Printed in October 2013 The Government of Indonesia (represented by the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Religious Affairs, and the Ministry of National Development Planning / BAPPENAS), the Government of Australia, through Australian Aid, the European Union (EU) and the Asian Development Bank (ADB) have established the Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP). ACDP is a facility to promote policy dialogue and facilitate institutional and organizational reform to underpin policy implementation and to help reduce disparities in education performance. The facility is an integral part of the Education Sector Support Program (ESSP). EU’s support to the ESSP also includes a sector budget support along with a Minimum Service Standards capacity development program. Australia’s support is through Australia’s Education Partnership with Indonesia. This report has been prepared with grant support provided by AusAID and the EU through ACDP. KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN EUROPEAN UNION DAN KEBUDAYAAN AGAMA The institutions responsible for implementation of the study were PT. TRANS INTRA ASIA in cooperation with the Institute of Public Administration of Canada (IPAC). The members of the study team who prepared this report were: 1. -

Daftar Fasilitas Asuransi Kesehatan Tingkat Pertama
DAFTAR FASILITAS ASURANSI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PROVINSI KANTOR REGIONAL KANTOR CABANG NAMA DATI2 KODE PPK NAMA PPK ALAMAT PPK TELF. PPK N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 00080010 KLINIK POLRES ACEH BARAT SWADAYA N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 00080011 KLINIK POLRES ACEH BESAR IMBRAHIM SAIDI NO. 1 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 00080012 KLINIK SPN SEULAWAH BANDA ACEH MEDAN KM 61 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 00080009 SIKES LANUD ISKANDARMUDA JL. PANTE PERAK BANDA ACEH N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U002 DR. IMRAN A. GANI DESA LAMTEUNGOH 85260153917 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U007 DR.MUHAMMAD ALI JL.SULTAN ISKANDAR MUDA NO.1 81269124571 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U008 KLINIK AISHA - 10 JL.T.ISKANDAR SIMPANG COT IRI 08126910292 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U004 KLINIK M.C MEULIGO BUNDA JL.B.ACEH-MEDAN 10LR.REFORMASI 06517413589 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U005 KLINIK MEURASI LAMBARO JL.BANDA ACEH-MEDAN KM 4,5 0811684550 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U001 DR. FIA DEWI AULIANI, MARS Jl.BANDA ACEH-MEDAN KM 25 0651-92195 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U010 KLINIK AISHA - 07 JL. BANDA ACEH-MEULABOH 08126910292 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. -

Jurnal Penelitian Fisika Dan Aplikasinya (JPFA)
Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA) Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA) - Journal of Physics Research and Its Application is a peer- reviewed journal that is managed by Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Negeri Surabaya and published by Universitas Negeri Surabaya in collaboration with Perkumpulan Pendidik IPA Indonesia (PPII). JPFA is published periodically (twice a year) in June and December.JPFA is available for free (open access) to all readers. The articles in JPFA include developments and researches in Physics Education, Classical Physics, and Modern Physics (theoretical studies, experiments, and its applications). Person in Charge Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya Editor in Chief Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. Editorial Advisory Board Prof. Rajesh Sharma, Ph.D., Arkansas State University, United States Prof. Dr. Wolfgang W Schmahl, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Germany Prof. Madya Dr. Hishamuddin Zainuddin, University Putra Malaysia, Malaysia Assc.Prof. Dr. Muhaimin Ismoen, Universiti Teknologi Brunei, Brunei Darussalam Assc.Prof. Dr. Chih-Hsiung Ku, National Dong Hwa University, Taiwan Assc.Prof. Dr. Massimo Brescia, INAF Astronomical Observatory of Capodimonte, Italy Assc.Prof. Simona Condurache-Bota, Ph.D., Dunarea de Jos University of Galaţi, Romania Prof. Dr. Agus Subekti, Universitas Jember (UJ), Indonesia Prof. Dr. Arif Hidayat, Universitas Negeri Malang (UM), Indonesia Prof. C Cari, Ph.D., Universitas Sebelas Maret, Indonesia Dr. P Parmin, Universitas Negeri Semarang, Indonesia Dr. Ade Gafar Abdullah, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia Prof. Dr. M Madlazim, Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Indonesia Managing Editor Utama Alan Deta, S.Pd., M.Pd., M.Si. -

479 DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku A. Hasymi Ali , Agus
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku A. Hasymi Ali , Agus Subekti, Wardana, 2002, Kamus Asuransi, Bumi Aksara, , Jakarta, hal. 282 dan Emmy Pangaribuan Simajuntak, 1980, Pertanggungan wajib/sosial, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajahmada YogyakartaSri Redjeki Hartono, 1990, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, A. Hasymi Ali, 2002, Pengantar Asuransi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, A.J. Mainake, 1959, Merenungkan Hubungan antara Individu dan Negaea berhubung dengan Kedudukan (posisi) Hukum Privat pada waktu sekarang, Majalah Padjadjaran, FH UNPAD, Abbas Salim, Asuransi dan Manejemen risiko, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), Abdul Kadir Muhamad, Hukum Asuransi Indonesia, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, Abdul Majid dan Sri Edi Swasono, 1992, Wawasan Ekonomi Pancasila, UI Pres, Jakarta, Abdul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, (Medan; Fakultas Hukum USU, 2005), Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya bakti, Bandung, Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2006 Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, Akademika Pressindo, Jakarta, Agus Prawoto, 1995, Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital, (RBC). BPFE, Yogyakarta, Agus Prawoto, 2003, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC), BPFE, Yogyakarta, Ahmad Warson Munawir, 1984, Kamus Munawir Arab-Indonesia, Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir, -

Reforming Research in Indonesia: Policies and Practice Dr
Global Development Network Working Paper Series Reforming Research in Indonesia: policies and practice Dr. Inaya Rakhmani and Fajri Siregar Working Paper No. 92 February 2016 Supported by The Global Development Network (GDN) is a Public International Organization that promotes social science in developing and transition countries. It empowers local researchers by giving them access to financial resources, to information, to training and mentoring services and to a global network of development researchers. Through its various projects, it contributes to the generation of policy-relevant knowledge on major development issues, and to the interaction between local researchers, their global peers, policymakers and other development stakeholders. Founded in 1999, GDN headquarters are in New Delhi, India with an office in Washington DC, USA. This research was funded by GDN, jointly carried out by the Communication Research Centre, University of Indonesia (Puskakom UI) and the Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), and in collaboration with the Asia Research Centre, Murdoch University, Australia (ARC). This Research Report has been prepared as part of the pilot phase of Doing Research, A GDN initiative to develop a comprehensive understanding of the factors that influence the organization of social science research, its quality, quantity and relevance for developing countries. The Report is part of a series of pilot case studies that investigated the research environment in 11 developing and transition countries. More information can be found at www.gdn.int/dr. © GDN, 2016 Reforming Research in Indonesia: Policies and Practices EXECUTIVE SUMMARY Dr. Inaya Rakhmani* It is a known fact that Indonesia continues to lag behind its Southeast Asian neighbours in terms Fajri Siregar** of international publications, particularly in the social sciences and humanities (Evers, 2003). -
PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PEMBELAJARANNYA IV 27 Maret 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta
P-ISSN: 2502-6526 E-ISSN: 2656-0615 PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PEMBELAJARANNYA IV 27 Maret 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta “Meningkatkan Literasi Matematika untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.” Surakarta, 27 Maret 2019 Penyelenggara: Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019 i PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PENELITIAN DAN PEMBELAJARANNYA IV 27 Maret 2019 Universitas Muhammadiyah Surakarta Artikel-artikel dalam prosiding ini telah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Penelitian dan Pembelajarannya IV pada tanggal 27 Maret 2019 di Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019 Tim Reviewer Artikel Seminar: 1. Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si. Universitas Sriwijaya 2. Dr. Makbul Muksar Universitas Negeri Malang 3. Dr. Rahmah Johar, M.Pd. Universitas Syiah Kuala 4. Dr. Yoppy Wahyu Purnomo, M.Pd. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka 5. Dyana Wijayanti, Ph.D. Universitas Sultan Agung 6. Dr. Wahidah Sanusi, M.Si. Universitas Negeri Makassar 7. Muhtarom, M.Pd. Universitas PGRI Semarang 8. Wahid Yunianto, M.Sc., M.A. SEAMEO Qitep in Mathematics 9. Ahmad Wachidul Kohar, M.Pd. Universitas Negeri Surabaya 10. Herani Tri Lestiana, M.Sc. IAIN Syekh Nurjati Cirebon 11. Febi Sanjaya, M.Sc. Universitas Sanata Dharma 12. Dian Ariesta Yuwaningsih, M.Sc. Universitas Ahmad Dahlan 13. Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom. Universitas Muhammadiyah Surakarta 14. Prof. Dr. Sutama, M.Pd. Universitas Muhammadiyah Surakarta 15. Dr. Sumardi, M.Si. Universitas Muhammadiyah Surakarta 16. Idris Harta, MA., Ph.D. Universitas Muhammadiyah Surakarta 17. Drs. Slamet Hw., M.Pd. Universitas Muhammadiyah Surakarta 18. -
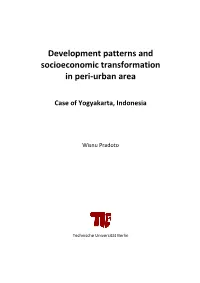
Development Patterns and Socioeconomic Transformation in Peri-Urban Area
Development patterns and socioeconomic transformation in peri-urban area Case of Yogyakarta, Indonesia Wisnu Pradoto Technische Universität Berlin ISBN 978-3-7983-2430-5 (Printing-version) ISBN 978-3-7983-2431-2 (Online-version) Berlin 2012 D 83 ∞ Printed on acid-free permanent paper Druck/ docupoint GmbH Magdeburg Printing: Otto-von-Guericke-Allee 14, 39179 Barleben Vertrieb/ Universitätsverlag der TU Berlin Publisher: Universitätsbibliothek Fasanenstr. 88 (im VOLKSWAGEN-Haus), D-10623 Berlin Tel.: (030) 314-76131; Fax: (030) 314-76133 E-Mail: [email protected] http://www.univerlag.tu-berlin.de Contents Contents i Acknowledgement v List of Tables vii List of Figures viii Abstract x Zusammenfassung xi Chapter 1 Introduction: The peri-urban as a new contested arena of urban development 1 1.1. Major related issue 1 1.2. Significance of the study 4 1.3. Theoretical standpoint 6 1.4. Research questions and scope of investigation 7 1.5. Conceptual and methodological approach 9 1.6. Limitation of the works 9 1.7. Chapter outline 11 Chapter 2 Peri-urban development and its implications for governance: a theoretical framework 14 2.1. Urbanization in developing countries and the dynamics of migration 14 2.1.1. Urban growth and urban transformation 15 2.1.2. The determinant of urban and regional changes 19 2.2. Peripheral urbanization and transforming rural spaces 20 2.2.1. Peri-urbanization: a concept and a pattern of development 22 2.2.2. Rural-urban economy and agricultural livelihood changes 24 2.2.3. Settlement transformation and the emerging socio-spatial segregation 25 2.3. -

KEBANGKITAN MARITIM INDONESIA Masih Banyak Lagi Artikel Menarik Yang Dapat Anda Simak Di Majalah DERMAGA Kali Ini
Siapkah SDM BUMN Barito Equator, Islam di Bali, FREE MAGAZINE menghadapi MEA 2015? Sang Penjaga Alur Barito Bukti Toleransi Edisi 199 - Juni 2015 KEBANGKITANKEBANGKITAN MARITIMMARITIM INDONESIAINDONESIA Marhaban Ya RamadhanBulan Penuh Rahmat, Hidayat, dan Ampunan Bersihkan diri dengan mematuhi perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya Melatih diri untuk menyempurnakan jiwa dengan keihklasan dan kejujuran Apa kabar pembaca? Edisi 199 | Juni 2015 Bulan Ramadhan yang penuh berkah telah tiba. Alhamdulillah kita masih Pelindung Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadhan penuh berkah di tahun ini. Bulan penuh ampunan, bulan bertabur amal dan pahala, bulan Pengarah Sekretaris Perusahaan yang lebih baik dari seribu bulan dan masih banyak lagi sebutan indah untuk Ramadhan. Umat muslim di seluruh dunia bersuka cita menyambut Pemimpin Redaksi Edi Priyanto bulan indah ini. Bismillah ... dengan niat yang tulus marilah kita jalani dan sambut Ramadhan hingga saat kemenangan tiba. Redaktur Pelaksana Camelia Ariestanti Edisi Juni 2015 ini sarat dengan agenda peresmian proyek APBS dan Koordinator Liputan & Fotografi Terminal Teluk Lamong pada akhir Mei lalu oleh Presiden Joko Widodo. R. Suryo Khasabu Pelabuhan yang memiliki nama lain Terminal Multipurpose Teluk Lamong Administrasi itu disebut sebagai bandar logistik paling modern di Indonesia saat Ardella Trastiana Dewi ini. Pelabuhan Teluk Lamong dibangun sejak 2010 dan mulai beroperasi Koordinator Distribusi dalam skala percobaan pada akhir 2014 silam. Hafidz Novalsyah Beberapa keunggulan pelabuhan petikemas tersebut, di antaranya adalah Alamat Redaksi Jl. Perak Timur 610 Surabaya 60165 Indonesia bersifat semiotomatis. Pelabuhan Teluk Lamong disebut beroperasi secara Telp : +62 (31) 3298631 - 3298637 semiotomatis karena alat pemindah kontainer atau crane dioperasikan Fax : +62 (31) 3295204 ; 3295207 dari jarak jauh melalui ruang kendali. -

Pusdalops Kepala Pelaksana Kasubdit No Prov/Kab
KONTAK BPBD PROVINSI / KABUPATEN / KOTA UPDATE DESEMBER 2018 NOMOR KONTAK NO PROV/KAB/ KOTA ALAMAT NO TELEPON KANTOR PUSDALOPS KEPALA PELAKSANA KASUBDIT Telp. 0651-34783 Pusdalops : 0813-6066-9111 Kasidar Ibnu Sakdan 0853-6013-5354 Bu Anri Pusdalops 0853-7048- Kasubag program Bp. Fadmi Ridwan Fax. 0651-34783 2106 SP, MA 0812-8974-468 Jl. Teuku Daud Beureueh No. Web : Pusdatin Ibu Henni Kasi Kesiapsiagaan Bp Fadly ACEH 18, Banda Aceh Kode Pos : http://bpba.acehprov.go.id/ 081377087000 Ir. Yusmadi, MM - 081362359661 081362601267 23121 Email : [email protected] / Balian Staff Pusdalops 0821- [email protected] 6313-6885 Email : Kasi Log Bp Teuku Izrialsyah [email protected] 081263026260 Telp. 0655-7551-413 Pusdalops 0822-6150-7858 Jl. Beringin Maju, Seuneubok, T. Syahluna Polem Sekretaris Bp Edison 0852-1092-0909 0852-7723-6569 1 Kab. Aceh Barat Johan Pahlawan, Kab. Aceh Email : Email : Barat, 23615 [email protected] pusdalops.bpbdacehbarat@gma Kasi Kedaruratan Bp Benny Hardi Web : www.acehbaratkab.go.id il.com 0813-6252-0077 Telp. (0659)-92929 Empi Sabril (Sekretaris) Fax. 0659-91647 Kab. Aceh Barat Jln. Iskandar Muda, Amiruddin 0813-6019-6823 / 2 web : Kode pos 23764 0853-5848-1111 Daya http://bpbk.acehbaratdayakab.go. Email : 0853-6157-9916 [email protected] d / [email protected] Telp. 0651-92071 Pusdalops Bp. Iqbal Kabid Pencegahan Bp Bahtiar 0853-7196-4442 / 0852-6095-9554 081-360-097776 Fax. 0651-92071 Jln. Bachtiar Panglima Polim, Ridwan Jamil, S.Sos., M.Si 3 Kab. Aceh Besar SH Kota Janto 23914 Email : [email protected] / 0812-6942-570 Kabid RR Bp. -

Reviewer Penelitian Nasional 2020
Lampiran I Nomor : B/1135/E3/RA.00/2020 Tanggal : 12 November 2020 Daftar Undangan Persamaan Persepsi Seleksi Substansi Proposal Penelitian Senin, 16 November 2020 No. Nama Reviewer Instansi 1 A HARIS BUDI WIDODO Universitas Jenderal Soedirman 2 ABDUL M SIBUEA Universitas Negeri Medan 3 ABRAHAM LOMI Institut Teknologi Nasional Malang 4 ABU BAKAR Universitas Hasanuddin 5 ADIT KURNIAWAN Institut Teknologi Bandung 6 AGOES ACHMAD MASROERI Institut Teknologi Sepuluh Nopember 7 AGOES SOEGIANTO Universitas Airlangga 8 AGUS SUBEKTI Universitas Jember 9 AGUS ULINUHA Universitas Muhammadiyah Surakarta 10 AGUS ZAINAL ARIFIN Institut Teknologi Sepuluh Nopember 11 AKHMAD FAUZY Universitas Islam Indonesia 12 AKHMAD KHARIS NUGROHO Universitas Gadjah Mada 13 AKHMAD SABARUDIN Universitas Brawijaya 14 AMAT MUKHADIS Universitas Negeri Malang 15 AMRI Universitas Syiah Kuala 16 ANAK AGUNG GEDE NGURAH Universitas Merdeka Malang 17 ANDI ALADIN Universitas Muslim Indonesia 18 ANNYTHA INA ROHI DETHA Universitas Nusa Cendana 19 ANTHON FREDDY SUSANTO Universitas Pasundan 20 ARIEF RACHMANSYAH Universitas Brawijaya 21 ARIEF SUBYANTORO Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 22 ARIF MUNTASA Universitas Trunojoyo 23 B.M. BACHTIAR Universitas Indonesia 24 BADARUDDIN Universitas Sumatera Utara 25 BAMBANG HERU BUDIANTO Universitas Jenderal Soedirman 26 BAMBANG JATMIKO Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 27 BENYAMIN LAKITAN Universitas Sriwijaya 28 BERRY JULIANDI Institut Pertanian Bogor 29 BUDI SURYADI Universitas Lambung Mangkurat 30 CHOLIS SA'DIJAH Universitas