Relief Dan Arca Candi Singosari - Jawi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Indonesia Insights
Indonesia Insights CELESTIAL VOYAGERS, Inc 27-28 Thomson Ave., Suite WS 11, Long Island City, NY 11101 Tel: +1 212-203-1021 www.celestialvoyagers.com May 27 - June 10, 2020 Indonesia Insights: Java, Bali, & Lombok DAY 1&2 WEDNESDAY, THURSDAY MAY 27, 28 DEPARTURE & TRAVEL TIME Trip price $3250- per person Departure from JFK. SQ#25 leaves JFK AT 8:55 PM from terminal 4. Single room supplement + $520. - DAY 3 FRIDAY MAY 29 JAKARTA, JAVA (D) Arrival Singapore at 6:50 AM. Connection with SQ # 952 lv. at 7:40 AM, arr. Jakarta 8:25 AM. Assistance,guided city tour, check-in at hotel for 1 night. Dinner at Padang Restaurant. DAY 4 SATURDAY MAY 30 YOGYAKARTA TEMBI JAVA(B, L, D) This price includes: Morning flight to Yogyakarta. On arrival drive to Domah Yogya Hotel in the village of Tembi. Check-in for 4 nights. Rest ● International flights from JFK with Singapore Airlines after lunch. Signature Rijsttafel Dinner with traditional music. ● Domestic flights within Indonesia DAY 5 SUNDAY MAY 31 YOGYAKARTA / TEMBI, JAVA (B, D) ● 11 nights hotel accommodation with double occupancy Full day guided tour: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Palace of Yogyakarta, Tamansari Watercastle. Lunch at ● Buffet breakfast daily Sentra Gudeg Wijilan (not included); Malioboro street to explore stalls and shops. Return for dinner at Domah Yogya. ● 3 Lunches and 8 dinners as per itinerary DAY 6 MONDAY JUNE 1 PRAMBANAN / TEMBI. JAVA (B, D) ● All sightseeing and entrance fees as per itinerary Morning guided tour: Prambanan Temple and Candi Rato Boko ruins. Return to Domah Yogya for lunch (not included). -
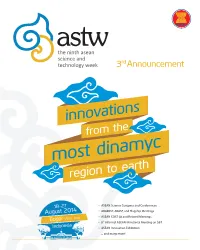
Astw Announcement CETAK FINAL
ASEAN Science Congress and Conferences ABAPAST, ABASF, and Flagship Meetings ASEAN COST 68 and Related Meetings 8th Informal ASEAN Ministerial Meeting on S&T ASEAN Innovation Exhibition ... and many more! Contents Background 05 Schedule of Activities 08 The 4th Science Congress and Conferences 10 Flagship Programs, SCIRD, ABAPAST, ABASF Meetings 11 The 68th ASEAN COST Meeting 11 ASEAN COST + Dialoguse Partner’s Meeting(s) 12 The 8th Informal Ministerial Meeting on S&T (8th IAMMST) 12 ASEAN S&T Awards 13 ASEAN STI Exhibition 15 9th ASTW - IIASA Joint Seminar 18 ASEAN Youth Science Summit (AYSS) 19 ASTW - APEC PPSTI Joint Workshop 20 ASTW - FEALAC Joint Workshop 21 Workshop on Biosecurity 22 Venue & Proposed Hotels 25 3 The Bogor Palace (Indonesian:Istana Bogor) - one of 6 Presidential Palaces in Indonesia. Courtesy : bp.blogspot.com innovations from the most dynamic region to earth INNOVATIONS FROM THE MOST DYNAMIC REGION TO EARTH The ASEAN S&T Week (ASTW) is a flagship project of the ASEAN COST, in order to showcase major achievements and potential of S&T generated both in ASEAN Member Countries and Dialogue Partners, relevant to the rapidly increasing needs of the public and private sectors, in light of the region's goal of achieving a knowledge-based economy. The ASTW is an important event of the ASEAN COST and it is conducted triennially in a rotational basis amongst ASEAN Member Countries, which has the main purpose of promoting of S&T Development in Southeast Asian Countries. In addition, it is expected that this event will open windows of opportunities for scientist, technologies, researchers, academicians, government officials, practitioners and private sectors, to interact and to promote networking, as well as to expand their S&T cooperation. -

From the Jungles of Sumatra and the Beaches of Bali to the Surf Breaks of Lombok, Sumba and Sumbawa, Discover the Best of Indonesia
INDONESIAThe Insiders' Guide From the jungles of Sumatra and the beaches of Bali to the surf breaks of Lombok, Sumba and Sumbawa, discover the best of Indonesia. Welcome! Whether you’re searching for secluded surf breaks, mountainous terrain and rainforest hikes, or looking for a cultural surprise, you’ve come to the right place. Indonesia has more than 18,000 islands to discover, more than 250 religions (only six of which are recognised), thousands of adventure activities, as well as fantastic food. Skip the luxury, packaged tours and make your own way around Indonesia with our Insider’s tips. & Overview Contents MALAYSIA KALIMANTAN SULAWESI Kalimantan Sumatra & SUMATRA WEST PAPUA Jakarta Komodo JAVA Bali Lombok Flores EAST TIMOR West Papua West Contents Overview 2 West Papua 23 10 Unique Experiences A Nomad's Story 27 in Indonesia 3 Central Indonesia Where to Stay 5 Java and Central Indonesia 31 Getting Around 7 Java 32 & Java Indonesian Food 9 Bali 34 Cultural Etiquette 1 1 Nusa & Gili Islands 36 Sustainable Travel 13 Lombok 38 Safety and Scams 15 Sulawesi 40 Visa and Vaccinations 17 Flores and Komodo 42 Insurance Tips Sumatra and Kalimantan 18 Essential Insurance Tips 44 Sumatra 19 Our Contributors & Other Guides 47 Kalimantan 21 Need an Insurance Quote? 48 Cover image: Stocksy/Marko Milovanović Stocksy/Marko image: Cover 2 Take a jungle trek in 10 Unique Experiences Gunung Leuser National in Indonesia Park, Sumatra Go to page 20 iStock/rosieyoung27 iStock/South_agency & Overview Contents Kalimantan Sumatra & Hike to the top of Mt. -

Challenges in Conserving Bahal Temples of Sri-Wijaya Kingdom, In
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-9, Issue-1, October 2019 Challenges in Conserving Bahal Temples of Sriwijaya Kingdom, in North Sumatra Ari Siswanto, Farida, Ardiansyah, Kristantina Indriastuti Although it has been restored, not all of the temples re- Abstract: The archaeological sites of the Sriwijaya temple in turned to a complete building form because when temples Sumatra is an important part of a long histories of Indonesian were found many were in a state of severe damage. civilization.This article examines the conservation of the Bahal The three brick temple complexes have been enjoyed by temples as cultural heritage buildings that still maintains the authenticity of the form as a sacred building and can be used as a tourists who visit and even tourists can reach the room in the tourism object. The temples are made of bricks which are very body of the temple. The condition of brick temples that are vulnerable to the weather, open environment and visitors so that open in nature raises a number of problems including bricks they can be a threat to the architecture and structure of the tem- becoming worn out quickly, damaged and overgrown with ples. Intervention is still possible if it is related to the structure mold (A. Siswanto, Farida, Ardiansyah, 2017; Mulyati, and material conditions of the temples which have been alarming 2012). The construction of the temple's head or roof appears and predicted to cause damage and durability of the temple. This study used a case study method covering Bahal I, II and III tem- to have cracked the structure because the brick structure ples, all of which are located in North Padang Lawas Regency, does not function as a supporting structure as much as pos- North Sumatra Province through observation, measurement, sible. -

Bělahan and the Division of Airlangga's Realm
ROY E. JORDAAN Bělahan and the division of Airlangga’s realm Introduction While investigating the role of the Śailendra dynasty in early eastern Javanese history, I became interested in exploring what relationship King Airlangga had to this famous dynasty. The present excursion to the royal bathing pla- ce at Bělahan is an art-historical supplement to my inquiries, the findings of which have been published elsewhere (Jordaan 2006a). As this is a visit to a little-known archaeological site, I will first provide some background on the historical connection, and the significance of Bělahan for ongoing research on the Śailendras. The central figure in this historical reconstruction is Airlangga (991-circa 1052 CE), the ruler who managed to unite eastern Java after its disintegration into several petty kingdoms following the death of King Dharmawangśa Těguh and the nobility during the destruction of the eastern Javanese capital in 1006 (Krom 1913). From 1021 to 1037, the name of princess Śrī Sanggrāmawijaya Dharmaprasādottunggadewī (henceforth Sanggrāmawijaya) appears in sev- eral of Airlangga’s edicts as the person holding the prominent position of rakryān mahāmantri i hino (‘First Minister’), second only to the king. Based on the findings of the first part of my research, I maintain that Sanggrāmawijaya was the daughter of the similarly named Śailendra king, Śrī Sanggrāma- wijayottunggavarman, who was the ruler of the kingdom of Śrīvijaya at the time. It seems plausible that the Śailendra princess was given in marriage to Airlangga to cement a political entente between the Śailendras and the Javanese. This conclusion supports an early theory of C.C. -

Candi Cangkuang
Direktori Pariwisata Indonesia Kementerian Pariwisata Republik Indonesia https://wisatasia.com Candi Cangkuang Kawasan JAWA BARAT Kabupaten Garut, Jawa Barat Candi Cangkuang termasuk ke dalam wilayah Kampung Ciakar, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles. Secara geografis beradapada koordinat 7º 06’ 067” LS 107º 55’168”. Untuk mencapai Candi Cangkuang bisa naik bus atau elf jurusan Bandung-Garut, berhenti di alun-laun Leles, kemudian dilanjutkan dengan naik delman atau ojeg, atau berjalan kaki sejauh 3 Km. Candi Cangkuang terletak di puncak bukit kecil di Pulau Panjang yang dikelilingi danau “Situ” Cangkuang, namun karena adanya pendangkalan pada sebagian danau maka salah satu sisinya menyatu dengan tanah di sekitar. Selain candi, ditemukan pula makam Arif Muhammad yang letaknya berdampingan dengan candi dan masih di areal Pulo Panjang ini terdapat pemukiman masyarakat adat Pulo. Nama Candi Cangkuang diambil dari nama Desa Cangkuang tempat dimana candi tersebut ditemukan, namun ada yang berpendapat bahwa Cangkuang adalah nama tumbuhan/pohon Cangkuang yang banyak tumbuh di kawasan tersebut. Candi Cangkuang ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 berkat usaha penelusuran oleh ahli purbakala Drs. Uka Tjandrasasmita terhadap buku Notulen Bataviach Genoot Schap yang ditulis oleh orang Belanda bernama Vorderman tahun 1893. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa di Desa Cangkuang terdapat makam kuna Arif Muhammad dan 1 / 2 Direktori Pariwisata Indonesia Kementerian Pariwisata Republik Indonesia https://wisatasia.com sebuah arca siwa. Penelitian tahun 1967/1968 dengan cara penggalian di sekitar daerah tersebut menemukan pondasi kaki candi dan serakan batu bahkan oleh penduduk digunakan sebagai nisan makam. Pada tahun 1974 -1976 dilakukan pemugaran (rekonstruksi) bangunan candi yang dilaksanakan oleh proyek Pembinaan Kepurbakalaan dan Peninggalan Nasional Depdikbud dan hasilnya seperti sekarang ini dan makam Arif Muhammad yang terletak di sebelah candi. -

Report on Biodiversity and Tropical Forests in Indonesia
Report on Biodiversity and Tropical Forests in Indonesia Submitted in accordance with Foreign Assistance Act Sections 118/119 February 20, 2004 Prepared for USAID/Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No. 3-5 Jakarta 10110 Indonesia Prepared by Steve Rhee, M.E.Sc. Darrell Kitchener, Ph.D. Tim Brown, Ph.D. Reed Merrill, M.Sc. Russ Dilts, Ph.D. Stacey Tighe, Ph.D. Table of Contents Table of Contents............................................................................................................................. i List of Tables .................................................................................................................................. v List of Figures............................................................................................................................... vii Acronyms....................................................................................................................................... ix Executive Summary.................................................................................................................... xvii 1. Introduction............................................................................................................................1- 1 2. Legislative and Institutional Structure Affecting Biological Resources...............................2 - 1 2.1 Government of Indonesia................................................................................................2 - 2 2.1.1 Legislative Basis for Protection and Management of Biodiversity and -

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Promosi Merupakan
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Promosi merupakan suatu bentuk komunikasi yang menawarkan dan mengenalkan produk atau jasa kepada khalayak. Promosi salah satu kegiatan kehumasan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan lembaga dan untuk meningkatkan citra perusahaan. Promosi dapat menjadikan suatu usaha lebih dikenal dan diketahui oleh khalayak, dalam promosi pariwisata produk yang ditawarkan ialah berupa keindahan alam serta keunikan dari tempat wisata itu sendiri. Keuntungan yang didapat dalam melakukan kegiatan promosi diantaranya meningkatkan penjualan, mendapatkan pelanggan baru, menjaga kesetiaan pelanggan, bahkan membantu mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen, maka dengan adanya promosi pariwisata dapat menjadikan salah satu penunjang majunya suatu daerah, secara ekonomi pariwisata dapat memberikan potensi untuk membuka lapangan pekerjaan, bahkan dapat meningkatkan devisa negara. Peningkatan devisa negara dapat diperoleh dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, terutama dalam kegiatan berwisata, maka dari itu Badan Pengelola Geopark Ciletuh-Palabuhanratu sebagai instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola Geopark Nasional Ciletuh- Palabuhanratu, dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan dengan 1 2 memperbaiki sarana dan infrastruktur daerah, meningkatkan kualitas pelayanan serta memaksimalkan promosi dan pemasaran melalui berbagai media seperti iklan, website resmi, social media dan event , mengingat persaingan dalam kepariwisataan yang semakin tajam. Promosi dan pemasaran yang -

Pemanfaatan Aset Dan Pengembangan Destinasi Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan
Pemanfaatan Aset dan Pengembangan Destinasi Candi Gedong Songo, Kabupaten Semarang dalam rangka Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Artikel Ilmiah Diajukan kepada Fakultas Teknologi Informasi untuk memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pariwisata Peneliti : Agus Dhian Nugroho (732013611) Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2016 i ii iii iv v Abstrak Pariwisata merupakan salah satu devisa utama bagi sebuah negara yang bertindak di bidang jasa. Potensi wisata di Indonesia sangat beraneka ragam mulai dari potensi alam serta budaya dan bangunan bersejarah. Di Jawa Tengah khususnya memiliki beberapa potensi wisata yang patut dilirik akan potensi budaya dan bangunan bersejarah. Candi Gedong Songo adalah salah satu situs bersejarah yang mempunyai potensi wisata alam, wisata religi, sekaligus wisata budaya dan sejarah yang terdapat di dalam satu kompleks destinasi. Maka dari itu Candi Gedong Songo dinobatkan sebagai destinasi unggulan yang menjadi maskot untuk wilayah Kabupaten Semarang. Destinasi wisata ini dikunjungi oleh banyak wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing dibandingkan dengan destinasi lain yang terdapat di Kabupaten Semarang. Karena itu penelitian dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan aset dan pengembangan destinasi Candi Gedong Songo sesuai dengan prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengembangan dan pemanfaatan aset Gedong Songo telah sesuai dengan prinsip pariwisata berkelanjutan, yang diimplementasikan oleh para stakeholder di Gedong Songo. Akan tetapi ada beberapa kekurangan didalam pengelolaan dan pemanfaatan aset, yaitu beralih fungsinya Candi Gedong Songo yang awalnya digunakan sebagai destinasi wisata sejarah, budaya, dan religi menjadi wisata outbound di salah satu area yang terdapat di Kawasan Candi Gedong Songo yang nampaknya harus ditinjau ulang oleh para stakeholder agar sesuai dengan prinsip Pariwisata Berkelanjutan. -

4D3N Jakarta, Puncak Highland, 7 Angels Waterfall Bogor City, Cisarua Safari Park, Bogor Botanical Garden* Greatest Values of All
Cultural & Heritage *4D3N Jakarta, Puncak Highland, 7 Angels Waterfall Bogor City, Cisarua Safari Park, Bogor Botanical Garden* Greatest Values of All • Jakarta City Cultural Tour • 1-night stay in Bogor • 1-night stay in Puncak • Bogor Night Bazaar • Bogor Botanical Garden • Explore wildlife at Cisarua Safari Park • Sindang Raya Walking Street • Fly Paraglide at Bukit Paralayang (own cost) • 7 Angels Waterfall FREE upgrade to Excellent-Cuisine Restaurants & Private Tour* Jakarta Itinerary Day 1 Visit the cultural sites of Jakarta City TBA Arrive at Soekarno-Hatta International Airport TBA Meet & greet by tour guide at the airport’s arrival gate 1400 Explore the cultural sites of Jakarta City Snapshot photography at Sunda Kelapa Harbour Pass by Glodok Chinatown & Fatahillah Square Selfie photography at the National Monument 1600 Check-in Hotel in Jakarta for 1-night 1830 Enjoy Indonesian Set Dinner at Raja Kuring Restaurant* 2000 Shop at Grand Indonesia Mega Mall Cisarua Safari Park 2200 Explore Hard Rock Café at Plaza EX (drop off only) 2300 Before we say good night Day 2 Explore 280 species of wildlife at Cisarua Safari Park 0700 Enjoy breakfast at hotel 0800 Travel to Puncak Highland, 1h55m, 75km 1000 Explore 280 species of wildlife at Cisarua Safari Park 1230 Visit Gunung Mas Tea Plantation at Puncak Highland 1330 Enjoy Indonesia Set Lunch at Puncak Pass Restaurant* 1500 Visit Taman Bunga Nusantara 1700 Check-in Hotel in Puncak for 1-night Puncak Highland 1900 Enjoy Indonesian Set Dinner at Rindu Alam Restaurant* 2030 Shop at the -

Folklor Candi Cangkuang: Destinasi Wisata Berbasis Budaya, Sejarah, Dan Religi
FOLKLOR CANDI CANGKUANG: DESTINASI WISATA BERBASIS BUDAYA, SEJARAH, DAN RELIGI Sri Rustiyanti [email protected] Prodi Antropologi Budaya, Fakultas Budaya dan Media Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung Artikel diterima: 2 Juli 2018 Artikel direvisi: 18 Juli 2018 Artikel disetujui: 25 Juni 2018 ABSTRACT West Java has a variety of cultural, historical and religious potential that can be developed as the main tourist attraction, especially in Cangkuang Temple, Leles District, Garut Regency. Cangkuang Temple is one form of non-verbal folklore (artifact) inherited from two religions, namely Hinduism and Islam. The relics of Hinduism are the statue of Lord Shiva which is thought to date from the VIII century and the relics of Islam originated in the seventeenth century with the remains of the tomb of the Eyang Embah Dalem Arief Muhammad. The potential of Cangkuang Temple is quite interesting as one of the non-oil and gas foreign exchange tourism assets that needs to be improved in its management and empowerment. Therefore, the readiness of the Kampung Pulo community in developing tourism based on culture, history and religion still needs to be improved. Unpreparedness can be seen from the form of tourism development in each segment that has not been holistic and has not yet synergized with each other, regardless of the socio-cultural diversity of each, as well as the unclear market segments that will be targeted for development. Thus it is necessary to conduct research that aims to map the zoning of tourism development in accordance with the character of the community in the Garut Regency region. -

Bali Tours D'horizons
Bali Tours d’horizons Jours: 17 Prix: 1750 EUR Vol international non inclus Confort: Difficulté: Les incontournables Vous ne voulez rien manquer de Bali ? Voici un circuit fait pour vous. À travers ce « tour d’horizon », vous découvrirez toutes les merveilles de l’île des Dieux. Visites de temples, balades à travers d’incroyables paysages, sessions de snorkeling, matinée rafting etc., autant d’activités pour se faire plaisir et découvrir toutes les subtilités de cette île. Aussi, c’est un voyage fait de rencontres et de partage avec les habitants : partez au marché local, préparez un bon repas local accompagné d’une famille Balinaise, échangez, discutez, rigolez etc. Partez à la découverte de Bali ! Jour 1. Accueil et transfert à Ubud Aéroport de Denpasar - Ubud Arrivée à l’aéroport de Denpasar et transfert vers Ubud, une cité située sur les collines au nord de Denpasar, dans un paysage valonné de rizières verdoyantes et de ravins. Ubud est réputée pour son école de peinture. Malgré le développement touristique exponentiel qu’elle a connu ces dernières années, la cité a su préserver sa tranquillité et sa beauté. Le reste de la journée est libre. Aéroport de Denpasar Déjeuner Repas libre 40km - 1h 20m Ubud Dîner Repas libre Hébergement Hôtel 3 étoiles Jour 2. A la découverte de la culture locale Ubud - Temple de Tirta Empul Ce matin nous visitons le palais d'Ubud - complexe historique emblématique de l'histoire balinaise où residait autrefois la famille royale. Juste en face se trouve le marché artisanal, où nous pourrons trouver toutes sortes de souvenirs.