Eksistensi Dan Peranan Undagi Pangarung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
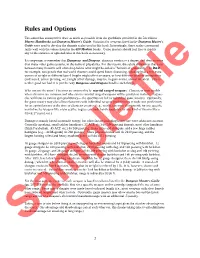
Rules and Options
Rules and Options The author has attempted to draw as much as possible from the guidelines provided in the 5th edition Players Handbooks and Dungeon Master's Guide. Statistics for weapons listed in the Dungeon Master's Guide were used to develop the damage scales used in this book. Interestingly, these scales correspond fairly well with the values listed in the d20 Modern books. Game masters should feel free to modify any of the statistics or optional rules in this book as necessary. It is important to remember that Dungeons and Dragons abstracts combat to a degree, and does so more than many other game systems, in the name of playability. For this reason, the subtle differences that exist between many firearms will often drop below what might be called a "horizon of granularity." In D&D, for example, two pistols that real world shooters could spend hours discussing, debating how a few extra ounces of weight or different barrel lengths might affect accuracy, or how different kinds of ammunition (soft-nosed, armor-piercing, etc.) might affect damage, may be, in game terms, almost identical. This is neither good nor bad; it is just the way Dungeons and Dragons handles such things. Who can use firearms? Firearms are assumed to be martial ranged weapons. Characters from worlds where firearms are common and who can use martial ranged weapons will be proficient in them. Anyone else will have to train to gain proficiency— the specifics are left to individual game masters. Optionally, the game master may also allow characters with individual weapon proficiencies to trade one proficiency for an equivalent one at the time of character creation (e.g., monks can trade shortswords for one specific martial melee weapon like a war scythe, rogues can trade hand crossbows for one kind of firearm like a Glock 17 pistol, etc.). -

Studi Tentang Keris Karya Suyanto (Kajian Tentang Estetika Dan Proses Pembuatan)
Studi tentang keris karya suyanto (kajian tentang estetika dan proses pembuatan) Oleh: Estri Ristianingrum NIM. K.3201022 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Keris merupakan benda seni dengan teknologi metalurgi tinggi yang rumit, penuh dengan sentuhan artistik serta karya yang bermutu seni yang mempunyai nilai estetika tinggi. Tidak semua orang bisa meniru dalam hal pembuatan, atau mewarisinya karena pada tiap jaman mempunyai teknik pembuatan tertentu disertai campuran bahan baku baik besi, baja, dan pamor, yang sampai sekarang masih diselimuti rahasia. Kecuali masih ada hubungan keturunan maupun keahlian dalam membuat keris ataupun memecahkan sendiri rahasia yang terkandung didalamnya melalui eksperimen pembuatan keris. Membuat keris tidaklah mudah untuk menghasilkan keris yang bermutu seni tinggi dan mempunyai nilai estetika tinggi diperlukan ritual-ritual khusus seperti menjalani laku tapa dan macam-macam latihan rohani kejawen. Selain itu membuat keris tradisional atau klasik yang sesuai dengan pribadi pemesan dan punya “isi” perlu waktu yang lama, setahun mungkin hanya bisa membuat 2-3 keris dengan biaya mahal. Ada kriteria tertentu untuk mendapatkan keris klasik atau tradisional, kriteria yang harus dipenuhi, antara lain wutuh, sepuh dan tangguh. Yang dimaksud dari kriteria tersebut adalah kondisi keris harus terlihat wutuh dengan tidak ada cacatnya, baik itu bilah, pola pamor besi, baja dan kelengkapan berupa warangka, ukiran maupun pendoknya. Dari masing-masing komponen tersebut seandainya ada salah satu yang cacat maka keris itu sudah kurang sempurna. Sedangkan yang dimaksud dengan sepuh adalah keris itu betul-betul tua usianya. Hal ini perlu diperhatikan, sebab proses kimiawi bisa merubah keris buatan manusia kini seolah-olah menjadi keris tua. Kemudian yang dimaksud tangguh adalah keris itu harus jelas asal-usulnya. -

Kode Provinsi : 33 Nama Provinsi : JAWA TENGAH
STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN Kode Provinsi : 33 Nama Provinsi : JAWA TENGAH KODEKAB KABUPATEN/KOTA KODEKEC KECAMATAN KODEDESA NAMA DESA IDM STATUS 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001101 PANULISAN BARAT 0,6824 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001102 PANULISAN 0,7640 Maju 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001103 PANULISAN TIMUR 0,7232 Maju 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001104 MATENGGENG 0,7023 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001105 CIWALEN 0,6985 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001106 DAYEUHLUHUR 0,7441 Maju 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001107 HANUM 0,7050 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001108 DATAR 0,6212 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001109 BINGKENG 0,6380 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001110 BOLANG 0,6238 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001111 KUTAAGUNG 0,5663 Tertinggal 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001112 CIJERUK 0,6098 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001113 CILUMPING 0,5781 Tertinggal 33001 CILACAP 1201260 DAYEUHLUHUR 33001114 SUMPINGHAYU 0,5624 Tertinggal 33001 CILACAP 1201260 WANAREJA 33001201 PURWASARI 0,7159 Maju 33001 CILACAP 1201260 WANAREJA 33001202 CILONGKRANG 0,7246 Maju 33001 CILACAP 1201260 WANAREJA 33001203 TARISI 0,5908 Tertinggal 33001 CILACAP 1201260 WANAREJA 33001204 BANTAR 0,6181 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 WANAREJA 33001205 SIDAMULYA 0,6465 Berkembang 33001 CILACAP 1201260 WANAREJA 33001206 ADIMULYA 0,7787 Maju 33001 CILACAP 1201260 WANAREJA 33001207 -

The Gods & the Forge
ificah International Foundation of Indonesian Culture and Asian Heritage The Gods & the Forge Balinese Ceremonial Blades The Gods & the Forge in a Cultural Context This publication is the companion volume for the exhibition of the same name at the IFICAH Museum of Asian Culture in Hollenstedt-Wohlesbostel, Germany December 2015 to October 2016. Title number IFICAH V01E © IFICAH, International Foundation of Indonesian Culture and Asian Heritage Text: Dr. Achim Weihrauch, Efringen-Kirchen, Germany Dr. Udo Kloubert, Erkrath, Germany Adni Aljunied, Singapore Photography: Günther Heckmann, Hollenstedt, Germany Printing: Digital Repro Druck GmbH, Ostfildern, Germany Layout: S&K Kommunikation, Osnabrück, Germany Editing: Kerstin Thierschmidt, Düsseldorf, Germany Image editing: Concept 33, Ostfildern, Germany Exhibition design: IFICAH Display cases: Glaserei Ahlgrim, Zeven, Germany "Tradition is not holding onto the ashes, Metallbau Stamer, Grauen, Germany Conservation care: but the passing on of the flame." Daniela Heckmann, Hollenstedt, Germany Thomas Moore (1477–1535) Translation: Comlogos, Fellbach, Germany 04 05 Foreword Summer 2015. Ketut, a native of Bali, picks me Years earlier, the fishermen had sold the land up on an ancient motorcycle. With our feet bordering the beach to Western estate agents, clad in nothing more resilient than sandals, we which meant however that they can now no ride along streets barely worthy of the name longer access the sea with their boats ... to the hinterland. We meet people from dif- ferent generations who live in impoverished It is precisely these experiences that underline conditions by western standards and who wel- the urgency of the work carried out by IFICAH – come the "giants from the West" with typi- International Foundation of Indonesian Culture cal Balinese warmth. -

Daftar Fasilitas Asuransi Kesehatan Tingkat Pertama
DAFTAR FASILITAS ASURANSI KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PROVINSI KANTOR REGIONAL KANTOR CABANG NAMA DATI2 KODE PPK NAMA PPK ALAMAT PPK TELF. PPK N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 00080010 KLINIK POLRES ACEH BARAT SWADAYA N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 00080011 KLINIK POLRES ACEH BESAR IMBRAHIM SAIDI NO. 1 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 00080012 KLINIK SPN SEULAWAH BANDA ACEH MEDAN KM 61 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 00080009 SIKES LANUD ISKANDARMUDA JL. PANTE PERAK BANDA ACEH N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U002 DR. IMRAN A. GANI DESA LAMTEUNGOH 85260153917 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U007 DR.MUHAMMAD ALI JL.SULTAN ISKANDAR MUDA NO.1 81269124571 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U008 KLINIK AISHA - 10 JL.T.ISKANDAR SIMPANG COT IRI 08126910292 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U004 KLINIK M.C MEULIGO BUNDA JL.B.ACEH-MEDAN 10LR.REFORMASI 06517413589 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U005 KLINIK MEURASI LAMBARO JL.BANDA ACEH-MEDAN KM 4,5 0811684550 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U001 DR. FIA DEWI AULIANI, MARS Jl.BANDA ACEH-MEDAN KM 25 0651-92195 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. ACEH BESAR 0008U010 KLINIK AISHA - 07 JL. BANDA ACEH-MEULABOH 08126910292 N. ACEH D. REGIONAL I - MEDAN BANDA ACEH KAB. -

No Periode Nama Nama2 Alm1 Alm2 Kota Saham Persentase La Status 1 6/30/2020 a Bamban Yuuwono Wonosari 001/003 Wonosari Gondangre
NOPERIODE NAMA NAMA2 ALM1 ALM2 KOTA SAHAM PERSENTASELA STATUS 16/30/2020A BAMBAN YUUWONO WONOSARI 001/003 WONOSARI GONDANGREJO KARANGANYAR 9,000 0.0005143 L PERORANGAN INDONESIA 26/30/2020A GUAN JL.PUKAT HARIMAU NO.57 MEDAN KEL.BANTAN TIMUR KEC.MEDAN TEMBUNG MEDAN 600 0.0000343 L PERORANGAN INDONESIA 36/30/2020A HERRY BUDI SUSANTO IR MM JL. PEMANDANGAN I / 6 RT 013 RW 001 PADE MANGAN BRT JAKARTA UTARA 10,000 0.0005714 L PERORANGAN INDONESIA 46/30/2020A N A S JL. H MERIN KAVLING BRI BLOK D NO.59 A, RT/RW: 3/4, KEL: MERUYA SELATA N (UDIK), JAKARTA BARAT 50,000 0.0028571 L PERORANGAN INDONESIA 56/30/2020A SIN WONOREJO PERMAI TIMUR IX/9 RT 003 RW 005 KEL. WONOREJO KEC. RUNGKUT / SURABAYA 60,000 0.0034285 L PERORANGAN INDONESIA 66/30/2020A TIE JL SETIA BUDI RT/RW:008/004 DESA/KEL.L P AKAM PEKAN KEC.LUBUK PAKAM DELI SERDANG 33,000 0.0018857 L PERORANGAN INDONESIA 76/30/2020A TIE JL.SETIABUDI NO.21 RT008 RW004 KEL. LUBU K PAKAM PEKAN KEC. LUBUK PAKAM DELI SERDANG 80,000 0.0045714 L PERORANGAN INDONESIA 86/30/2020AA NOVA SWANDANA JL. H. KATIM NO.63 RT: 04 RW:01 KEL:MERU YUNG KEC:LIMO DEPOK 5,100 0.0002914 L PERORANGAN INDONESIA 96/30/2020AANG KUNAEFI USMAN KURIPAN RT/RW 001/001 KEL .KURIPAN KEC. GARUNG WONOSOBO 7,000 0.0004000 L PERORANGAN INDONESIA 106/30/2020ABDUL GANI DUSUN SUNGAI RENGAS 006/006 TALANG DUKU TAMAN RAJO MUARO JAMBI 5,500 0.0003143 L PERORANGAN INDONESIA 116/30/2020ABDUL GAPAR SUNGAI RENGAS KELURAHAN TALANG DUKU KECA MATAN TAMAN RAJO MUARO JAMBI 100 0.0000057 L PERORANGAN INDONESIA 126/30/2020ABDUL HAFIZ LAMUSUNG KELURAHAN LAMUSUNG KECAMATAN SE TELUK SUMBAWA BARAT 4,800 0.0002743 L PERORANGAN INDONESIA 136/30/2020ABDUL HALIM JL. -

Character of the Inhabitants of Java
( 244 ) CHAPTER VI. Character Q[ the Inhabitants (if Ja'Va.-Difference between the 8undas and the Ja'Vans.-The Lower Orders.-The Chiifs.-Nature cif the Native Go'Vern. ment.-Different Officers cif the State.-Judicial Establishments and Institu tions.-Laws, and how administered.-Police Institutions and Regulations. -Military Establishments.-Re'Venue. H AV IN G, in the foregoing pages, attempted to introduce the inhabitants of Java to the reader, by an account of their person, their manners, and employment in the principal departments of agriculture, manufactures, and commerce, I shall now endeavour to make him, in some degree, acquainted with their intellectual and moral character, their institutions, government, and such other particulars as may contribute to enable him to form some estimate of their relative rank in the scale of civilized society. Intellectual From what has been stated of their progress in'the manufacturing and character. agricultural arts, their general advancement in knowledge may be easily estimated. There are no establishments for teaching the sciences, and there is little spirit of scientific research among them~ The common people have little leisure or inclination for improving their minds or acquiring informa tion, but they are far from being deficient in natural sagac.ity or docility. Their organs are acute and delicate, their observation IS ready, and their judgment of character is generally correct. Like most eastern nations, they are enthusiastic admirers of poetry, and possess a delicate ear for music. Though deficient in energy, and excited to action with difficulty, the effect probably of an enervating ciimate and a still more enervating government, they are capable of great occasional exertion, and sometimes display a remarkable perseverance in surmounting obstacles or enduring labours. -

Data Peserta Yang Aktif Di Sistem Gurudaring Milenial
NO NAMA UNIT KERJA KAB KOTA USER 1 A,LAMBOGO,S.PD.M.PD SDN 8 Tampaan ENREKANG gurudaring4814 2 A. Abriyawati. Makassar gurudaring9908 3 A. Dimas SugraCahyono SDN Podosugih 1 Kota PekalongaPekalongan gurudaring8394 4 A. Hamdana, S. Pd. MTsN 1 Kota Makassar Makassar gurudaring5132 5 A. Maisyarah,M.Pd SMPN 5 Tanah Grogot PASER gurudaring3814 6 A. NOVER SETYAWAN Y SMK PGRI 2 KOTA JAMBI KOTA JAMBI gurudaring784 7 A. Nur hasiahSultan, S.Pd Makassar gurudaring14592 8 A. NURAENI,S.Pd SDN KUTAGANDOK I KARAWANG gurudaring1119 9 A. RACHMAT TAUFIQ, S.Pd. UPT SDN 57 PINRANG PINRANG gurudaring4977 10 A. Suryaningsih, S.Pd.Ina. SMP Pius Bakti Utama Gombong Kebumen gurudaring10388 11 A. Syifaul UmamM.Pd SMK PGRI 2 KOTA KEDIRI Kota kediri gurudaring2878 12 A.ABD. RAHMAN MARUAPE. SMA N 2 MALUKU TENGAH Maluku Tengah gurudaring4099 13 A.Ambo, S.Pd Kepulauan Selayar gurudaring13273 14 A.ANITA SARI,S.Pd TK ULFIRA MAROS gurudaring5061 15 A.DEWI SARTIKA S. SEA. Dewi TK ISLAM TERPADU ASSHIDDIQ BONE gurudaring12543 16 A.H. Ayanda Sadra, MA SMPN 2 X Koto Diatas Kabupaten Solok gurudaring5467 17 A.Iffahuzaefa. gurudaring9640 18 A.ZAMRONI Banyuwangi gurudaring6723 19 AA KOSWARA, S. Pd.. SMPN 2 GANEAS Sumedang gurudaring1562 20 AAABDUL BASIT Kota Tasikmalaya gurudaring9150 21 AanAgustina S.Pd SD Kristen Terang Bangsa Kota Semarang gurudaring1996 22 A'ANKURNIAWATI Jember gurudaring13214 23 AanKusnaeni, S.Pd SMPN 1 Cimalaka Sumedang gurudaring1578 24 Aan's Charisma Oktaviana,S.Pd. SMP KRISTEN TERANG BANGSA KOTA SEMARANG gurudaring2089 25 AAPABDULAH, S.Pd SDN 1 Cikarang Kec. Muncang Kab. Lebak gurudaring319 26 AATSOLIHAT, S.Pd, M.M SDN 2 Bojong Leles Kec. -

Book Reviews -Timothy Barnard, J.M. Gullick, a History of Selangor (1766-1939). Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1989, Vi + 220 Pp
Book Reviews -Timothy Barnard, J.M. Gullick, A history of Selangor (1766-1939). Kuala Lumpur: Malaysian branch of the Royal Asiatic Society, 1989, vi + 220 pp. [MBRAS Monograph 28.] -Okke Braadbaart, Michael L. Ross, Timber booms and institutional breakdown in Southeast Asia. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, xvi + 237 pp. -H.J.M. Claessen, Patrick Vinton Kirch ,Hawaiki, ancestral Polynesia; An essay in historical anthropology. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, xvii + 375 pp., Roger C. Green (eds) -Harold Crouch, R.E. Elson, Suharto; A political biography. Cambridge: Cambridge University Press, 2001, xix + 389 pp. -Kees van Dijk, H.W. Arndt ,Southeast Asia's economic crisis; Origins, lessons, and the way forward. Singapore: Institute of Southeast Asian studies, 1999, ix + 182 pp., Hal Hill (eds) -Kees van Dijk, Sebastiaan Pompe, De Indonesische algemene verkiezingen 1999. Leiden: KITLV Uitgeverij, 1999, 290 pp. -David van Duuren, Albert G. van Zonneveld, Traditional weapons of the Indonesian archipelago. Leiden: Zwartenkot art books, 2001, 160 pp. -Peter van Eeuwijk, Christian Ph. Josef Lehner, Die Heiler von Samoa. O Le Fofo; Monographie über die Heiler und die Naturheilmethoden in West-Samoa. Frankfurt am Main: Lang, 1999, 234 pp. [Mensch und Gesellschaft 4.] -Hans Hägerdal, Frans Hüsken ,Reading Asia; New research of Asian studies. Richmond: Curzon, 2001, xvi + 338 pp., Dick van der Meij (eds) -Terence E. Hays, Jelle Miedema ,Perspectives on the Bird's head of Irian Jaya, Indonesia; Proceedings of the conference, Leiden, 13-17 October 1997. Amsterdam: Rodopi, 1998, xiii + 982 pp. (editors with the assistance of Connie Baak), Cecilia Odé, Rien A.C. Dam (eds) -Menno Hekker, Peter Metcalf, They lie, we lie; Getting on with anthropology. -

Inventory of the Oriental Manuscripts of the Library of the University of Leiden
INVENTORIES OF COLLECTIONS OF ORIENTAL MANUSCRIPTS INVENTORY OF THE ORIENTAL MANUSCRIPTS OF THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF LEIDEN VOLUME 11 MANUSCRIPTS OR. 10.001 – OR. 11.000 REGISTERED IN LEIDEN UNIVERSITY LIBRARY IN THE PERIOD BETWEEN 1949 AND DECEMBER 1964 -UPDATE 2 SEPTEMBER 2015- COMPILED BY JAN JUST WITKAM PROFESSOR EMERITUS OF PALEOGRAPHY AND CODICOLOGY OF THE ISLAMIC WORLD IN LEIDEN UNIVERSITY INTERPRES LEGATI WARNERIANI EMERITUS TER LUGT PRESS LEIDEN 2015 © Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt Press, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007, 2015. The form and contents of the present inventory are protected by Dutch and international copyright law and database legislation. All use other than within the framework of the law is forbidden and liable to prosecution. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of the author and the publisher. First electronic publication: 19 November 2006. Update: 31 July 2007. Latest update: 2 September 2015 Copyright by Jan Just Witkam & Ter Lugt P ress, Leiden, The Netherlands, 2006, 2007, 2015 PREFACE TO THE 2015 EDITION For reasons that are not entirely clear to me anymore, volume 11 of my Inventories of the Oriental manuscripts in the library of Leiden University was never published before. Yet is has been largely ready ever since I updated the text in July 2007. Working on other volumes, I more or less by accident found out that I had never uploaded it to my website. -

VU Research Portal
VU Research Portal Caught between three fires; The Javanese pangulu under the Dutch colonial administration, 1882-1942 [Review of: M. Hisyam (2001) Caught between three fires; The Javanese pangulu under the Dutch colonial administration, 1882-1942] Sutherland, H.A. published in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 2003 document version Publisher's PDF, also known as Version of record Link to publication in VU Research Portal citation for published version (APA) Sutherland, H. A. (2003). Caught between three fires; The Javanese pangulu under the Dutch colonial administration, 1882-1942 [Review of: M. Hisyam (2001) Caught between three fires; The Javanese pangulu under the Dutch colonial administration, 1882-1942]. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 159(1), 226- 228. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. E-mail address: [email protected] Download date: 29. Sep. 2021 Book Reviews -Timothy Barnard, J.M. -

1. Online-Auktion Asiatische Kunst Endet Am 10.12.2016 Unsere Experten Termine Our Specialists Dates
& KUNSTHANDEL KLEFISCH 1. Online-Auktion Asiatische Kunst endet am 10.12.2016 www.van-ham.com Unsere Experten Termine Our Specialists Dates Christoph Bouillon Vorbesichtigung Geschäftszeiten nach der Auktion Katalogredaktion Preview Business hours after the sale Tel. +49 (221) 925862-32 Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr [email protected] 3. bis 7. Dezember 2016 Samstag 10 bis 13 Uhr Samstag 10 bis 16 Uhr Walter Bruno Brix Sonntag 11 bis 16 Uhr Buddhistische und chinesische Kunst Montag 10 bis 18 Uhr Adresse Textilien, Indien, Khmer Dienstag 10 bis 18 Uhr address Tel. +49 (221) 925862-28 Mittwoch 10 bis 18 Uhr Van Ham Kunstauktionen [email protected] Hitzelerstraße 2 Auktion 50968 Köln Iris Hekeler Sale Tel.: +49 (221) 925862-0 Japanische Kunst und Holzschnitte Fax: +49 (221) 925862-4 Tel. +49 (221) 925862-21 Samstag, 10. Dezember 2016 [email protected] [email protected] bis 22 Uhr www.van-ham.com Trudel Klefisch Netsuke, Inro Tel. +49 (221) 925862-88 Indonesien [email protected] Waffen Nr. 3000 – 3047 Indonesien/Thailand Hua Yan Textil Nr. 3048 – 3064 Chinesische Kunst und Porzellan Japan Tel. +49 (221) 925862-80 Holzschnitte Nr. 3065 – 3099 [email protected] Tsuba Nr. 3100 – 3110 China Natalie Alfers Kunsthandwerk Nr. 3111 – 3117 Volontariat Fachbücher Nr. 3118 – 3123 Tel. +49 (221) 925862-85 [email protected] 預展時間: 2016年12月3日-7日 12月3日 10 –16點 12月4日 11 –16點 12月5日-7日 10 –18點 拍賣會後營業時間: 德國科隆 VAN HAM(範∙漢姆) 週一至週五 10 –17點 藝術拍賣公司 週六 10 –13點 Hitzeler Str.