Merayakan Indonesia Raya
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PROSES PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Sebelas Maret Institutional Repository i LAPORAN KHUSUS PROSES PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA Oleh: Ratna Dewi Ayuningtyas NIM. R0006066 PROGRAM D-III HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2009 ii PENGESAHAN Laporan khusus dengan judul: PROSES PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA Diteliti oleh: Ratna Dewi Ayuningtyas NIM. R0006066 Telah diuji dan disahkan pada tanggal: Pembimbing I Pembimbing II dr. Harninto,MS. Sp.Ok Drs. Hisyam, SW. MS NIP. 130 543 962 NIP. 130 354 829 ii iii PENGESAHAN Laporan umum dengan judul : PROSES PENGOLAHAN LIMBAH CAIR DI RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA Disusun oleh: Ratna Dewi Ayuningtyas NIM. R0006066 Laporan ini telah diajukan dan disahkan pada tanggal: Pembimbing Lapangan Kepala Instalasi Sanitasi Sudirman, SKM Endah Kusumaningsih, ST NIP. 140 192 847 NIP. 140 336 991 iii iv ABSTRAK Ratna Dewi Ayuningtyas, 2006. PROSES PENGOLAHAN LIMBAH CAIR di RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA. PROGRAM D-III HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNS. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses pengolahan limbah cair pada IPAL di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Kerangka pemikiran dari penelitian adalah menggambarkan bahwa rumah sakit dalam melakukan kegiatannya menghasilkan limbah cair yang bersifat fisik,kimia dan biologis. Pelaksanaan pengolahan limbah cair meliputi bak penangkap lemak, bak penampung air limbah (pengumpul 1), bak penampung air limbah (pengumpul 2), bak penyaring, bak floatasi, bak sedimentasi, bak equalisasi, bak biodetok FBK 10, bak biodetok FBK 20, bak desinfeksi (kaporit), bak kontak desinfeksi, bak uji hayati, bak pengering lumpur. -

Figurative Language in Amir Hamzah's Poems
Novia Khairunnisa, I Wy Dirgeyasa, Citra Anggia Putri Linguistica Vol. 09, No. 01, March 2020, (258-266) FIGURATIVE LANGUAGE IN AMIR HAMZAH’S POEMS 1 2 3 NOVIA KHAIRUNISA . I WY DIRGEYASA , CITRA ANGGIA PUTRI 123 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN Abstract This study dealt with figurative language in Amir Hamzah’s selected poems. The objective of this study were to investigate the types of figurative language found in Amir Hamzah’s selected poems and to find out the literal meaning of figurative language found. This study was conducted by using qualitative method to solve the problems. The data of this study were phrases and sentences contained figurative language in the poems. The sources of data were six poems poems which had multiple series taken from Amir Hamzah’s Poetry Anthology of Buah Rindu. The data were selected by using random sampling technique. For collecting the data, this study used documentary technique, and the instruments of data were documentary sheets. The data were analyzed by using descriptive qualitative method. The findings of this study are there twenty two figurative languages found as follows, three figurative language of metaphor (13.63%), seven figurative language of hyperbole (31.81%), five figurative language of personification (22.72%) and seven figurative language of simile (31.83%). The literal meaning of figurative language found in Amir Hamzah’s poems were basically was about the love story of Amir himself and also talking about his longing to his mother. Keywords : Figurative Language, Figure of Speech, Poem INTRODUCTION Poem is a literary work in patterned language. It can also be said as the art of rhythmical composition. -

Antara Senapan Dan Pena (Perjuangan TRIP Jawa Barat Pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia)
Antara Senapan dan Pena (Perjuangan TRIP Jawa Barat Pada Masa Perang Kemerdekaan Indonesia) A. Pendahuluan Proklamasi Kemerdekaaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu perwujudan dari kesadaran bangsa Indonesia untuk membentuk sebuah negara yang merdeka, bebas, dan berdaulat, ternyata mendapat kecaman dari pihak Belanda. Tepatnya pada bulan September 1945, pasukan Sekutu yang membawa tugas AFNEI (Allied Forces Nethterlands East Indies), melakukan pendaratan di Jakarta, Semarang dan Surabaya, kemudian bergerak ke pemusatan- pemusatan tentara Jepang. Pendaratan pasukan Sekutu ini ternyata mengikutsertakan rombongan NICA yang ingin membentuk kembali kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Pada tahun 1945 terjadilah fenomena sejarah yang unik ketika seluruh rakyat termasuk para pelajar Indonesia semuanya dicekam oleh emosi yang meluap-luap untuk mempertahankan kemerdekaan. Sehingga usaha penjajahan kembali terhadap suatu bangsa yang sudah merdeka akan mendapat perlawanan dari rakyat yang rela mati untuk bangsa dan tanah airnya. Kemerdekaan yang berarti “perang” memaksa rakyat Jawa Barat bersiap-siap dan kemudian mengorganisir badan- badan perjuangan yang anggotanya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat setempat, seperti di Jakarta, Bandung, 112 Purwakarta, Serang, Bogor, Tasikmalaya, Cirebon dan Sumedang, telah berdiri laskar-laskar perjuangan sebagai potensi bersenjata yang lahir dari masyarakat.1 Demikian pula keadaan negara yang belum stabil akibat goncangan dari pihak Belanda yang mencoba kembali menduduki Indonesia, -

(PENILAIAN TENGAH SEMESTER) Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (Ppkn) KELAS 8 SEMSTER GENAP
SOAL MED SEMESTER (PENILAIAN TENGAH SEMESTER) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) KELAS 8 SEMSTER GENAP SOAL PILIHAN GANDA 1. Penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) pada 20 Maret 1602. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik…. A. Devide et impera B. Balas budi C. Etische Politic D. Dumping 2. Perhatikanlah nama-nama berikut ini! 1. Baron Van Houvel. 2. Van Den Bosch. 3. Mr. Van Deventer. 4. Edward Douwes Dekker. Siapakah orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia yang mengetahui penderitaan rakyat Indonesia karena diterapkannya tanam…. A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 1, 3, dan 4 D. 2, 3, dan 4 3. Gerakan Budi Utomo yaitu sebuah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan berbentuk modern atau lebih jelasnya sebuah organisasi dengan sistem pengurusan yang tetap, ada anggota, tujuan dan program kerja. Organisasi Budi Utomo sendiri dibentuk oleh pelajar STOVIA yang bernama…. A. Wahidin Sudirohusodo B. Cipto Mangunkusumo C. Suwardi Suryaningrat D. Sutomo 4. Perhatikanlah nama-nama tokoh berikut ini! 1. Wahidin Sudirohusodo. 2. Sutomo. 3. Suwardi Suryaningrat. 4. Cipto Mangunkusumo. Siapakah tokoh-tokoh perintis Kebangkitan Nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia…. A. 1, 2, dan 3 B. 2, 3, dan 4 C. 1, 3, dan 4 D. 1, 2, dan 4 5. Perhatikanlah pernyataan dibawah ini! 1. Mempelajari berbagai tarian daerah sebagai upaya untuk melestarikannya. 2. Menggunakan produksi luar negeri karena kualitasnya terjamin. 3. Menjaga kelestarian alam. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Dari pernyataan diatas, perilaku yang menggambarkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia ditunjukkan pada nomor…. -
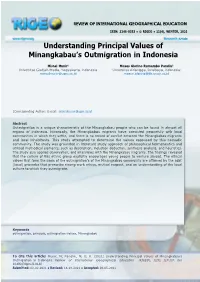
Understanding Principal Values of Minangkabau's Outmigration In
REVIEW OF INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL EDUCATION ISSN: 2146-0353 ● © RIGEO ● 11(4), WINTER, 2021 www.rigeo.org Research Article Understanding Principal Values of Minangkabau’s Outmigration in Indonesia Misnal Munir1 Moses Glorino Rumambo Pandin2 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia [email protected] [email protected] 1Corresponding Author: E-mail: [email protected] Abstract Outmigration is a unique characteristic of the Minangkabau people who can be found in almost all regions of Indonesia. Historically, the Minangkabau migrants have coexisted peacefully with local communities in which they settle, and there is no record of conflict between the Minangkabau migrants and local inhabitants. This study attempted to determine the values espoused by this nomadic community. The study was grounded in literature study approach of philosophical hermeneutics and utilized methodical elements, such as description, induction deduction, synthesis analysis, and heuristics. The study also applied observation, and interviews with the Minangkabau migrants. The findings revealed that the culture of this ethnic group explicitly encourages young people to venture abroad. The ethical values that form the basis of the outmigration’s of the Minangkabau community are affirmed by the adat (local) proverbs that prescribe strong work ethics, mutual respect, and an understanding of the local culture to which they outmigrate. Keywords outmigration, principle, outmigration-values, Minangkabau To cite this article: Munir, M; Pandin, M, G, R. (2021) Understanding Principal Values of Minangkabau’s Outmigration In Indonesia. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(4), 127-137. doi: 10.48047/rigeo.11.04.10 Submitted: 02-02-2021 ● Revised: 16-04-2021 ● Accepted: 26-05-2021 © RIGEO ● Review of International Geographical Education 11(4), WINTER, 2021 Introduction The cultural traditions of the Minangkabau people are rich in values derived from indigenous wisdom. -

Oleh: FLORENTINUS RECKYADO
PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN RERUM NOVARUM DALAM PERPEKTIF PANCASILA SKRIPSI SARJANA STRATA SATU (S-1) Oleh: FLORENTINUS RECKYADO 142805 SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN WIDYA YUWANA MADIUN 2021 PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN RERUM NOVARUM DALAM PERPEKTIF PANCASILA SKRIPSI Diajukan kepada Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana Madiun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Oleh: FLORENTINUS RECKYADO 142805 SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN WIDYA YUWANA MADIUN 2021 PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Florentinus ReckYado NPM :142805 Programstudi : Ilmu Pendidikan Teologi Jenjang Studi : Strata Satu Judul skripsi : Prinsip-Prirsip Kemanusiaan Rerum Novarum ' Dalam Perpektif Pancasila Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini adalah mumi merupakan gagasan, mmusan dan penelitian saya sendiri tanpa ada bantuan pihak lain kecuali bimbingan dan arahan dosen pembimbing. 2. Skripsi ini belum pemah diajukan untuk mendapat gelat akademik apapun di STKIP Widya Yuwana Madiun maupun di perguruan tinggi lain- 3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengamng dan mencantumkan dalam daftar pust*a. Demikianlah pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pemyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencbutan gelar yang telah diberikan melalui karya tulis ini se(a sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini. Madi !.fl... hs :!.t.1:'. t 74Y\ lvtETERAl TEMPEL DAJX198738966 Florentinus Reckyado 142805 HALAMAN PERSETUJUAN Skripsi dengan judul "Prinsip-Prinsip Kemanusiaan Rerum Novarum Dalam Perpektif Pancasila", yang ditulis oleh Florentinus Reckyado telah diterima dan disetujui untuk diqji pada tanggal tA 3u\i eo3\ Oleh: Pembimbing Dr. -

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Hk.01.07/Menkes/44/2019 Tentang Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1440 H/2019 M
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: HK.01.07/MENKES/44/2019 TENTANG TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1440 H/2019 M DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang (kloter), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1440 H/2019 M. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas - 2 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia -

Clinical Profile and Incidence of Infection in Systemic Lupus Erythematosus Patients at Medical Inpatient Installation, Department of Internal Medicine, Dr
49 Majalah Biomorfologi Volume 31 Number 2, July 2021 p-ISSN: 0215-8833, e-ISSN: 2716-0920, DOI: 10.20473/mbiom.v31i2.2021.49-56 Clinical profile and incidence of infection in Systemic Lupus Erythematosus patients at Medical Inpatient Installation, Department of Internal Medicine, Dr. Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia in 2016 Desy Trilistyoati1, Betty Agustina2*, Awalia3 1Faculty of Medicine, Universitas Airlangga, Dr. Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia. 2Department of Clinical Pathology, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga; Dr. Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia. 3Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Universitas Airlangga; Dr. Soetomo General Academic Hospital; Siloam Hospital, Surabaya, Indonesia. Article Info ABSTRACT Article history: Background: Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is an Received Sep 20, 2020 autoimmune disease with unknown aetiology. SLE attacks multiple Revised Mar 3, 2021 organs with diverse clinical manifestations. Most patients get immunosuppressant therapy that suppresses immune system, Accepted Mar 24, 2021 Published Jul 1, 2021 causing the body to be susceptible to infection. Objective: to describe clinical manifestations, laboratory abnormalities, and incidence of infections in SLE patients hospitalized at Dr. Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia in 2016. Keywords: Disease Materials and Methods: Cross-sectional descriptive observational Medicine study used medical records of 273 SLE patients hospitalized at Dr. Systemic Lupus Soetomo General Academic Hospital, Surabaya, Indonesia in 2016. Erythematosus Results: Clinical manifestations found in this study were malar rash Lupus nephritis 7.33%, discoid rash 2.93%, oral ulcer 8.42%, allopecia 16.48%, Infection arthritis 26.74%, serositis 13.19%, kidney 35.9%, neurology Autoimmune disease 24.91%, anemia 73.71%, leucopenia 32.67%, lymphopenia 76.89%, Immunosuppressant and thrombocytopenia 33.86%. -

Words: Education; Opuses; Behind the Story of Merah-Putih; Si Tou Timou Tumou Tou
STAINU Purworejo: Jurnal As Sibyan Vol 3 No 2, Desember 2020 Jurnal Kajian Kritis Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Dasar Homepage: https://ejournal.stainupwr.ac.id/ Email: [email protected] E-ISSN: : 2599-2732 PENGENALAN PAHLAWAN SAM RATULANGI PADA SISWA MI/SD Hilda Zuhri Khairunnisa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Email: [email protected] Orcid Id: Anis Fuadah Z Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Email: [email protected] Orcid Id: 0000-0002-5935-030X Abstract (in English; 12 pt Cambria) This article moots about a struggle of a famous and an influenced figure ever in that time, coming from Minahasa, North Sulawesi. He fought for Indonesia in his own way and got his thoughts gone viral even until now. His name is Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi or usually called Sam Ratulangi. He also had the biggest role why Indonesia nowadays is called “Indonesia”. This article was made to 1) acquaint a biography of a patriot that is Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi to learners, especially in elementary school. 2) acquaint the values in Sam Ratulangi. 3) know how Sam Ratulangi fought for his beloved country and what was his role in defending Indonesia. 4) acquaint his thoughts that is going viral even in nowadays. All of the data are gotten from books, literature, and journals that are related to the topic. Keywords: education; opuses; behind the story of Merah-Putih; Si Tou Timou Tumou Tou. Abstrak Artikel ini membahas tentang perjuangan seorang pahlawan terkenal dan paling berpengaruh pada masanya dari Minahasa, Sulawesi Utara. -
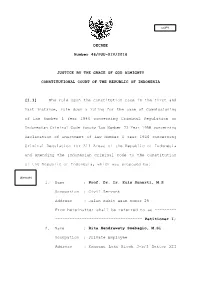
DECREE Number 46/PUU-XIV/2016 JUSTICE by THE
COPY DECREE Number 46/PUU-XIV/2016 JUSTICE BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA [1.1] Who rule upon the constitution case in the first and last instance, rule down a ruling for the case of Commissioning of Law Number 1 Year 1946 concerning Criminal Regulation or Indonesian Criminal Code juncto Law Number 73 Year 1958 concerning Declaration of Enactment of Law Number 1 Year 1946 concerning Criminal Regulation for All Areas of the Republic of Indonesia and Amending the Indonesian Criminal Code to the Constitution of the Republic of Indonesia, which was proposed by: [Barcode] 1. Name : Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.S Occupation : Civil Servant Address : Jalan Bukit Asam nomor 29 From hereinafter shall be referred to as --------- ------------------------------------ Petitioner I; 2. Name : Rita Hendrawaty Soebagio, M.Si Occupation : Private Employee Address : Kencana Loka Block J-5/3 Sektor XII RT.004/RW.014, Rawabuntu Village, Serpong District, South Tangerang City; From hereinafter shall be referred to as --------- ----------------------------------- Petitioner II; 3. Name : Dr. Dinar Dewi Kania Occupation : Private Employee/Lecturer Address : Jalan Tanjung 15 Block E Number 5 RT.007/RW.002, West Tanjung Village, Jagakarsa District, South Jakarta City; From hereinafter shall be referred to as --------- ---------------------------------- Petitioner III; 4. Name : Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto Occupation : Housewife/Lecturer at University of Indonesia Address : Komplek Timah Block CC Number 30 RT.005/RW.012, Kelapa Dua Village, Cimanggis District, Depok City; From hereinafter shall be referred to as --------- ----------------------------------- Petitioner IV; 5. Name : Nurul Hidayati Kusumahastuti Ubaya, S.S., MBA Occupation : Housewife Address : Jalan Parkit RT.004/RW.001, Sawah Besar Village, Ciputat District, South Tangerang City; From hereinafter shall be referred to as --------- ------------------------------------ Petitioner V; 6. -

Jaringan Rumah Sakit Rekanan PT Chubb Life Insurance Indonesia
Jaringan Rumah Sakit Rekanan PT Chubb Life Insurance Indonesia Kode ADM/ Nama Rumah Sakit/ Penanggung Jawab/ Nomor Telepon/ Nomor Fax/ No Daerah/State Kota/City Alamat/Address Divisi/Division Email ADM CODE Medical Provider Name Contact Person Hospital Phone Number Hospital Fax Number 1 BALI BADUNG 3429 KF 0384 BERAWA JL.RAYA SEMAT,DS.TIBUBENENG,BADUNG, TIBUBENENG, KUTA UTARA, BADUNG- - 0361761834/082114696984 - [email protected] [email protected];[email protected]; 2 BALI BADUNG 4867 RS. BALI JIMBARAN JL. KAMPUS UNUD LING. PERARUDAN, JIMBARAN, KUTA SELATAN WIDYA WIDHIASTUTI MARKETING (0361) 4725123 / 082138977403 (0361) 4725122 [email protected]; [email protected] [email protected];[email protected];[email protected];kadekl 3 BALI BADUNG 5783 RS. KHUSUS BEDAH BIMC NUSA DUA BALIBLOK D KAWASAN BTDC NUSA DUA IBU SISKA MARKETING 0361-3000911 0361-3001150 [email protected] 4 BALI BADUNG 6761 KLINIK TAKENOKO JL. SUNSET ROAD NO.77A, KUTA DR. I KOMANG WIRAJAYA PIC 0361-4727288 0361-4727289 [email protected] 5 BALI BADUNG 6786 KLINIK PRATAMA SADA JIWA BR PASEKAN, SEMBUNG, MENGWI DR I GUSTI AYU PURI AYUNI MANAGER OPERASIONAL 0361-829225 / 829888 - [email protected] 6 BALI BADUNG 7013 KLINIK DWI KARYA USADHA JL. RAYA KEROBOKAN LINGKUNGAN BANJAR CAMPUAN KEL. KEROBOKAN KEC. KUTAEKA LEONIUTARA MULYA DEWI MARKETING 0361-9342142 - [email protected]; [email protected] 7 BALI BANGLI 4898 RS. BANGLI MEDIKA CANTI JL. TIRTA GIRI KUTRI LCSUBAK AYA BEBALANG, BANGLI, BALI SANG KOMPYANG - 0366-91555/93444 - [email protected]; [email protected]; [email protected] 8 BALI BULELENG 0870 RSU. KERTHA USADA JL. CENDRAWASIH, NO.5-7, SINGARAJA IBU ECHA MARKETING 0362-26277/8 0362-22741 [email protected]; [email protected] 9 BALI BULELENG 1451 RSU. -

Daftar Nama Pahlawan Nasional Republik Indonesia
DAFTAR NAMA PAHLAWAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Asal Daerah / NO Nama SK Presiden Daerah Ket Pengusul Abdul Muis 218 Tahun 1959 1. Sumatera Barat 1883 – 1959 30 – 8 – 1959 Ki Hadjar Dewantoro 305 Tahun 1959 2. D.I. Yogyakarta 1889 – 1959 28 – 11 – 1959 Surjopranoto 310 Tahun 1959 3. D.I. Yogyakarta 1871 – 1959 30 – 11 – 1959 Mohammad Hoesni Thamrin 175 Tahun 1960 4. DKI Jakarta 1894 – 1941 28 – 7 – 1960 K.H. Samanhudi 590 Tahun 1961 5. Jawa Tengah 1878 – 1956 9 – 11 – 1961 H.O.S. Tjokroaminoto 590 Tahun 1961 6. Jawa Timur 1883 – 1934 9 – 11 – 1961 Setyabudi 590 Tahun 1961 7. Jawa Timur 1897 – 1950 9 – 11 – 1961 Si Singamangaradja XII 590 Tahun 1961 8. Sumatera Utara 1849 – 1907 9 – 11 – 1961 Dr.G.S.S.J.Ratulangi 590 Tahun 1961 9. Sulawesi Utara 1890 – 1949 9 – 11 – 1961 Dr. Sutomo 657 Tahun 1961 10. Jawa Timur 1888 – 1938 27 – 12 – 1961 K.H. Ahmad Dahlan 657 Tahun 1961 11. D.I. Yogyakarta 1868 – 1934 27 – 12 – 1961 K.H. Agus Salim 657 Tahun 1961 12. Sumatera Barat 1884 – 1954 27 – 12 – 1961 Jenderal Gatot Subroto 222 Tahun 1962 13. Jawa Tengah 1907 – 1962 18 – 6 1962 Sukardjo Wirjopranoto 342 Tahun 1962 14. Jawa Tengah 11903 – 1962 29 – 10 – 1962 Dr. Ferdinand Lumban Tobing 361 Tahun 1962 15. Sumatera Utara 1899 – 1962 17 – 11 – 1962 K.H. Zainul Arifin 35 Tahun 1963 16. Sumatera Utara 1909 – 1963 4 – 3 – 1963 Tan Malaka 53 Tahun 1963 17. Sumatera Utara 1884-1949 28 – 3 – 1963 MGR A.Sugiopranoto, S.J.