Pembentukan Uu No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

History of Badminton
Facts and Records History of Badminton In 1873, the Duke of Beaufort held a lawn party at his country house in the village of Badminton, Gloucestershire. A game of Poona was played on that day and became popular among British society’s elite. The new party sport became known as “the Badminton game”. In 1877, the Bath Badminton Club was formed and developed the first official set of rules. The Badminton Association was formed at a meeting in Southsea on 13th September 1893. It was the first National Association in the world and framed the rules for the Association and for the game. The popularity of the sport increased rapidly with 300 clubs being introduced by the 1920’s. Rising to 9,000 shortly after World War Π. The International Badminton Federation (IBF) was formed in 1934 with nine founding members: England, Ireland, Scotland, Wales, Denmark, Holland, Canada, New Zealand and France and as a consequence the Badminton Association became the Badminton Association of England. From nine founding members, the IBF, now called the Badminton World Federation (BWF), has over 160 member countries. The future of Badminton looks bright. Badminton was officially granted Olympic status in the 1992 Barcelona Games. Indonesia was the dominant force in that first Olympic tournament, winning two golds, a silver and a bronze; the country’s first Olympic medals in its history. More than 1.1 billion people watched the 1992 Olympic Badminton competition on television. Eight years later, and more than a century after introducing Badminton to the world, Britain claimed their first medal in the Olympics when Simon Archer and Jo Goode achieved Mixed Doubles Bronze in Sydney. -

Risalah Sidang Perkara Nomor 71/Puu-Xiv/2016
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PIHAK TEKAIT DAN AHLI PEMOHON (IV) J A K A R T A SELASA, 25 OKTOBER 2016 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------- RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 71/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Rusli Habibie ACARA Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait dan Ahli Pemohon (IV) Selasa, 25 Oktober 2016 Pukul 11.19 – 13.00 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat (Ketua) 2) Aswanto (Anggota) 3) Patrialis Akbar (Anggota) 4) Wahiduddin Adams (Anggota) 5) I Dewa Gede Palguna (Anggota) 6) Suhartoyo (Anggota) 7) Manahan MP Sitompul (Anggota) Syukri Asy’ari Panitera Pengganti i Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Heru Widodo 2. Meyke Camaru 3. Aan Sukirman 4. Supriyadi Adi 5. Dimas Pradana B. Ahli dari Pemohon: 1. H.A.S. Natabaya C. Pemerintah: 1. Hotman Sitorus 2. Wahyu Jaya Setia Azhari D. -

(2011), “Kointegrasi Bursa Bu
BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan Hendrawan & Gustyana (2011), “Kointegrasi Bursa bursa saham di Asia” penelitian ini bertujuan untuk menguji keterkaitan antar bursa saham Asia yang terdiri dari bursa saham Jakarta Composite (^JKSE)- Indonesia, KLSE Composite (^KLSE)- Malaysia, Thailand Composite Index (^SET). Philipines Composite Index (^PSEI)-Philipina. Straits Times (^STI)- Singapura, Nikkei 225 (^N225)- Jepang, Hang Seng (^HSI)- Hongkong, Seoul Composite (^KS11)- Korea selatan, Shanghai Composite (^SSEC)- Cina dengan mengunakan data periode januari tahun 2000 sampai dengan januari 2010. Metode yang digunakan adalah metode johansen yaitu multivariate cointegration dan bivariate cointegration. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat integrasi dalam keseimbangan jangka panjang (kointegrasi) pada bursa saham Asia periode januari 2000- januari 2010 dibuktikan dengan adanya 5 vektor dalam uji multivariate cointegration dan dalam uji bivariate cointegration menunjukan terdapat 36 kemungkinan pasangan bursa dengan 28 pasang bursa menunjukan kointegrasi, 1 pasang bursa menunjukan kointegrasi meskipun kecil dan sisanya 7 pasang bursa tidak menunjukan kointegrasi. Nurhayati (2010), “Analisis Integrasi Pasar Modal Kawasan ASEAN dalam rangka menuju masyarakat ekonomi ASEAN” Penelitian ini menguji integrasi pasar modal di kawasan ASEAN yaitu negara Indonesia, Malaysia, Philiphina, 10 11 Singapura, Thailand dengan mengunakan data time series bulanan Indeks Harga Saham Gabungan masing masing bursa efek di kelima Negara dari bulan juli 1997 sampai maret 2010. Pengujian dalam penelitian ini adalah uji deteksi stasioneritas, uji kointegrasi, uji kointegrasi johansen dan uji kointegrasi berbasis ARDL. Hasil penelitian ini menunjukan dalam jangka pendek integrasi pasar modal tidak terjadi ditunjukan dengan data tidak stasioneritas pada tingkat level. Dalam jangka panjang terjadi integrasi pasar modal (kointegrasi), walaupun tidak sepenuhnya. -
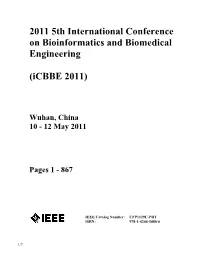
A Visualization Quality Evaluation Method for Multiple Sequence Alignments
2011 5th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering (iCBBE 2011) Wuhan, China 10 - 12 May 2011 Pages 1 - 867 IEEE Catalog Number: CFP1129C-PRT ISBN: 978-1-4244-5088-6 1/7 TABLE OF CONTENTS ALGORITHMS, MODELS, SOFTWARE AND TOOLS IN BIOINFORMATICS: A Visualization Quality Evaluation Method for Multiple Sequence Alignments ............................................................1 Hongbin Lee, Bo Wang, Xiaoming Wu, Yonggang Liu, Wei Gao, Huili Li, Xu Wang, Feng He A New Promoter Recognition Method Based On Features Optimal Selection.................................................................5 Lan Tao, Huakui Chen, Yanmeng Xu, Zexuan Zhu A Center Closeness Algorithm For The Analyses Of Gene Expression Data ...................................................................9 Huakun Wang, Lixin Feng, Zhou Ying, Zhang Xu, Zhenzhen Wang A Novel Method For Lysine Acetylation Sites Prediction ................................................................................................ 11 Yongchun Gao, Wei Chen Weighted Maximum Margin Criterion Method: Application To Proteomic Peptide Profile ....................................... 15 Xiao Li Yang, Qiong He, Si Ya Yang, Li Liu Ectopic Expression Of Tim-3 Induces Tumor-Specific Antitumor Immunity................................................................ 19 Osama A. O. Elhag, Xiaojing Hu, Weiying Zhang, Li Xiong, Yongze Yuan, Lingfeng Deng, Deli Liu, Yingle Liu, Hui Geng Small-World Network Properties Of Protein Complexes: Node Centrality And Community Structure -

UNIVERSITAS INDONESIA Analisis SWOT Teknik Situational Crime
UNIVERSITAS INDONESIA Analisis SWOT Teknik Situational Crime Prevention Pada Kawasan Perumahan Industri PT Chevron Pacific Indonesia di Duri Residential Industrial Area SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Kriminologi Disusun Oleh : Franz Hendrawan P 0806347353 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN KRIMINOLOGI DEPOK JULI, 2012 Analisis SWOT..., Franz Hendrawan P., FISIP UI, 2012 Analisis SWOT..., Franz Hendrawan P., FISIP UI, 2012 Analisis SWOT..., Franz Hendrawan P., FISIP UI, 2012 KATA PENGANTAR Puji syukur saya penjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada: (1) Yogo Tri Hendiarto, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini; (2) kemudian kepada Kombes Pol (Purn) Drs. P.H. Hutadjulu, M.M selaku penguji yang telah bersedia menguji peneliti; (3) orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan moral dan material; dan (4) sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan -

54Th Annual Commencement 54TH
54th Annual Commencement 54TH Brilliant Future Juris Doctor Degrees MAY 11 Doctor of Medicine Degrees JUNE 1 Master of Fine Arts and Doctoral Degrees JUNE 15 Master’s and Baccalaureate Degrees JUNE 14, 15, 16, 17 Table of Contents 2019 Commencement Schedule of Ceremonies . 3 Chancellor’s Award of Distinction . 4 Message from the Chancellor . 5 Message from the Interim Vice Chancellor, Student Affairs . 6 Deans’ Messages & Ceremonies Claire Trevor School of the Arts. 7-8 School of Biological Sciences . 9-10 The Paul Merage School of Business . 11-12 School of Education . .13-14 Samueli School of Engineering . .15-16 Susan and Henry Samueli College of Health Sciences . 17-21 School of Medicine . 18, 20 Sue & Bill Gross School of Nursing . 18, 21 Department of Pharmaceutical Sciences . .19, 21 Program in Public Health . .19, 21 School of Humanities . 22-23 Donald Bren School of Information & Computer Sciences . 24-25 School of Law . 26-27 School of Physical Sciences . .28-29 School of Social Ecology . 30-31 School of Social Sciences . 32-33 Graduate Division . .34-35 List of Graduates Advanced Degree Candidates . 36 Undergraduate Degree Candidates Claire Trevor School of the Arts. 47 School of Biological Sciences . .48 The Paul Merage School of Business . 52 School of Education . 54 The Henry Samueli School of Engineering . 55 School of Humanities . .60 Donald Bren School of Information & Computer Sciences . 63 Sue & Bill Gross School of Nursing . 67 Department of Pharmaceutical Sciences . 67 School of Physical Sciences . 68 Program in Public Health . 70 School of Social Ecology . 73 School of Social Sciences . -

Analisis Perencanaan Dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil
ANALISIS PERENCANAAN DAN EVALUASI ANGGARAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TESIS O L E H TEUKU RULLY HENDRAWAN NPM. 171801044 PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2019 UNIVERSITAS MEDAN AREA ANATISIS PERENCANAAN DAN EVALUASI ANGGARAN DATAM MEMNGKATKAN KINERJA PBMBRINTAH DAERAH KABTJPATEN ACEH SINGKIL TESIS gelar Magrster Administrasi Publik Sebagai-puai salah satu syarat untuk memperoleh program Stuii Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area OLEH TET]KU RT]LLY HENDRAWAN NPM. 171801044 PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PTIBTIK UNTVERSITAS MEDAI\ AREA MEDAN 2019 UNIVERSITAS MEDAN AREA UNIVERSITAS MEDAFT AREA PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK HALAMAN PERSETUJUAN Judul : Analisis Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nama Teuku Rully Hendrawan NPM 171801044 l\zfenyetujui Pembimbing I Pembimbing II l^ tu M.AP Prof. Dr. Marlon, Sihombing, MA ri Lubis, S.STP, Ketua Program Studi Direktur \Iagister Ilmu Administrasi Publik (t. Prof. ili.t Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS UNIVERSITAS MEDAN AREA PERT{YATAAN Denganinisayamenyatakanbahwadalamtesisinitidakterdapatkaryayang Perguruan Tinggi dan pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suafu atau pendapat yang pematr ditulis sepanjang pengetahuan saya juga tidak tedapat karya terfilis diacu dalam naskah ini dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara disebutkan dalam daftar Pustaka Medan,27 APil2019 -
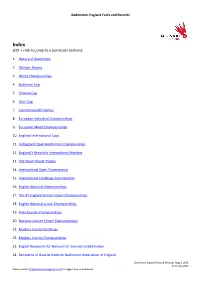
Facts and Records
Badminton England Facts and Records Index (cltr + click to jump to a particular section): 1. History of Badminton 2. Olympic Games 3. World Championships 4. Sudirman Cup 5. Thomas Cup 6. Uber Cup 7. Commonwealth Games 8. European Individual Championships 9. European Mixed Championships 10. England International Caps 11. All England Open Badminton Championships 12. England’s Record in International Matches 13. The Stuart Wyatt Trophy 14. International Open Tournaments 15. International Challenge Tournaments 16. English National Championships 17. The All England Seniors’ Open Championships 18. English National Junior Championships 19. Inter-County Championships 20. National Leisure Centre Championships 21. Masters County Challenge 22. Masters County Championships 23. English Recipients for Honours for Services to Badminton 24. Recipients of Awards made by Badminton Association of England Badminton England Facts & Records: Page 1 of 86 As at May 2021 Please contact [email protected] to suggest any amendments. Badminton England Facts and Records 25. English recipients of Awards made by the Badminton World Federation 1. The History of Badminton: Badminton House and Estate lies in the heart of the Gloucestershire countryside and is the private home of the 12th Duke and Duchess of Beaufort and the Somerset family. The House is not normally open to the general public, it dates from the 17th century and is set in a beautiful deer park which hosts the world-famous Badminton Horse Trials. The Great Hall at Badminton House is famous for an incident on a rainy day in 1863 when the game of badminton was said to have been invented by friends of the 8th Duke of Beaufort. -

Diplomatic List – Fall 2018
United States Department of State Diplomatic List Fall 2018 Preface This publication contains the names of the members of the diplomatic staffs of all bilateral missions and delegations (herein after “missions”) and their spouses. Members of the diplomatic staff are the members of the staff of the mission having diplomatic rank. These persons, with the exception of those identified by asterisks, enjoy full immunity under provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Pertinent provisions of the Convention include the following: Article 29 The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom, or dignity. Article 31 A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of: (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; (b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as an executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State; (c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside of his official functions. -- A diplomatic agent’s family members are entitled to the same immunities unless they are United States Nationals. -

Ferry Sonneville
FERRY SONNEVILLE _. Karya dan Pengabdiannya MILIK DEPDIKBUD TIDAK DIPERDAGANGKAN FERRY SONNEVILLE Karya dan Pengabdiannya Oleh: Wisnu Subagyo p . 1 Nomor lnduk : I Tanggal ii 0 ,_DEC 20W DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL JAKARTA 1985 SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAY AAN Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradi sional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku-buku biografi tokoh dan pahlawan nasional. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut. Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerja sama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang. Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita ting katkan untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak pa da kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan mem bina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional. Saya meng1'arapkan dengan terbitnya buK.u-buku ini da pat menarribah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlu kan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pem- iii bangunan kebudayaan. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini. Jakarta, Desember 1984 Direktur Jenderal Kebudayaan )f M� Prof. Dr. Haryati Soebadio NIP. 1301191 23 iv KATA PENGANTAR Proyek lnventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudaya an, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengerjakan penulisan biografi "tokoh" yang telah berjasa da lam masyarakat. -

Bab Ii Penguasaan Atas Tanah, Hak Atas Tanah Dan
BAB II PENGUASAAN ATAS TANAH, HAK ATAS TANAH DAN PERALIHANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA A. Penguasaan Atas Tanah Penguasaan di dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 529 menegaskan: “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.” Berdasarkan rumusan Pasal 529 KUHPerdata, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja berpendapat bahwa:1 “Dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang haknya kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.” Menurut Boedi Harsono, penguasaan tanah dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek fisik. Penguasaan tanah secara yuridis dilandasi oleh suatu hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai tanah tersebut secara fisik. Hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang 1 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Kedudukan Berkuasa & Hak Milik -

Studi Kasus Pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani)
BAB III KEDUDUKAN DEBITOR PASCA PUTUSAN PKPU OLEH PENGADILAN NIAGA (Studi Kasus pada Koperasi Serba Usaha Persada Madani) A. Bilyet Giro yang Telah Jatuh Tempo dan Tidak Dibayar merupakan Utang dalam Syarat Pemohonan PKPU Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.98 Pengertian utang diatur dalamPasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu: “kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.” Menurut Kartini Muljadi, utang dalam Undang-Undang Kepailitan merujuk pada hukum perikatan dalam hukum Perdata. Kartini Muljadi mengaitkan pengertian utang itu dengan Pasal 1233 dan 1234 KUHPerdata. Pengertian utang sama dengan pengertian kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban karena setiap perikatan, yang menurut Pasal 1234 KUHPerdata dilahirkan baik karena perjanjian 98 Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 56 57 maupun karena Undang-Undang. Selanjutnya Kartini Muljadi menghubungkan