Pengembang Islam Dan Budaya Moderat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Muslim Negarawan: Telaah Atas Pemikiran Dan Keteladanan Buya Hamka
Andi Saputra MUSLIM NEGARAWAN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN DAN KETELADANAN BUYA HAMKA Andi Saputra Mahasiswa Pascasarjana Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pe- mikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Surel: [email protected] Abstract One of the primary values inherent in the personality of the nation (founding father) in addition to the breadth of insight is the strong pas- sion and love for the homeland nationality. Philosophy of life that stands on the foundation of nationalism and patriotism that is then color every movement, behavior as well as the epic struggle deeds they do, for the grounding the ideals of independence. Along with that, especially in the context of the independence of the nation, teaching in the form of ideas and ideals that appear to be important life values for the next generation. Besides an attempt to take the essence of the teaching given, also related to the effort to continue to foster national values and love of the homeland as the ethical foundation in terms of bringing the nation to the gates of progress. One in a series of well-known national leader is Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka); a statesman who thinks that nation- alism and patriotism as part of the faith (religion). Through a sociolog- ical theory of knowledge Mannheim has found that important teaching presented Hamka in relation to the life of the nation that is their re- sponsibility that must be realized that every citizen. Responsibilities shall include nationality, homeland, all of which according to Hamka in line with the main principles of Islam, namely amar ma’ruf nahi munkar. -
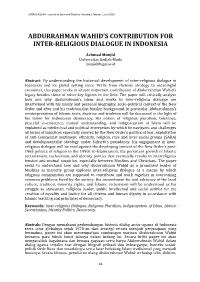
Abdurrahman Wahid's Contribution for Inter
JURNAL AQLAM – Journal of Islam and Plurality –Volume 5, Nomor 1, Juni 2020 ABDURRAHMAN WAHID’S CONTRIBUTION FOR INTER-RELIGIOUS DIALOGUE IN INDONESIA Achmad Munjid Universitas Gadjah Mada [email protected] Abstract: By understanding the historical development of inter-religious dialogue in Indonesia and its global setting since 1970s from rhetoric strategy to meaningful encounter, this paper seeks to situate important contribution of Abdurrahman Wahid’s legacy besides those of other key figures in the field. The paper will critically analyze how and why Abdurrahman’s ideas and works in inter-religious dialogue are intertwined with his family and personal biography, socio-political context of the New Order and after and his traditionalist Muslim background. In particular, Abdurrahman’s reinterpretation of Islamic texts, doctrine and tradition will be discussed in the light of his vision for Indonesian democracy. His notion of religious pluralism, tolerance, peaceful co-existence, mutual understanding, and indigenization of Islam will be explained as intellectual and political enterprises by which he navigates and challenges all forms of injustices especially created by the New Order’s politics of fear, exploitation of anti-Communist sentiment, ethnicity, religion, race and inter-social groups (SARA) and developmentalist ideology under Suharto’s presidency. His engagement in inter- religious dialogue will be read against the developing context of the New Order’s post- 1965 politics of religion to the 1990s re-Islamization, the persistent growth of Islamic sectarianism, exclusivism, and identity politics that eventually results in interreligious tension and mutual suspicion, especially between Muslims and Christians. The paper seeks to understand how and why Abdurrahman Wahid as a prominent leader of Muslims as majority group explores inter-religious dialogue as a means by which religious communities are supposed to contribute and work together in overcoming common problems faced by the society. -

Mengenang Kembali Sosok Mukti Ali Dan Relevansi Pemikirannya Terhadap Pendidikan Indonesia Era Milenium
DOI: 10.31002/ijel.v1i2.654 Mengenang Kembali Sosok Mukti Ali.. | 129 MENGENANG KEMBALI SOSOK MUKTI ALI DAN RELEVANSI PEMIKIRANNYA TERHADAP PENDIDIKAN INDONESIA ERA MILENIUM Rafiqa Noviyani Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Email: [email protected] Abstrak Tujuan penulisan ini untuk mengenang kembali sosok Mukti Ali sebagai ingatan segar di era milenium sehingga memberikan semangat baru dalam menelaah kembali tujuan pendidikan di Indonesia. Sejatinya pemikiran pendidikan Mukti Ali telah memberikan warna untuk konsep pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan direvisinya konsep kurikulum pendidikan Indonesia menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sederhananya ingin memadukan berbagai nilai pendidikan dalam pembelajaran. Fokus penulisan ini membahas pada siapa sosok Mukti Ali dalam dunia pendidikan dan bagaimana konsep dan relevansi pendidikan Mukti Ali untuk Indonesia di era milenium. Untuk mendapatkan data tersebut penulis lacak melalui beberapa sumber yaitu mengumpulkan beberapa karya asli dari Mukti Ali dan sumber pendukung yang berkaitan. Hasil dari penulisan ini menjelaskan bahwa konsep pemikiran pendidikan Mukti Ali didasarkan pada konsep keilmuan yang dikenal dengan istilah scientific-cum-doctrinaire, konsep kebangsaan dikenal dengan istilah agree in disagreement, dan konsep kemanusiaan. Dengan ketiga fokus pemikiran ini, Mukti Ali berupaya membangun peradaban dan pendidikan melalui hasil keputusan SKB 3 Menteri yaitu adanya kesamaan derajat lulusan sekolah umum dan madrasah. Yang artinya Mukti Ali telah menggagas -
![Archipel, 100 | 2020 [En Ligne], Mis En Ligne Le 30 Novembre 2020, Consulté Le 21 Janvier 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/8932/archipel-100-2020-en-ligne-mis-en-ligne-le-30-novembre-2020-consult%C3%A9-le-21-janvier-2021-398932.webp)
Archipel, 100 | 2020 [En Ligne], Mis En Ligne Le 30 Novembre 2020, Consulté Le 21 Janvier 2021
Archipel Études interdisciplinaires sur le monde insulindien 100 | 2020 Varia Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/archipel/2011 DOI : 10.4000/archipel.2011 ISSN : 2104-3655 Éditeur Association Archipel Édition imprimée Date de publication : 15 décembre 2020 ISBN : 978-2-910513-84-9 ISSN : 0044-8613 Référence électronique Archipel, 100 | 2020 [En ligne], mis en ligne le 30 novembre 2020, consulté le 21 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/archipel/2011 ; DOI : https://doi.org/10.4000/archipel.2011 Ce document a été généré automatiquement le 21 janvier 2021. Association Archipel 1 SOMMAIRE In Memoriam Alexander Ogloblin (1939-2020) Victor Pogadaev Archipel a 50 ans La fabrique d’Archipel (1971-1982) Pierre Labrousse An Appreciation of Archipel 1971-2020, from a Distant Fan Anthony Reid Echos de la Recherche Colloque « Martial Arts, Religion and Spirituality (MARS) », 15 et 16 juillet 2020, Institut de Recherches Asiatiques (IRASIA, Université d’Aix-Marseille) Jean-Marc de Grave Archéologie et épigraphie à Sumatra Recent Archaeological Surveys in the Northern Half of Sumatra Daniel Perret , Heddy Surachman et Repelita Wahyu Oetomo Inscriptions of Sumatra, IV: An Epitaph from Pananggahan (Barus, North Sumatra) and a Poem from Lubuk Layang (Pasaman, West Sumatra) Arlo Griffiths La mer dans la littérature javanaise The Sea and Seacoast in Old Javanese Court Poetry: Fishermen, Ports, Ships, and Shipwrecks in the Literary Imagination Jiří Jákl Autour de Bali et du grand Est indonésien Śaivistic Sāṁkhya-Yoga: -

Bruinessen 04 Traditionalistandi
"'Traditionalist' and 'Islamist' pesantrens in Indonesia", paper presented at the workshop 'The Madrasa in Asia, transnational linkages and alleged or real political activities', ISIM, Leiden, 24-25 May 2004. [updated version] New Page 1 ‘Traditionalist’ and ‘Islamist’ pesantren in contemporary Indonesia Martin van Bruinessen, ISIM, Netherlands Paper presented at the workshop 'The Madrasa in Asia, transnational linkages and alleged or real political activities', ISIM, Leiden, 24-25 May 2004. Like the madrasa in India and Pakistan, the Indonesian pesantren — religious boarding schools, the local variant of the madrasa — have in recent years drawn some unfriendly attention due to suspicions of their involvement in radical and possibly terrorist activities. The Indonesian authorities did not appear to share those suspicions, certainly not concerning the pesantren in general, but those of the Philippines, Singapore, Australia and the US, as well as numerous international journalists have shown grave concern. This was mostly due to the fact that some highly visible terrorism suspects share a connection with one particular pesantren in Central Java, the PP (Pondok Pesantren) Al- Mukmin in Ngruki near Solo or with one of a small number of offshoots from this school.[1] Ustad Abu Bakar Ba’asyir, who was one of the founders of this pesantren in the early 1960s and who returned there in 1999 after fourteen years spent in Malaysian exile, has been accused of being the spiritual leader of an underground movement known as Jama’ah Islamiyah, which is believed to be active all over Muslim Southeast Asia and to have carried out a large number of terrorist actions in this region. -
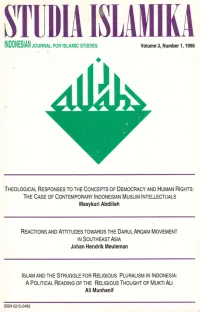
STUDIAISLAIIIKA IND0NESIAN Journal for Rslamrc Studtes Volume 3, Number 1, 1996
STUDIAISLAIIIKA IND0NESIAN JouRNAL FoR rsLAMrc sTUDTES Volume 3, Number 1, 1996 THTOIOEICAL RESPoNSES To THE CoNCEPTS OF DTUOCnRCY AND HUITIRITI RICHTS: THr Cnse or ConreupoRARy INDoNESTAN MusltH,t lrurellrcruRts Masykuri Abdillah RTRCTIOTs AND ATTITUDES ToWARDS THE DnnUIAnOAM MOVEMENT IIrI SOUTHTRST ASIA Johan Hendrik Meuleman IsI-RIrI AND THE SrRuceIr FoR RELIGIoUS PLURALISM IN IITIOOTrSN: A POLITICAL READING OF THE RELIGIOUS THOUGHT OF MUKTIALI Ali Munhanif lssN 0215-0492 $TI]NIA ISTAilIII(A Indonesian Journal for lslamic Studies Volume 3, Number 1, 1996 EDITORIAT BOARD: Harun Nasution Mastubu M. Qurakb Sbibab A. Azb Dablan M. SatrhEffendi Nabilab Lubis M. YunanYusuf Komaruddin Hidayat M. Din$amsuddin Muslim Nasution Wabib Mu'tbi EDITOR.IN.CHIEF: Azlumardi Azra EDITON: Sadul Mujani Hendro Prasetyo Joban H. Meuleman Didin Syafruddin Ali Munbanif ASSISTANTS TO THE EDITOR: Arief Subban Heni Nuroni ENGTISH LANGUAGE ADVISOR: Judith M. Dmt ARABIC LANGUAGE ADVISOR: Fuad M. Facbruddin COVER DESIGNER: S. Pinka STUDIA ISLAMIIG OSSN 0215-0492) is a lournal published quarterly by the Institut Agama Islam Negen (IAIN, The State Institute for Islamic Studies) Syarif Hidayatullah, Jakarta. (STT DEPPEN No. 1294K/DITJENiPPG/STTA976) and sponsored by the Depanment of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. It specializes in Indonesian Islamic snrdies, and is intended to communi. cate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. All anicles published do not necessarily represent the views of the lournal, or other institutions to which it is affiliated. They are solely the vievrs of the authors. - Ali Munhanif Islam and the Struggle for Religious Pluralism in Indonesia; A Political Reading of the Religious Thought of Mukti Ali Abstraksi: Problem dialog antar-urnat beragama merupakan salah satu udcand penting dalam perkembangan pemikiran keagamaan Indonesia modern. -

Blografl Tokoh Perempuan Dari Surnatera
b I do .run\ 801) v k 1 all( Vd/aalr - ~J(s) '* ya D. If2 2ed b 1 :' 1. , --L BlOGRAFl RANGKAYO H.J= SYAMSJDAR YAHYA (1914-1975) Tokoh Perempuan dari Surnatera Pusat Kajian iosialdudaya & Ekonorni (PKSBE), Fakultas Ilmu-llmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Padang '2010 BIOGRAFI RANGKAYO HJ. SYAMSIDAR YAHYA (191 4-1 975) Tokoh Perempuan Sumatera KATA ASKAH asli tulisan ini berasal dari serangkaian penelitian pendahuluan yang dikerjakan dalam beberapa tahap sejak pertengahan 2008. Mula-mula kami meminta kesediaan Sdr. Ferawati S.S., anggota tim peneliti freelance di Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE), FIS, Universitas Negeri Padang untuk melakukan riset lapangan. Sembari melengkapi data penelitiannya, sejak pertengahan 2008 Ferawati sudah mulai membuat catatan- catatan lepas ke dalam draf -draf kasar dalam beberapa bab yang belurn lengkap datanya. Masih banyak bagian-bagian yang kosong, tetapi bagiamanapun ia sudah berhasil mengmpulkan sejumlah informasi awal yang dapat digunakan untuk memulai penulisan draft pertama pada akhir 2009. Draf awal naskah ini baru dapat dirampungkan akhir 2008. Itu pun masih ada sejumlah data lapangan yang mesti dilengkapi sambil meneruskan studi pustaka tankahan sekedarnya sebelum naskah ini dapat disempurnakan. Draf kedua mengalami penundaan karena Sdr Ferawati makin terlibat dengan kesibukan barunya , menyiapkan studi lanjutan dan kursus-kursus Inggris untuk ke Belanda. Tadinya saya sangat mengharapkan kesediaan Sdr Dr. Siti Fatimah,M.Hwn untuk menuntaskan buku ini. Terlebih lagi karena keahliannya dalam women studies. Namun karena keterikatannya dengan kesibukan yang tak terelakkan, beliau 'membenar ' kepada saya agar dicarikan yang lain saja, yang memiliki cukup waktu untuk melanjutkan riset ini. PKSBE akhirnya menemukan orang yang tepat untuk tugas in2 tatkala menemukan orang muda yang enerjetik. -

Awal Abad Xx
I (;:HPUSTAKAAN 1 •{) Ll(JC '} .-. '"' iv!\ {\ "'· '<..J 1,_~1.' I).. Ase. ~ ,,_ AS·'"' /-\ .. ~.,'>.I" ~ -· .il\.~ ... I 1·--lAlN :):~ h~\ YO\:iYAK-:.tflA. I PEMBAHARUAN ISLAM DI INDONESIA AWAL ABAD XX: Studi Terhadap Pemikiran Dr. H. Abdul Karim Amrullah Oleh: Zulmuqim NIM: 933009 DISERTASI J-17- 'iJL ~S NJL f,I c; ~ Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam YOGYAKARTA 2001 PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini saya menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah basil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yanag dirujuk sumbernya Padang, 9 April 200 l Saya yang menyatakan \ rs. Zulmugim, M.A. NIM.933009 .... --~ .. ~. ti. PERNYATAAN KEASLIAN Dengan ini saya menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah basil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbemya. Jambi, 18 Februari 2000 .. ··.···.· '. JI .-. -..,~~ menyatakan JDrs. Zulmuqim, M.A. NIM. 933009 DEPARTEMEN AGAMA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PENGESAHAN DISERTASI berjudul : PEMBAHARUAN ISLAM DI INJX>NEBIA AWAL ABAD XX : Studi temada.p Pemik:ira.n ~. H. Abdul Ka.rim .Amrullah Ditulis oleh Dre. Zulmuqim, M.A. NIM 93;003 I s3 Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam llmu Agama Islam Yogyakarta, 30 Juli 2001 .• ' ,• OEPl\RTEllEN AQAMA IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA/PROMOSI Nama : Drs. Zulalqim, M.A. NIM : 933003 I S3 Judul : PD!BAHA.RUAB ISLAM lil INDONESIA AWAL Al3AD XX : stmi te:rhadap pemikiran Dr. H. Abdul Karim Amrullah Ketua : Prof• Br. H.M. Atho Mudzbar Sekretaris : Prof'. :Dr. H.M. Amin Abdullah Anggota : 1. -

Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism After Suharto
Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities Vol. 1, 2008, pp. 23–51 URL: http://jissh.journal.lipi.go.id/index.php/jissh/article/view/2 DOI: 10.14203/jissh.v1i1.2 Copyright: content is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License ISSN: 1979-8431 (printed), 2656-7512 (Online) Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto Noorhaidi Hasan Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta Abstract This paper examines the rising tide of ethno-religious conflicts and Islamic radicalism in the political arena of post-Suharto Indonesia. In the climate of Reformasi that heralded freedom of expression, ethnic and religious violence flared up in various regions of Indonesia, threatening a society apparently imbued with a culture of tolerance based on harmonious inter-ethnic and inter-faith relations. In a flurry of conflicts, a number of militant Muslim groups arose and engulfed the political arena of post-Suharto Indonesia by calling for jihad and other violent actions. The rise of the groups gave a remarkable boost to the explosion of militant religious discourses and activism that threaten Indonesia’s reputation for practising a tolerant and inclusive form of Islam and threaten, too, the integrity of the Indonesian nation-state as well. Against the backdrop of the state–Islam relationship in the New Order, this paper looks at how this phenomenon is embedded in the state’s failure to manage properly religious diversity and civic pluralism. In the context of mounting competition among elites, religion has become tremendously politicised and has served more as a tactical tool used by political contenders in their own interests. -

Genealogi Intelektual Tokoh Pembaharuan Mesir
Available online at: https://ejournal.fah.uinib.ac.id/index.php/khazanah Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam ISSN: 2339-207X (print) ISSN: 2614-3798 (online) Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam DOI: https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0. 55 SENTRALISASI ISLAM MARJINAL: Konstruksi Pemikiran Hamka dalam Historiografi Islam Melayu-Nusantara Lukmanul Hakim Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang E-mail: [email protected] Abstract This paper aims to analyze the thoughts of Hamka in Malay Islamic Nysties Historiography. The method used is historical method, especially historiography approach. Characteristic of Hamka's work; First, writing techniques; Not using footnotes, style of language; Simple, alive, and communicative. The sources used by Hamka can be grouped into three groups; Primary sources, historical books composed by Muslim authors themselves; Second, the second source of material is the Dutch and British writers' writings on Indonesia and the Malay Land; Third, the third source of material materials that allegedly most of the writers of Islamic history in Indonesia did not get it. While from the Method of Historical Criticism, according to Hamka there are two ways to write history among Muslims; First collecting all the facts wherever it comes from, no matter whether the facts make sense or not, what needs to be taken care of is where this history is received. Second, judging the facts and giving their own opinions, after the facts were collected, this is the system used by Ibn Khaldun. 83 84 Sentralisasi Islam... Keywords: Hamka, Thought, Islamic Historiography, Malay Archipelago Abstrak Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis pemikiran Hamka dalam Historiografi Islam Melayu Nusantara. -

Regime Change, Democracy and Islam the Case of Indonesia
REGIME CHANGE, DEMOCRACY AND ISLAM THE CASE OF INDONESIA Final Report Islam Research Programme Jakarta March 2013 Disclaimer: The authors gratefully acknowledge financial support from the Islam Research Programme – Jakarta, funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. The views presented in this report represent those of the authors and are in no way attributable to the IRP Office or the Ministry CONTENTS INTRODUCTION 1 Kees van Dijk PART 1: SHARIA-BASED LAWS AND REGULATIONS 7 Kees van Dijk SHARIA-BASED LAWS: THE LEGAL POSITION OF WOMEN AND CHILDREN IN BANTEN AND WEST JAVA 11 Euis Nurlaelawati THE ISLAMIC COURT OF BULUKUMBA AND WOMEN’S ACCESS TO DIVORCE AND POST-DIVORCE RIGHTS 82 Stijn Cornelis van Huis WOMEN IN LOCAL POLITICS: THE BYLAW ON PROSTITUTION IN BANTUL 110 Muhammad Latif Fauzi PART 2: THE INTRODUCTION OF ISLAMIC LAW IN ACEH 133 Kees van Dijk ALTERNATIVES TO SHARIATISM: PROGRESSIVE MUSLIM INTELLECTUALS, FEMINISTS, QUEEERS AND SUFIS IN CONTEMPORARY ACEH 137 Moch Nur Ichwan CULTURAL RESISTANCE TO SHARIATISM IN ACEH 180 Reza Idria STRENGTHENING LOCAL LEADERSHIP. SHARIA, CUSTOMS, AND THE DYNAMICS OF VIGILANTE VIOLENCE IN ACEH 202 David Kloos PART 3: ISLAMIC POLITICAL PARTIES AND SOCIO-RELIGIOUS ORGANIZATIONS 237 Kees van Dijk A STUDY ON THE INTERNAL DYNAMICS OF THE JUSTICE AND WELFARE PARTY (PKS) AND JAMA’AH TARBIYAH 241 Ahmad-Norma Permata THE MOSQUE AS RELIGIOUS SPHERE: LOOKING AT THE CONFLICT OVER AL MUTTAQUN MOSQUE 295 Syaifudin Zuhri ENFORCING RELIGIOUS FREEDOM IN INDONESIA: MUSLIM ELITES AND THE AHMADIYAH CONTROVERSY AFTER THE 2001 CIKEUSIK CLASH 322 Bastiaan Scherpen INTRODUCTION Kees van Dijk Islam in Indonesia has long been praised for its tolerance, locally and abroad, by the general public and in academic circles, and by politicians and heads of state. -

What Happened to the Smiling Face of Indonesian Islam? Muslim Intellectualism and the Conservative Turn in Post-Suharto Indonesia
The RSIS Working Paper series presents papers in a preliminary form and serves to stimulate comment and discussion. The views expressed are entirely the author’s own and not that of the S. Rajaratnam School of International Studies. If you have any comments, please send them to the following email address: [email protected]. Unsubscribing If you no longer want to receive RSIS Working Papers, please click on “Unsubscribe.” to be removed from the list. No. 222 What happened to the smiling face of Indonesian Islam? Muslim intellectualism and the conservative turn in post-Suharto Indonesia Martin Van Bruinessen S. Rajaratnam School of International Studies Singapore 6 January 2011 About RSIS The S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) was established in January 2007 as an autonomous School within the Nanyang Technological University. RSIS’ mission is to be a leading research and graduate teaching institution in strategic and international affairs in the Asia-Pacific. To accomplish this mission, RSIS will: Provide a rigorous professional graduate education in international affairs with a strong practical and area emphasis Conduct policy-relevant research in national security, defence and strategic studies, diplomacy and international relations Collaborate with like-minded schools of international affairs to form a global network of excellence Graduate Training in International Affairs RSIS offers an exacting graduate education in international affairs, taught by an international faculty of leading thinkers and practitioners. The teaching programme consists of the Master of Science (MSc) degrees in Strategic Studies, International Relations, International Political Economy and Asian Studies as well as The Nanyang MBA (International Studies) offered jointly with the Nanyang Business School.