Wildan Imaduddin Muhammad
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Fiqh Council of North America (Revised)
IIssllaammiicc CCeenntteerr ooff BBoossttoonn,, WWaayyllaanndd WILL HENCEFORTH BE FOLLOWING THE RECOMMENDATIONS OF TTHHEE FFIIQQHH CCOOUUNNCCIILL OOFF NNOORRTTHH AAMMEERRIICCAA REGARDING THE ADOPTION OF AN AASTRONOMICALLY CCALCULATED IISLAMIC CCALENDAR DETAILED INFORMATION ABOUT THIS DECISION AND A CALENDAR FOR THE NEXT FIVE YEARS ARE PROVIDED IN THIS DOCUMENT. September 7th, 2007 RAMADAN AND EID ANNOUNCEMENT BY THE FIQH COUNCIL OF NORTH AMERICA (REVISED) 09- 5-07 15:21 The Fiqh Council of North America in its meeting in Herndon, Virginia on July 31- August 1, 2007 noted with satisfaction the recent Fatwa of its counterpart in Europe “the European Council for Fatwa and Research” related to the permissibility of the use of calculation method for determining the beginning of Lunar months including the months of Ramadan and Shawwal. The position of ECFR is very similar to the position of FCNA adopted last year on June 10, 2006, with a minor difference. FCNA adopted the position that the conjunction should occur before noon at Greenwich time. ECFR has adopted Makkah al-Mukarram as a conventional point and took the position that the conjunction must take place before sunset in Makkah and moon must set after sunset in Makkah. FCNA after careful discussion has revised its position and has adopted the Fatwa of ECFR. This revised position will change only a few dates in the Fiqh Council’s Five year calendar; but it will bring greater harmony and unity among the Muslims communities in the West. On the basis of this new position the dates of Ramadan and Eidul Fitr for this year are as follows: 1st of Ramadan will be on Thursday, September 13, 2007 1st of Shawwal will be on Saturday, October 13, 2007 Ramadan 1428 AH: The astronomical New Moon is on Tuesday, September 11, 2007 at 12:44 Universal Time (3:44 pm Makkah time). -
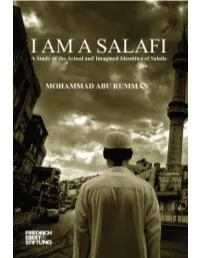
I Am a Salafi : a Study of the Actual and Imagined Identities of Salafis
The Hashemite Kingdom Jordan The Deposit Number at The National Library (2014/5/2464) 251.541 Mohammad Abu Rumman I Am A Salafi A Study of The Actual And Imagined Identities of Salafis / by Mohammad Abu Rumman Amman:Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014 Deposit No.:2014/5/2464 Descriptors://Islamic Groups//Islamic Movement Published in 2014 by Friedrich-Ebert-Stiftung Jordan & Iraq FES Jordan & Iraq P.O. Box 941876 Amman 11194 Jordan Email: [email protected] Website: www.fes-jordan.org Not for sale © FES Jordan & Iraq All rights reserved. No part of this publication may be reprinted, reproduced or utilized in any form or by any means without prior written permission from the publishers. The views and opinions expressed in this publication are solely those of the original author. They do not necessarily represent those of the Friedrich-Ebert Stiftung or the editor. Translation: Dr. Hassan Barari Editing: Amy Henderson Cover: YADONIA Group Printing: Economic Printing Press ISBN: 978-9957-484-41-5 2nd Edition 2017 2 I AM A SALAFI A Study of the Actual and Imagined Identities of Salafis by Mohammad Abu Rumman 3 4 Dedication To my parents Hoping that this modest endeavor will be a reward for your efforts and dedication 5 Table of Contents DEDICATION ........................................................................................................ 5 FOREWORD .......................................................................................................... 8 ACKNOWLEDGEMENTS ................................................................................ -

How Should Muslims Think About Apostasy Today?
2 | The Issue of Apostasy in Islam Author Biography Dr. Jonathan Brown is Director of Research at Yaqeen Institute, and an Associate Professor and Chair of Islamic Civilization at Georgetown University. Disclaimer: The views, opinions, findings, and conclusions expressed in these papers and articles are strictly those of the authors. Furthermore, Yaqeen does not endorse any of the personal views of the authors on any platform. Our team is diverse on all fronts, allowing for constant, enriching dialogue that helps us produce high-quality research. Copyright © 2017. Yaqeen Institute for Islamic Research 3 | The Issue of Apostasy in Islam The Shari’ah consists of some laws that remain the same regardless of changing circumstances and others that change with them. Most of the Shari’ah is up to individual Muslims to follow in their own lives. Some are for judges to implement in courts. Finally, the third set of laws is for the ruler or political authority to implement based on the best interests of society. The Shari’ah ruling on Muslims who decide to leave Islam belongs to this third group. Implemented in the past to protect the integrity of the Muslim community, today this important goal can best be reached by Muslim governments using their right to set punishments for apostasy aside. One of the most common accusations leveled against Islam involves the freedom of religion. The problem, according to critics: Islam doesn’t have any. This criticism might strike some as odd since it has been well established that both the religion of Islam and Islamic civilization have shown a level of religious tolerance that would make modern Americans blush. -

Mdno3 Version 6
Muslim Democrat www.islam-democracy.org Published by the Center for the Study of Islam & Democracy (CSID), Washington, D.C. Volume 4, No. 1, January 2002 In This Issue: ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ What’s Next For Afghanistan? 2 Reason and Freedom in Islamic Thought estroying Taliban and al-Qaeda was the easy part in the war against terrorism. The US has enough weapons and Dintelligence to destroy all of Afghanistan if it wanted to. The difficult part is what comes next. Will we leave Afghanistan destroyed, demoralized, impoverished, and hungry? Or are we going to help build Afghanistan into a 4 Interview with Sheikh Taha prosperous country and society? Are we going to impose another undemocratic regime on the Afghani people? Or are we, for a By Radwan A. Masmoudi Center for the Study of Islam change, going to help build a democratic and representative & Democracy (CSID) government in Afghanistan? The ultimate success or failure of the war on terrorism will depend on the answers to these questions. If we leave Afghanistan impoverished and devastated, the public opinion in the Muslim world will continue to see the U.S. as an enemy and the war on terrorism as revenge. However, 6 Islam & Democracy: The if we help to build a new, democratic, and prosperous nation, then people in the Muslim Struggle Continues world will begin to see the U.S. as a friend and an ally. Building a democratic regime in Afghanistan is not going to be easy because the country is in ruin. However, sometimes it is easier to build from scratch than to revamp an existing and failing system. -

An Explanatory Memorandum on the General Strategic Goal
The Muslim Brotherhood’s U.S. Network by Zeyno Baran ashington D.C. has suddenly become very interested in the Muslim Brotherhood. American policymakers are debating whether to engage non-violent elements of the Muslim Brother- hood network, both inside and outside the United States, in the hope that such engagement will empower these “moderates” Wagainst violent Wahhabi and Salafi groups such as al-Qaeda. Unfortunately, this strat- egy is based on a false assumption: that “moderate” Islamist groups will confront and weaken their violent co-religionists, robbing them of their support base. This lesser-of-two-evils strategy is reminiscent of the rationale behind the Cold War-era decision to support the Afghan mujahideen against the Soviet army. In the short term, the U.S. alliance with the mujahideen did indeed aid America in its struggle against the Soviet Union. In the long term, however, U.S. support led to the empowerment of a dangerous and potent adversary. In choosing its allies, the U.S. cannot afford to elevate short-term tactical considerations above longer-term strate- gic ones. Most importantly, the U.S. must consider the ideology of any potential part- ners. Although various Islamist groups do quarrel over tactics and often bear considerable animosity towards one another, they all agree on the endgame: a world dictated by political Islam. A “divide and conquer” strategy by the United States will only push them closer together. Even though the Muslim Brotherhood (in Arabic, al-Ikhwan al-Muslimun) does not openly call for violence or terrorism, it still does little to oppose it. -

A Critical Examination of Qur'an 4:34 and Its Relevance to Intimate Partner Violence in Muslim Families
A Critical Examination of Qur'an 4:34 and Its Relevance to Intimate Partner Violence in Muslim Families Author Ibrahim, Nada, Abdalla, Mohamad Published 2010 Journal Title Journal of Muslim Mental Health DOI https://doi.org/10.1080/15564908.2010.551278 Copyright Statement © 2010 Routledge. This is an electronic version of an article published in Journal of Muslim Mental Health, Volume 5, Issue 3, 2010 , pages 327-349. Journal of Muslim Mental Health is available online at: http://www.informaworld.com with the open URL of your article. Downloaded from http://hdl.handle.net/10072/38916 Griffith Research Online https://research-repository.griffith.edu.au A Critical Examination of Qur’an 4:34 and its Relevance to Intimate Partner Violence in Muslim Families Nada Ibrahim and Mohamad Abdalla Griffith University, Brisbane, Australia 2 A Critical Examination of Qur’an 4:34 Abstract This article examines Islam’s position on wife beating in the context of intimate partner violence (IPV). Though research indicates multiple causes of IPV, Islam is singled out as the main cause for violence against women in Muslim societies, based on the interpretation of verse 4:34 (which seemingly supports wife beating). This verse is often interpreted out of context and Islam’s position on IPV is confused with the issue of nushuz (contentiously translated as wife’s disobedience, flagrant defiance, and/or misbehavior). The lack of accurate translations compounds the problem for English readers. This article critically examines the legal meanings and implications of nushuz found in verse 4:34 within the context of IPV; and the authors contend that contextual understating of this is imperative for positive clinical engagement with Muslim clients. -

Books on Islam and the Muslim World
Books On Islam And The Muslim World Halalco Books 155 Hillwood Avenue Falls Church, VA 22046 (703) 532-3202 Fax: (703) 533-1234 or (703) 542-3212 [email protected] www.halalco.com CATALOG 2017 CATALOG 122815 H HOLY QUR’AN SEERAH: Books On/About The Qur’an . 44 Life Of Prophet Muhammad . 101 CONTENTS Color-Coded For Tajweed … 48 Some Aspects Of His Life ….104 Dictionaries & Concordances 49 Qaidahs & Reading Aids … 49 Shia-Sunni Perspectives …… 106 99 Names Of Allah ………………. 1 Qur’an In 30 Parts …………. 50 Sufism & Mysticism ……………. 106 Qur’an In Arabic Only …… 51 BIOGRAPHIES Qur’an In Uthmani Script… 51 Companions & Family ……… 1 Qur’an In Multi-Colors ……..51 <<<<<<<>>>>>>> Prophets & Others .. ……… 3 Qur’an In Zipper ………… 51 Selections/Partial Translatns.. 51 BOOKS IN OTHER LANGUAGES: Arabic (Separate Catalog) Tajweed Books …………….. 53 French (Separate Catalog) Transliterations …………… 53 Spanish (Separate Catalog) Halalco Urdu (Separate Catalog) HOLY QUR’AN TRANSLATIONS: Abdullah Yusuf Ali …………54 Books BOOKS ON OR BY: In The Shade Of The Qur’an .. 54 Ahmed Deedat …………….. 7 Marmaduke Pickthall ……….54 Your One-Stop Source Allama Iqbal (Poet) ……….. 7 Mohsin Khan (Noble Qur’an) 54 for all your shopping Harun Yahya ……………….. 8 Sayyid Abul Aala Maududi …55 Ibn Arabi …………………… 9 Other English Translations ….55 needs Ibn Sina (Avicenna) … … … 10 Tafsir Ibn Kathir …………… 56 Imam Al-Ghazali ……………. 10 In Other Languages …………57 Exotic Groceries Baklava, Cookies, Dates & Ready To Eat Foods Jalaluddin Rumi ……………. 12 Halal Marshmallows & Beef Sticks & Jerky Malcolm X …………………. 13 IBADAH & WORSHIP ………… 58 Du’a & Supplication ………. 58 International Gifts Shaikh Abdal-Qadir Al-Jilani . 14 Azan Clocks & Watches, Henna, Fasting & Ramadan ………… 60 Keychains & Dolls Children’s Books (Separate Catalog) Hajj & Umrah ………………. -

LIST of BOOKS in STOCK (English Language)
INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT P.O. Box 669 Herndon, VA 20172 USA ● Tel (703) 471-1133 ● Fax: (703) 471-3922 ● www.iiit.org ● E-mail: [email protected] LIST OF BOOKS IN STOCK (English Language) 1. A Brief Introduction to Qur’anic Exegesis, Ali Suleiman Ali, 2017, 188pp, $12.95. 2. A Guide for Authors, Translators, and Copy-editors: IIIT Style Sheet, 2002, 64pp, $6.50. 3. A Thematic Commentary on the Qur’an, Shaikh Muhammad al-Ghazali, 3rd ed., 2005, 804pp $27.95. 4. Abu Zayd Al-Balkhi’s Sustenance of the Soul: The Cognitive Behavior Therapy of A Ninth Century Physican, Malik Badri, 2013, 78pp $6.95. 5. Al-Shura: The Qur’anic Principle of Consultation, Ahmad Al-Raysuni, 2011, 206pp, $12.95- $22.95. 6. Al-Tawhid: Its Implications for Thought and life, Ismail Raji Al-Faruqi, 4th ed. 1998, 256pp, $8.95-$16.00. 7. Anthropomorphic Depictions of God: The Concept of God in Judaic, Christian, and Islamic Traditions: Representing the Unrepresentable, Zulfiqar Ali Shah, 2012, 764pp, $29.95-$39.95. 8. Apostasy in Islam: A Historical and Scriptural Analysis, Taha Jabir Alalwani, 2011, 168pp, $9.95-$19.95. 9. Apostates, Islam & Freedom of Faith: Change of Conviction VS Change of Allegiance, AbdulHamid AbuSulayman, 2013, 42pp, $5.95. 10. Approaching the Sunnah: Comprehension and Controversy, Yusuf Al-Qaradawi, 2006, 234pp, $16.95-$26.95. 11. Authentication of Hadith: Redefining the Criteria, Israr Ahmad Khan, 2010, 240pp $14.95-24.95. 12. Books-In-Brief: Al-Shura: The Qur’anic Principle of Consultation, Ahmad Al-Raysuni, 2012, 28pp, $4.50. -

Dr. Jamaal Zarabozo
The Assembly of Muslim Jurists of America 15th Annual Imams' Conference Houston – United States Principles of “Fatwaa-Making”: Easiest Opinions, Madhhab-Combining and Anomalies Dr. Jamaal Zarabozo prolific writer, researcher and speaker "اﻷراء الفقهية في هذا البحث تعبر عن رأي الباحث و ليس بالضرورة عن رأي أمجا" Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA "اﻷراء الفقهية في هذا البحث تعبر عن رأي الباحث و ليس بالضرورة عن رأي أمجا" Fiqh opinions in this research is solely those of its author and do not represent AMJA Principles of “Fatwaa-Making” Dr. Jamaal Zarabozo Contents Introduction ........................................................................................................................................... 4 Definition of Fatwaa ................................................................................................................................... 5 Methodological Challenges Facing the Mufti ............................................................................................. 6 The Mufti and al-Rukhsah al-Shariyyah ...................................................................................... 7 Al-Rukhsah vis-à-vis al-Azeemah .............................................................................................. 7 The Mufti and Making Qiyaas based on a Shareeah Rukhsah ........................................ 8 Summary ............................................................................................................................................ -

Islamic Perspective
Islamic Perspective Journal of the Islamic Studies and Humanities Volume 14, Winter 2015 Center for Sociological Studies In Cooperation with London Academy of Iranian Studies Chairman: Seyed G. Safavi, SOAS University, UK Editor-in-Chief: Seyed Javad Miri, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Iran Book Review Editor: Yoginder Singh Sikand, National Law School, Bangalore, India Managing Editor: Vahideh Sadeghi, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS), Iran Editorial Board Akbar Ahmed, American University, USA Rohit Barot, Bristol University, England Kenneth MacKendrick, University of Manitoba, Canada Faegheh Shirazi, The University of Texas at Austin, USA Judith Blau, University of North Carolina, Chapel Hill, USA Warren S. Goldstein, Center for Critical Research on Religion, USA Oleg V. Kuznetsov, State University of Chita, Siberia, Russia Syed Farid al-Attas, National University of Singapore, Singapore Seyed G. Safavi, SOAS University, UK Richard Foltz, Concordia University, Canada John Herlihy, Petroleum Institute, UAE Margarita Karamihova, Sofia University, Bulgaria Gary Wood, Virginia Polytechnic Institute & State University, USA Seyed Javad Miri, Institute of Humanities and Cultural Studies, Iran Husain Heriyanto, ICAS, Indonesia Eleanor Finnegan, University of Florida, USA Tugrul Keskin, Portland State University, USA Advisory Board George Ritzer, University of Maryland, USA Oliver Leaman, University of Kentucky, USA William I. Robinson, University of California-Santa Barbara, USA Omid Safi, University of North Carolina, USA Charles Butterworth, University of Maryland, College Park, USA Mahmud Keyvanara, Isfahan University of Medical Sciences, Iran Zivar Huseynova, Xezer University, Republic of Azerbayjan Yoginder Singh Sikand, National Law School, Bangalore, India Rachel Woodlock, Monash University, Australia Ejder Okumuş, Eskişehir osmangazi University, Turkey Manuscript Submission Submissions of articles, book reviews and other correspondence should be sent to: Seyed Javad Miri at [email protected]. -

Denouncing Terrorism in the West
Denouncing Terrorism in the West: English Publications of Anti-terrorism Fatwa's as Western Islamic Discourse with an analysis of the ‘Open Letter to Baghdadi’ Arnold Yasin Mol Denouncing Terrorism in the West Arnold Yasin Mol Introduction With the rise of Islamism in the 20th century and the later emergence of Jihadi-Salafi1 groups performing attacks inside and outside Muslim lands, the majority of institutional and famous Muslim scholars have rejected their methods and claims of it being a legitimate Jihad as proscribed by the Sharia.2 When Western forces colonized the majority of Muslim lands in the 19th and early 20th century, many resistance movements (e.g. Mahdi movement in Sudan) were deemed legitimate in their claim of Jihad.3 Later conflicts, as the establishment of Israel, the Russian invasion of Afghanistan, and the American invasion of Iraq, were all seen as attacks on Muslim lands and so fighting in defense of those lands was considered by resistance fighters to be a legitimate cause for Jihad.4 But many Jihadist groups applied tactics and targets that scholars have deemed as unlawful according to Sharia law. The increased use of bombs and Muslim victims and noncombatant non-Muslim victims, many notable Muslim scholars declared public statements and fatwa’s against the Jihadi groups’ methods and claims. In our analysis we will discuss the rise of Islamism and its violent offshoots, and the counter responses given by Islamic scholars through fatwa’s and letter-declarations. Our specific focus will be on the “Letter to Baghdadi”, a letter written against the claims and acts of Abu Bakr al-Baghdadi, the current leader of the self-declared caliphate of the Islamic State 1 For a discussion on these terms, see: Ahmad Moussalli, “Wahhabism, Salafism and Islamism: Who is the enemy?” Conflicts forum, may 4, 2016, accessed juli 6, 2016, http://www.conflictsforum.org/2009/wahhabism- salafism-and-islamism/. -

Author Biography
2 | The Issue of Apostasy in Islam Author Biography Dr. Jonathan Brown is Director of Research at Yaqeen Institute, and an Associate Professor and Chair of Islamic Civilization at Georgetown University. Disclaimer: The views, opinions, findings, and conclusions expressed in these papers and articles are strictly those of the authors. Furthermore, Yaqeen does not endorse any of the personal views of the authors on any platform. Our team is diverse on all fronts, allowing for constant, enriching dialogue that helps us produce high-quality research. Copyright © 2017. Yaqeen Institute for Islamic Research 3 | The Issue of Apostasy in Islam The Shariah consists of some laws that remain the same regardless of changing circumstances and others that change with them. Most of the Shariah is up to individual Muslims to follow in their own lives. Some are for judges to implement in courts. Finally, the third set of laws is for the ruler or political authority to implement based on the best interests of society. The Shariah ruling on Muslims who decide to leave Islam belongs to this third group. Implemented in the past to protect the integrity of the Muslim community, today this important goal can best be reached by Muslim governments using their right to set punishments for apostasy aside. One of the most common accusations leveled against Islam involves the freedom of religion. The problem, according to critics: Islam doesn’t have any. This criticism might strike some as odd since it has been well established that both the religion of Islam and Islamic civilization have shown a level of religious tolerance that would make modern Americans blush.