WALENNAE ISSN (P): 1411-0751 ISSN (E): 2508-121X
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cenozoic Carbonates and Petroleum Systems of South Sulawesi, 2003
© IPA, 2006 - Cenozoic Carbonates and Petroleum Systems of South Sulawesi, 2003 The Cenozoic carbonates and petroleum systems of South Sulawesi IPA Field Excursion October, 2003 Moyra wilsonl and Alit ~scaria' 1. Department of Geological Sciences, Durham University, South Road, Durham, UK, DH13LE 2.Pertamina Exploration Division, Kwarnas Pramuka Building, 1 lth floor J1. Medan Merdeka Timur no.6., Jakarta 101 10, Indonesia Formerly of SE Asia Research Group, University of London, Geology Department, Royal Holloway, Egham, Surrey, TW20 OEX, United Kingdom ITINERARY Day 1: Flight to Ujung Pandang, Sulawesi Introduction to the geology and petroleum systems of South Sulawesi Eocene to middle Miocene shallow water platform carbonates of the Tonasa Formation: Depositional environment, reservoir quality, karstification, caves & waterfalls Eocene clastics of the Malawa Formation: Reservoir and source rocks Structure of South Sulawesi: the Walanae Depression and fault system Drive to, and overnight in Watampone (Bone) - traditional Bugis welcome Day 2: Shallow water buildups of the Tacipi Formation: depositional environment & reservoir quality Volcaniclastic sealing lithologies to the Tacipi Formation Active gas seeps from carbonate buildups of the Tacipi Formation Modem lacustrine environments of Lake Tempe (source rocks of the future) Traditional Bugis meal and overnight in Sengkang Day 3: Structure and petroleum system of western central Sulawesi Distal and proximal synorogenic clastics of the Pliocene Walanae Formation Thrusting and folding in the Latimojong Mountains Depositional environments and active oil seeps from the Eocene-Oligocene Toraja Formation Kete Kesu: a traditional Toraja village and the Oligo-Miocene carbonates of the Makale Formation Day 4: Return to Makassar and Jakarta CONTENTS Itinerary Contents Acknowledgements . -

1 APPENDIX 4 BANGLADESH General Information* Main Rivers
APPENDIX 4 BANGLADESH General Information* Surface area: 143,998 km2 Population (1995): 118,000,000 GDP (1996/1997): US$ 14,000 million Agricultural GDP (1996/1997): US$ 4,508 million Capture Fisheries as % of GDP1: 1.88% Aquaculture as % of GDP1: 2.69% Indicative exchange rate (1999) US$ 1 = Tk 48.5 * FAO World Fisheries Statistics – Country profile, 1999 1 Asia-Pacific Fishery Commission (2005) Main Rivers** Total area Rivers and estuaries 4,047,316 ha Total Length of 700 Rivers 22,155 km The Padma-Ganges and its distribution System Annual catch: 6,489 tonnes (1996-97)3(capture) i) Ganges, Padma 305 km Surface area: 69,481 ha2 Annual catch: 1,641 tonnes2 (1991-92) 50.6 kg/ha2 (1991-92) 0.34% contribution to production2 (1991-92) ii) Mathabhanga 128 km iii) Ichhamati 285 km iv) Bhairab 559 km v) Kumar 443 km vi) Kobadak 280 km vii) Chitra 188 km viii) Nabaganga 210 km ix) Garai, Madhumati 314 km x) Arial Khan 266 km The Meghna and Surma System Surface area: 73,999 ha2 Annual catch 84,737 tonnes (1989-90) 54,244 tonnes2 (1991-92) 1,369.60 kg/ ha2 (1991-92) 11.3% contribution to production2 (1991-92) i) Surma 350 km ii) Kushiyara 110 km 1 Jamuna-Brahmaputra System Surface area: 73,666 ha2 Annual catch: 2,280 tonnes (1989-90) i) Brahmaputra 350 km Annual catch: 505 tonnes (1989-90) 391 tonnes2 (1991-92) 0.081% contribution to production2 (1991-92) ii) Jamuna 531 km Annual catch: 1,775 tonnes (1989-90) 2,253 tonnes2 (1991-92) 30.58 kg/ ha2 (1991-92) 0.46% contribution to production2 (1991-92) Other Rivers in West region i) Nagar 238 km ii) -

Tempe Lake and Various Problems Andi Gusti Tantu1, Nurkaidah2 and Suryawati Salam3
11(4): 014-018(2017) Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X © 2017 www.fisheriessciences.com Review Article Tempe Lake and Various Problems Andi Gusti Tantu1, Nurkaidah2 and Suryawati Salam3 1Fishery Department, Bosowa University, Urip Sumoharjo, Makassar, Indonesia 2Social Department, Bosowa University, Urip Sumoharjo, Makassar, Indonesia 3Agribusiness Department, Bosowa University, Urip Sumoharjo, Makassar, Indonesia Received: 07.09.2017 / Accepted: 16.10.2017 / Published online: 24.10.2017 Abstract: Tempe Lake is a lake located in the western part of Wajo Regency, South Sulawesi, precisely in Tempe Sub- district, Belawa Sub-district, Tanah Sitolo Sub-district, Maniangpajo Sub-District and Sabbangparu Sub-district, about 7 km from Sengkang City to Walanae River. Tempe Lake, which covers an area of about 13,000 hectares, has a species of freshwater fish that is rarely found elsewhere. This is because the lake is located on the slab of australia and asia. This lake is one of tectonic lake in Indonesia. Tempe Lake is supplied with water from the River of Bila and its tributaries Bulu Cenrana. In addition to supplying water, the two rivers also cause siltation due to high erosion upstream. The management of Lake Tempe fishery in Wajo Regency that is environmentally friendly must be based on the applicable law that is the Law of Ministry of Environment and the Fisheries Law. In the management of environmentally friendly fisheries, there are regulations in the Forest Management and Fisheries Law. The regulation is a process that must be done to make the management integrated into ecological and economic aspects, namely sustainable management of lake fisheries. -
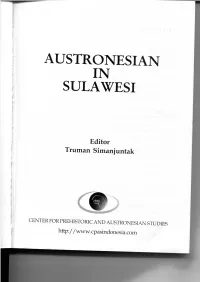
Austronesian in ... Sulawesi
AUSTRONESIAN IN ... SULAWESI Editor Truman Simanjuntak CENTER FOR PREHISTORIC AND AUSTRONESIAN STUDIES http: / / www.cpasindonesia.com Austronesian in Sulawesi Editor: Truman Simanjuntak Cover Design: Levi Simanjuntak Layout: Mirza Ansyor First Published, 2008 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without written permission from the copyright owner Published by: Center For Prehistoric And Austronesian Studies (CPAS) Jin. A. Dahlan IV/20, Kukusan, Depok 16425, Indonesia Telp. 021-708881968; Fax. 021-78881968 Perpustakaan Nasional (Indonesian National Library) Katalog Dalam Terbitan (KDT) Austronesian in Sulawesi CPAS Depok; First Published, 2008; 175 x 230 mm; vi + 269 Halaman ISBN: 978-602-8174-07-7 I. Archaeology II. Title III. Simanjuntak, Truman 3 A CENTURY OF ARCHAEOLOGY IN SULAWESI David Bulbeck During the history of archaeological research on Sulawesi, there have been five major publications on the topic. The first of these was the monograph by two cousins from Basel in Switzerland, Paul Sarasin and Fritz Sarasin, on their excavations undertaken in 1903 on rock shelters at Lamoncong, Bone Regency, South Sulawesi. Sarasin and Sarasin (1905) had been attracted to these sites by reports of a local "cave dwelling" population, the Toala' or "forest people" (not to be confused with the Toala' of Luwu Regency, who speak a language related to Toraja-Sa'dan), and gave us the name "Toalean" with their choice of a name for the assemblages of flaked lithics recovered from the Lamoncong rock shelters. The second and third major publication events for Sulawesi archaeology are due to Robert van Heekeren (1958, 1972). -

Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Irigasi Pada Lahan Sawah: Studi Kasus Di Provinsi Sulawesi Selatan
Jurnal Tanah dan Iklim Vol. 41 No. 2, Desember 2017:135-145 Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air Irigasi pada Lahan Sawah: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan Analysis of Availability and Requirement of Irrigation Water on Rice Field: Case Study in South Sulawesi Nani Heryani, Budi Kartiwa, Adang Hamdani, Budi Rahayu Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Jl. Tentara Pelajar No. 1A, Kampus Penelitian Pertanian Cimanggu, Bogor 16124, Jawa Barat Abstrak: Data dan informasi sumber daya air dalam suatu kawasan dapat digunakan sebagai dasar INFORMAS I ARTIKEL dalam menentukan teknologi pengelolaan air yang tepat sehingga dapat menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya airnya. Teknologi pengelolaan air tersebut perlu diaplikasikan pada skala petani untuk menjawab permasalahan aktual di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Riwayat artikel: Sulawesi Selatan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2015 dengan tujuan untuk mengetahui Diterima: 27 Maret 2017 ketersediaan dan kebutuhan air irigasi pada budidaya padi dan jagung di Provinsi Sulawesi Selatan. Direview: 03 Mei 2017 Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: a) persiapan dan pengumpulan Peta Rupa Disetujui: 02 Januari 2018 Bumi Indonesia (RBI) dan peta sebaran daerah irigasi, b) survei dan pengumpulan data lapang, dan c) analisis data dan pemetaan. Ketersediaan air irigasi diketahui melalui pemodelan hidrologi menggunakan model Integrated Flood Analysis System (IFAS), sedangkan kebutuhan air ditentukan berdasarkan kebutuhan air tanaman padi dan jagung pada satu siklus pertanaman. Hasil penelitian Katakunci: menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 4 golongan ketersediaan irigasi (1-4) dengan -1 -1 IFAS debit air antara <0,3 sampai >0,9 l dt ha , dan 4 indeks kecukupan irigasi A1 sampai A4, yaitu Indeks kecukupan irigasi wilayah yang memiliki IP (indeks pertanaman) 300 dengan pola tanam berturut-turut padi-padi-padi; Pola tanam padi-padi-palawija; padi-palawija-palawija; dan palawija-palawija-palawija. -

Title: Earliest Hominin Occupation of Sulawesi, Indonesia. Authors: Gerrit
Earliest hominin occupation of Sulawesi, Indonesia Author Van den Bergh, Gerrit D, Li, Bo, Brumm, Adam, Gruen, Rainer, Yurnaldi, Dida, Moore, Mark W, Kurniawan, Iwan, Setiawan, Ruly, Aziz, Fachroel, Roberts, Richard G, Suyono, Storey, Michael, Setiabudi, Erick, Morwood, Michael J Published 2016 Journal Title Nature Version Version of Record (VoR) DOI https://doi.org/10.1038/nature16448 Copyright Statement © 2016 Nature Publishing Group. This is the author-manuscript version of this paper. Reproduced in accordance with the copyright policy of the publisher. Please refer to the journal website for access to the definitive, published version. Downloaded from http://hdl.handle.net/10072/142470 Griffith Research Online https://research-repository.griffith.edu.au 1 Title: Earliest hominin occupation of Sulawesi, Indonesia. 2 Authors: Gerrit D. van den Bergh1,2†, Bo Li1, Adam Brumm3,4, Rainer Grün5, Dida 3 Yurnaldi1,6, Mark W. Moore7, Iwan Kurniawan6, Ruly Setiawan6, Fachroel Aziz6, Richard G. 4 Roberts1, Suyono6, Michael Storey8, Erick Setiabudi6, Michael J. Morwood1# 5 6 Author affiliations: 7 1Centre for Archaeological Science, School of Earth & Environmental Sciences, University of 8 Wollongong, Wollongong, NSW 2522, Australia. 9 †E-mail: [email protected] 10 2 Naturalis Biodiversity Center, 2333 CR Leiden, The Netherlands. 11 3Environmental Futures Research Institute, Griffith University, Nathan, QLD 4111, Australia 12 4School of Earth & Environmental Sciences, University of Wollongong, Wollongong, NSW 13 2522, Australia. 14 5Research School of Earth Sciences, The Australian National University, Canberra, ACT 15 0200, Australia. 16 6Geology Museum Bandung, Geological Agency, Jl. Diponegoro 57, Bandung 40122, 17 Indonesia. 18 7Archaeology, School of Humanities, University of New England, Armidale, NSW 2350, 19 Australia. -

Karszt- És Barlangkutatás
KARST REGIONS IN INDONESIA by DR. D BALÁZS Between the Eurasian and Australian continents stretches a vast archipelago on both sides of the Equator. Composed of more than 20,000 islands, the East-Indian Archipelago* is one of the most diversified, continually moving and changing, parts of our Globe. This is due to its being a point of junction of three huge tectonic units. From the north, the southeast shield of the Asiatic Massif (Southeast India and the inundated Sanda Shelf as well as the northeast fiatland of Sumatra and the southwest one-third of Kalimantan) wedges into the heart of the archipelago; on the south and west the rem nants of the Gondwana Massif — the Indian Shield, the bottom of the Indian Ocean, the Australian continent, and the associated Sahul Shelf — form an arched, rigid wall; on the east the abyssal craton of the Pacific Ocean borders the region. (Fig. 1) The three stable tectonic units are hemmed in by three huge sedimentary troughs: a) between the Eurasiatic and the Gondwana Massifs there is the Alpi ne-Himalayan- Sunda orogenic belt which, beyond Arakan Joma, Burma, is split up and submerged, its emergent portions being the Andaman islands, Sumatra, Java, and the Little Sunda islands ; h) the circum-Pacific orogenic belt, whose Asiatic arch, crossing the Philippines, entwines Kalimantan and the northern half of Sulawesi; *The naming of the archipelago flanked by Southeast Asia and Australia has been a vexed question for a long time. If the insular world, geographically belonging together (includ ing. beyond the political borders of present-day Indonesia, the island groups of Andaman and Nicobar, the Christmas island, northern Kalimantan, the Philippines, and the entire complex of Irian (New Guinea) and the surrounding islands, covering a total area of 2 832 000 km2), is considered, perhaps terms such as the “Australe-Asiatic Archipelago*’ proposed by S a r Qasin or Z e u n e r's “Indo-Australian Archipelago" would be the most apropriate. -

Directors: Ir. Widagdo, Dipl.HE Hisaya SAWANO Authors
Directors: Ir. Widagdo, Dipl.HE Hisaya SAWANO Authors: Ir. Sarwono Sukardi, Dipl.HE Ir. Bambang Warsito, Dipl.HE Ir. Hananto Kisworo, Dipl.HE Sukiyoto, ME Publisher: Directorate General of Water Resources Yayasan Air Adhi Eka i Japan International Cooperation Agency ii River Management in Indonesia English Edition English edition of this book is a translation from the book : “Pengelolaan Sungai di Indonesia” January 2013 ISBN 978-979-25-64-62-4 Director General of Water Resources Foreword Water, as a renewable resource, is a gift from God for all mankind. Water is a necessity of life for creatures in this world. No water, no life. The existence of water, other than according to the hydrological cycle, at a particular place, at a particular time, and in particular quality as well as quantity is greatly influenced by a variety of natural phenomena and also by human behavior. Properly managed water and its resources will provide sustainable benefits for life. However, on the other hand, water can also lead to disasters, when it is not managed wisely. Therefore, it is highly necessary to conduct comprehensive and integrated water resources management efforts, or widely known as “Integrated Water Resources Management”. In the same way, river management efforts as part of the river basin integrated water resources management, include efforts on river utilization, development, protection, conservation and control, in an integrated river basin with cross-jurisdiction, cross-regional and cross- sectoral approach. This book outlines how water resources development and management in several river basins are carried out from time to time according to the existing situations and conditions, Besides, it covers various challenges and obstacles faced by the policy makers and the implementers in the field, The existing sets of laws and regulations and the various uses and benefits are also discused. -

Colloquium2018 Between Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) & Universitas Negeri Makassar, Indonesia
PROCEEDINGS OF THE Colloquium2018 between Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) & Universitas Negeri Makassar, Indonesia Cetakan Pertama/ First Printing 2018 Hak Cipta Universiti Teknologi Malaysia/ Copyright Universiti Teknologi Malaysia, 2018 All right reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Faculty of Education UTM Perpustakaan Negara Malaysia Cataloguing-in-Publication Data Abdul Halim Abdullah, 1983–. 2018 PROCEEDINGS OF THE EDUCATION RESEARCH COLLOQUIUM BETWEEN FACULTY OF EDUCATION, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) & UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, INDONESIA / Abdul Halim Abdullah et al. ISBN 978-967-2171-12-6 Editor: Abdul Halim Abdullah et al. Cover Design: Fadhilah Othman Published in Malaysia by Faculty of Education UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 81310 UTM Johor bahru, JOHOR, MALAYSIA http://educ.utm.my/ PROCEEDINGS OF THE BETWEEN FACULTY OF EDUCATION, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) & UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR, INDONESIA Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia Foreword by the Dean of Faculty of Education, UTM Assalamualaikum w.b.t and Good Day Ladies and gentlemen, It is my pleasure to welcome you to the Education Research Colloquium between Faculty of Education, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) & Universitas Negeri Makassar (UNM), Indonesia. This colloquium is a platform for both institutions to sustain a harmonious and stable global society and to promote international cooperation and exchange. As we know, UTM participated in a wide variety of collaborative relationships with universities, institutions and individuals in many countries. I am confident that through this colloquium, relationship and friendship between FP UTM and UNM will become stronger. -

Review of River Fisheries Valuation in Tropical Asia
Review of river fisheries valuation in tropical Asia Item Type book_section Authors Norman-Lpez, A.; Innes, J.P. Publisher WorldFish Center Download date 01/10/2021 16:21:42 Link to Item http://hdl.handle.net/1834/19131 CHAPTER 4 Review of River Fisheries Valuation in Tropical Asia Ana Norman-Lpez and James P. Innes CEMARE (Centre for the Economics & Management of Aquatic Resources) University of Portsmouth Locksway Road Portsmouth PO4 8JF Hampshire United Kingdom E-mails: [email protected] [email protected] 147 148 TROPICAL RIVER FISHERIES VALUATION: BACKGROUND PAPERS TO A GLOBAL SYNTHESIS Contents - Chapter 4 Abstract 150 Acknowledgements 150 1. Introduction 151 2. Conceptual and Measurement Issues 151 Řǯŗȱȱ ȱ 151 ŘǯŘȱȱ ȱȱȱȱȱ 152 2.2.1 Reasons for the Economic Valuation of Natural Resources 152 2.2.2 Reasoning against the Economic Valuation of Natural Resources 153 Řǯřȱȱ ȱȱȱǻǼ 154 ŘǯŚȱȱ ȱȱȱ 155 Řǯśȱȱ ȱȱȱ 155 2.5.1 Stated Preference Methods – estimation of people’s preferences based on direct questioning 155 (i) Contingent Valuation Methodology (CVM) 155 (ii) Discrete Choice Modeling (Conjoint Analysis (CA)) 156 2.5.2 Revealed Preference Methods – estimation of people’s preferences based on observed market behaviour 156 (i) Travel Cost Method (TCM) 156 (ii) Hedonic Pricing Method 156 (iii) Production Function Analysis 156 (iv) Sustainable Livelihood Analysis (SLA) 157 ȱ ŘǯŜȱȱ ȱȱȱȱ 158 3. Inland Fisheries Production 159 4. Economic Valuation Case Studies 160 ȱ Śǯŗȱȱ ȱȱȱ¢ 160 4.1.1 Water Use in the Mekong River Basin 160 4.1.2 -

V. Sulawesi - Buton
BIBLIOGRAPHY OF THE GEOLOGY OF INDONESIA B G O I AND SURROUNDING AREAS Edition 7.0, July 2018 J.T. VAN GORSEL V. SULAWESI - BUTON www.vangorselslist.com V. SULAWESI- BUTON V. SULAWESI- BUTON ................................................................................................................................... 1 V.1. Sulawesi............................................................................................................................................. 17 V.2. Buton, Tukang Besi .......................................................................................................................... 130 This chapter V of Bibliography 7.0 contains 140 pages with 970 titles on the Sulawesi region, subdivided in two sub-chapters, Sulawesi and Buton. For discussions and papers on surrounding areas see also: - Makassar Straits: in Chapter IV (Borneo); - Celebes Sea: in Chapter IXa (Circum-Indonesia/ Asia); - Banggai-Sula islands: in Chapter VII (North Moluccas). V.1. Sulawesi Sub-chapter V.1 contains 893 papers on the geology of the Sulawesi region. Today Sulawesi is a triple junction of three major tectonic plates, Eurasia to the west, Pacific to the NE and Australia- New Guinea- Indian Ocean to the South and East. Its peculiar K-shape reflects a Cretaceous- Recent history with multiple episodes of subduction, collision and dismemberment of the active margin by hyperextension. Despite widespread volcanism on Sulawesi during most of Cenozoic time, there is little or no volcanic activity today (except Una Una volcano -

Walanae Formation and Walanae Terraces in the Stratigraphy of South Sulawesi (Celebes, Indonesia)
21 Walanae Formation and Walanae Terraces in the Stratigraphy of South Sulawesi (Celebes, Indonesia) by Gert-]an Bartstra, Groningen The river Walanae flows through the south-westem arm of the island of Sulawesi (Celebes, Indonesia; see fig. 1). The terraces of this river have acquired a certain fame, both for the remains of fossil Pleisto cene vertebrates (the Archidiskodon-Celebochoerus fauna; first publications: Hooijer, 1948a, band c), and for stone artefacts (the Tjabenge industry '~ ); first announcements: Van Heekeren, 1949a, band c). lt is always maintained in the Iiterature that fauna and industry are probably contemporaneous (e. g. Van Heekeren, 1972, p. 69 and 1975, p. 48; Hooijer, 1973, p. 12; Soejono, 1975, p. 95). However, I very much doubt whether fossils and artefacts are originally from the same deposit. I first had these doubts when taking part in a joint Dutch-Indonesian expedition to South Sulawesi in 1970 (financed by the Ne therlands Foundation for the Advancement of Tropical Research: WOTRO). Apart from the description of some specimens from the newly-found fossil material (Hooijer, 1972), th.e results of the expedition have not yet been published. But the Ieaders of the team in Sulawesi, Dr. H. R. van Heekeren and Dr. R. P. Soejono, have as far as I know, never basically changed their ideas about the contemporaneity of artefacts and fossils. I will give here the reasons for my doubts and will do this in the form of a survey of the stratigraphy of South Sulawesi. Thanks are due to Dr. D. A. Hooijer and Dr. H. J.