Mengadili Korban Praktek Pembenaran Terhadap Kekerasan Negara
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History
Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History Emile Schwidder & Eef Vermeij (eds) Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History Emile Schwidder Eef Vermeij (eds) Guide to the Asian Collections at the International Institute of Social History Stichting beheer IISG Amsterdam 2012 2012 Stichting beheer IISG, Amsterdam. Creative Commons License: The texts in this guide are licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 license. This means, everyone is free to use, share, or remix the pages so licensed, under certain conditions. The conditions are: you must attribute the International Institute of Social History for the used material and mention the source url. You may not use it for commercial purposes. Exceptions: All audiovisual material. Use is subjected to copyright law. Typesetting: Eef Vermeij All photos & illustrations from the Collections of IISH. Photos on front/backcover, page 6, 20, 94, 120, 92, 139, 185 by Eef Vermeij. Coverphoto: Informal labour in the streets of Bangkok (2011). Contents Introduction 7 Survey of the Asian archives and collections at the IISH 1. Persons 19 2. Organizations 93 3. Documentation Collections 171 4. Image and Sound Section 177 Index 203 Office of the Socialist Party (Lahore, Pakistan) GUIDE TO THE ASIAN COLLECTIONS AT THE IISH / 7 Introduction Which Asian collections are at the International Institute of Social History (IISH) in Amsterdam? This guide offers a preliminary answer to that question. It presents a rough survey of all collections with a substantial Asian interest and aims to direct researchers toward historical material on Asia, both in ostensibly Asian collections and in many others. -
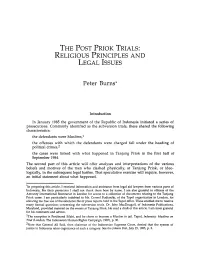
R Eligious P Rinciples and L Egal Issues Peter Burns
T h e P ost P rio k T r ia l s : R el ig io u s P r in c ip l e s a n d L e g a l Issues Peter Burns* Introduction In January 1985 the government of the Republic of Indonesia initiated a series of prosecutions. Commonly identified as the subversion trials, these shared the following characteristics: the defendants were Muslims,1 the offenses with which the defendants were charged fall under the heading of political crimes,2 the cases were linked with what happened in Tanjung Priok in the first half of September 1984. The second part of this article will offer analyses and interpretations of the various beliefs and motives of the men who clashed physically, at Tanjung Priok, or ideo logically, in the subsequent legal battles. That speculative exercise will require, however, an initial statement about what happened. *In preparing this article, I received information and assistance from legal aid lawyers from various parts of Indonesia. For their protection I shall not thank them here by name. I am also grateful to officers of the Amnesty International Secretariat in London for access to a collection of documents relating to the Tanjung Priok cases. I am particularly indebted to Ms. Carmel Budiardjo, of the Tapol organization in London, for allowing me free use of the extensive file of press reports held in the Tapol office. These enabled me to resolve many factual questions concerning the subversion trials. Dr. John MacDougall, of Indonesia Publications, Maryland, provided material on the events at Tanjung Priok. -

Indonesia and East Timor
224 Amnesty International ReporI 1986 Naxalites were killed and a survivor stated that they had been sur rounded by police in plain clothes, stripped naked, stood in a row with their hands behind their backs and shot. Although the Supreme Court had ruled that the death penalty should be imposed only in the "rarest of rare" cases,dozens of people were sentenced to death in 1985 as in previous years. In December Amnesty International wrote to the President of India expressing concern that the Rajasthan High Coun had sentenced a man and a woman to be executed in public. Amnesty International welcomed the Supreme Coun's ruling of 13 December that public executions should not be carried out, which the Attorney General had stated were "cruel and brutal". It appealed for commutation of the death sentence for these and other prisoners sentenced to death. The organization did not have information regarding the number of executions actually carried out. Indonesia and East Timor Over 100 Muslim activists, many of them possible prisoners of con science, were tried and convicted during 1985 for offences ranging from subversion to spreading false .....___ -'==;,:"...... "-'Ll---l information. Repons that suspec- ted criminals and alleged governmem opponents had been extra judicially executed continued to be received . Five judicial executions were carried out, including the execution by firing-squad of four men alleged to have held high-ranking positions in the banned Partai Komunis Indonesia (PKI), Indonesian Communist Pany, all of whom had been in detention for over 16 years. Amnesty International remained concerned about reponsof torture and ill-treatment by the Indonesian security forces of prisoners, many of whom were suspected of supporting independence movements in lrian Jaya and East Timor. -

Kisah Tiga Jenderal Dalam Pusaran Peristiwa 11-Maret
KISAH TIGA JENDERAL DALAM PUSARAN PERISTIWA 11‐MARET‐1966 Bagian (1) “Kenapa menghadap Soeharto lebih dulu dan bukan Soekarno ? “Saya pertama‐tama adalah seorang anggota TNI. Karena Men Pangad gugur, maka yang menjabat sebagai perwira paling senior tentu adalah Panglima Kostrad. Saya ikut standard operation procedure itu”, demikian alasan Jenderal M. Jusuf. Tapi terlepas dari itu, Jusuf memang dikenal sebagai seorang dengan ‘intuisi’ tajam. 2014 Dan tentunya, juga punya kemampuan yang tajam dalam analisa June dan pembacaan situasi, dan karenanya memiliki kemampuan 21 melakukan antisipasi yang akurat, sebagaimana yang telah dibuktikannya dalam berbagai pengalamannya. Kali ini, kembali ia Saturday, bertindak akurat”. saved: Last TIGA JENDERAL yang berperan dalam pusaran peristiwa lahirnya Surat Perintah 11 Maret Kb) 1966 –Super Semar– muncul dalam proses perubahan kekuasaan dari latar belakang situasi (89 yang khas dan dengan cara yang khas pula. Melalui celah peluang yang juga khas, dalam suatu wilayah yang abu‐abu. Mereka berasal dari latar belakang berbeda, jalan pikiran dan 1966.docx ‐ karakter yang berbeda pula. Jenderal yang pertama adalah Mayor Jenderal Basuki Rachmat, dari Divisi Brawijaya Jawa Timur dan menjadi panglimanya saat itu. Berikutnya, yang kedua, Maret ‐ 11 Brigadir Jenderal Muhammad Jusuf, dari Divisi Hasanuddin Sulawesi Selatan dan pernah menjadi Panglima Kodam daerah kelahirannya itu sebelum menjabat sebagai menteri Peristiwa Perindustrian Ringan. Terakhir, yang ketiga, Brigadir Jenderal Amirmahmud, kelahiran Jawa Barat dan ketika itu menjadi Panglima Kodam Jaya. Pusaran Mereka semua mempunyai posisi khusus, terkait dengan Soekarno, dan kerapkali Dalam digolongkan sebagai de beste zonen van Soekarno, karena kedekatan mereka dengan tokoh puncak kekuasaan itu. Dan adalah karena kedekatan itu, tak terlalu sulit bagi mereka untuk Jenderal bisa bertemu Soekarno di Istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966. -

Power Politics and the Indonesian Military
Downloaded by [University of Defence] at 20:05 09 May 2016 Power Politics and the Indonesian Military Throughout the post-war history of Indonesia, the military has played a key role in the politics of the country and in imposing unity on a fragmentary state. The collapse of the authoritarian New Order government of President Suharto weakened the state, and the armed forces briefly lost their grip on control of the archipelago. Under President Megawati, however, the military has again begun to assert itself, and to reimpose its heavy hand on control of the state, most notably in the fracturing outer provinces. This book, based on extensive original research, examines the role of the military in Indonesian politics. It looks at the role of the military histori- cally, examines the different ways in which it is involved in politics, and considers how the role of the military might develop in what is still an uncertain future. Damien Kingsbury is Head of Philosophical, International and Political Studies and Senior Lecturer in International Development at Deakin University, Victoria, Australia. He is the author or editor of several books, including The Politics of Indonesia (Second Edition, 2002), South-East Asia: A Political Profile (2001) and Indonesia: The Uncertain Transition (2001). His main area of work is in political development, in particular in assertions of self-determination. Downloaded by [University of Defence] at 20:05 09 May 2016 Downloaded by [University of Defence] at 20:05 09 May 2016 Power Politics and the Indonesian Military Damien Kingsbury Downloaded by [University of Defence] at 20:05 09 May 2016 First published 2003 by RoutledgeCurzon 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Simultaneously published in the USA and Canada by RoutledgeCurzon 29 West 35th Street, New York, NY 10001 This edition published in the Taylor and Francis e-Library, 2005. -

Pepres, Kepres, Inpres Tahun 1946 Sd 2010
DAFTAR PERATURAN PRESIDEN, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN INSTRUKSI PRESIDEN DARI TAHUN 1946 S.D. TAHUN 2010 NOMOR/TGL NO. TENTANG SUMBER STATUS PERATURAN TAHUN 1946 PERPRES 1 No. 1 Tahun 1946 Pemberian Ampunan Kepada Orang-orang HPPN 1946 8 Agustus 1946 Hukuman. Hal.: 239 - 240 2 No. 2 Tahun 1946 Pemberian Tunjangan kepada Bekas Menteri HPPN 1946 Diubah dg Perpres 16 Agustus 1946 Negara. Hal.: 241 - 243 No.4 Th.1946 3 No. 3 Tahun 1946 Perhubungan Dewan Pertahanan Daerah HPPN 1946 28 Oktober 1946 Dengan Jawatan-Jawatan Pemerintahan Sipil. Hal.: 244 4 No. 4 Tahun 1946 Perubahan dan tambahan dalam Peraturan HPPN 1946 30 Nopember 1946 Presiden No.2 Th.1946 tentang Pemberian Hal.: 245 - 246 Tunjangan kepada Bekas Menteri Negara 5 No. 5 Tahun 1946 Penetapan gaji beberapa Pegawai Tinggi. HPPN 1946 Diubah dg Perpres 28 Desember 1946 Hal.: 247 - 248 No.1 Th.1947 Dicabut dg Perpres No.2 Th.1949 6 No. 6 Tahun 1946 Penyempurnaan Susunan Komite Nasional HPPN 1946 29 Desember 1946 Pusat. Hal.: 249 - 250 TAHUN 1947 PERPRES 1 No. 1 Tahun 1947 Mengubah dan Menambahi Peraturan Presiden HPPN 1947 Dicabut dg Perpres 17 September 1947 No.5 Tahun 1946 dari hal penetapan gaji Hal.: 326 - 327 No.2 Th.1949 beberapa Pegawai Tinggi. PENPRES 1 No.01 Tahun 1947 Membubarkan Panitia Perancang Peraturan HPPN 1947 Gaji Pegawai Negeri. Hal.: - 2 No.02 Tahun 1947 Pengesahan Anggota-anggota Komite Nasional HPPN 1947 Pusat Yang Menjadi Anggota Badan Pekerja. Hal.: - 3 No.03 Tahun 1947 Pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi. HPPN 1947 Hal.: - 4 No.04 Tahun 1947 Pembubaran Delegasi Lama Dan HPPN 1947 Pembentukan Delegasi Baru Yang Di Ketuai Hal.: - Oleh Sutan Sjahrir. -

Statistical Tables TABLE 4.1 ASEAN: Area and Population 1978
Statistical Tables TABLE 4.1 ASEAN: Area and Population 1978 Area Population Population Average population Population (mid-1978) density growth (%) projected to ('000 sq. km.) millions (per sq. km.) 1960-70 1970-78 AD2000 Indonesia 2,027 136.0 67 2.2 1.8 204 Malaysia 330 13.3 40 2.9 2.7 20 Philippines 300 45.6 152 3;0 2.7 75 Singapore 0.6 2.3 3,833 2.4 1.5 3 Thailand 514 44.5 86 3.0 2.7 68 ASEAN 3,172 241.7 176 370 ~ ~ Source: World Bank, World Development Indicators - Annex to World Development Report, 1979 (Washington, ~ DC,1980). .... ~r TABLE 4.2 ASEAN: Gross National Product and Food Production - ~ 1978 ~ ..,~ GNP per capita 1978 Average annual inflation rates Index ollood Average annual production US$ growth,1960-78 1960-70 1970-78 per capita % % % Av.1976-8 Indonesia 360 4.1 20.0 100 Malaysia 1,090 3.9 -0.3 7.2 110 Philippines 490 2.6 5.8 13.4 115 Singapore 3,290 7.4 1.1 6.1 112 N Thailand 510 4.6 1.9 9.1 122 VI -....l Source: World Bank, World Development Indicators - Annex to World Development Report, 1979 (Washington, DC, August 1980). N VI TABLE 4.3 ASEAN: Gross Domestic Product 00 1978 (A) Percentage Growth Rates of GDP by Sector GDP Agriculture Industry Manufacturing Services 1960-70 1970-78 1960-70 1970-78 1960-70 1970-78 1960-70 1970-78 1960-70 1970-78 Indonesia 3.5 7.8 2.5 4.0 5.0 11.2 3.3 12.4 8.0 8.7 Malaysia 6.5 7.8 5.0 9.6 12.3 8.4 ~ Philippines 5.1 6.3 4.3 4.9 6.0 8.6 6.7 6.8 5.2 5.4 ~ Singapore 8.8 8.5 5.0 1.5 12.6 8.5 13.0 9.2 7.7 8.6 ~ Thailand 8.2 7.6 5.5 5.6 11.6 10.2 11.0 11.5 9.0 7.4 ~ := ~ (B) Percentage Distribution of GDP by Sec tor ~. -
ASA 21/03/97 Indonesia: the Anti-Subversion
amnesty international INDONESIA The Anti-subversion Law: A Briefing Introduction "[T]he Anti-subversion Law can be used to punish people whose ideas are different from those of the government. It allows prosecutors and judges to act as if they can read the accused’s mind".1 In Indonesia subversion is punishable by death, yet those accused of this crime are denied the most basic rights - including the right to a fair trial - which would provide them with the opportunity to defend themselves against the charge. Most of those convicted of subversion in Indonesia have done nothing more than peacefully express views which differ from those of the government authorities. In a state where national stability, security and order are among the key "national goals" such peaceful opposition - perceived or real - is considered to threaten the stability of the state and its ideology and, as such, is deemed subversive. The legislation which makes the criminalisation of peaceful dissent possible is the 1963 Anti- subversion Law. This law has been employed extensively by the Indonesian Government to silence dissent by detaining without trial hundreds of thousands of alleged political opponents during the past 32 years. 1 Indonesia’s National Commission for Human Rights (Komnas HAM) on the Anti-subversion Law. Jakarta Post, 9 April 1996. 2 Indonesia’s Anti-subversion Law Hundreds of others charged with subversion have been put through unfair trials and sentenced to long terms of imprisonment or even put to death. In recent years, faced with strong criticism of the law, including from Indonesia’s National Commission on Human Rights (Komisi Nasional Hak Azasi Manusia - Komnas HAM), its use by the authorities had declined. -
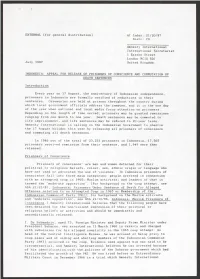
July 1987 AI Index
EXTERNAL (for general distribution) AI Index: 21/20/87 Distr: CO Amnesty International International Secretariat 1 Easton Street London WC1X 8DJ July 1987 United Kingdom INDONESIA : APPEAL FOR RELEASE OF PRISONERS OF CONSCIENCE AND COMMUTATION OF DEATH SENTENCES Introduction Eve r y year on 17 August, the anniversary of Indonesian independence, prisoners in Indonesia are formally notified of reductions in their sentences . Ceremonies are held at prisons throughout the country during which local gov ernment officials address the inmates, and it is the one day of the year when national and local media focus attention on prisoners. Depending on the length of time served, prisoners may be granted remissions ranging from one month to one year. Death sentences ma y be commuted to life imprisonment, and life sentences ma y be reduced to 20-year terms . Amnesty International is calling on the Indonesian Government to observe the 17 August holiday this year by releasing all prisoners of conscience and commuting all death sentences. In 1986 out of the total of 23,233 prisoners in Indonesia, 17,565 prisoners received remission from their sentence, and 1,949 were then released. Prisoners of Conscience " Prisoners of consc ience " are men and women detained for their political or religious beliefs , colour, sex, ethnic origin or language who have not used or advocated the use of v iolence. In Indonesia prisoners of conscience fall into three main categories: people arrested in connection with an attemp ted coup in 1965; Muslim activists; and leaders of what is termed the "moderate opposition" . (For background on the coup attempt , see ASA 21/ 23/ 85, Indonesia: Prisoners Under Sentence of Death for Alleged Offences relating to an Attempted Coup in 1965 or Membership of the Indonesian Commu nist Party (PKI); for background on the Muslim activists and "moderate opposition", see ASA 21 / 10/ 86, Indonesia : Muslim Prisoners of Conscience. -

Kemal Idris, Kisah Tiga Jenderal Idealis
KEMAL IDRIS, KISAH TIGA JENDERAL IDEALIS “Kalau ada segelintir perwira yang tidak berubah sikap, maka itu tak lain adalah tiga jenderal idealis Sarwo Edhie Wibowo, HR Dharsono dan Kemal Idris. Namun perlahan tapi pasti satu persatu mereka pun disingkirkan dari kekuasaan”. SELAIN Jenderal Soeharto, ada tiga jenderal yang tak bisa dilepaskan dari catatan sejarah pergolakan dan perubahan Indonesia pada tiga bulan terakhir tahun 1965, hingga 1966‐ 1967. Peran mereka mewarnai secara khas dan banyak menentukan proses perubahan negara di masa transisi kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto. Tentu saja ada sebarisan jenderal dan perwira bersama Jenderal Soeharto dalam membangun rezim kekuasaan baru menggantikan kekuasaan Soekarno. Namun hanya sedikit dari mereka yang 2014 tetap berpegang kepada idealisme semula yang menjadi dasar kenapa rezim yang lama di June bawah Soekarno harus diganti, dan bahwa kekuasaan baru yang akan ditegakkan adalah 21 sebuah kekuasaan demokratis sebagai koreksi terhadap rezim Nasakom Soekarno. Saturday, Paling menonjol dari barisan perwira idealis ini adalah tiga jenderal, yakni Sarwo Edhie saved: Wibowo, Hartono Rekso Dharsono dan Achmad Kemal Idris, yang ketiganya di akhir karir Last mereka ‘hanya’ mencapai pangkat tertinggi sebagai Letnan Jenderal. Ketika masih Kb), berpangkat Kolonel pada 1 Oktober 1965, Sarwo Edhie adalah bagaikan anak panah yang (56 muncul dari dari balik tabir blessing in disguise dalam satu momentum sejarah bagi Jenderal Soeharto. Mayor Jenderal Hartono Rekso Dharsono, yang pada bulan Juli 1966 naik setingkat dari Kepala Staf menggantikan Mayjen Ibrahim Adjie sebagai Panglima Siliwangi, kemudian Idealis.docx muncul sebagai jenderal yang menjadi ujung tombak upaya pembaharuan struktur politik Jenderal Indonesia hingga setidaknya pada tahun 1969. -

Statistik Politik 2014 Iii Iv Statistik Politik 2014 Daftar Isi
Kata Pengantar Kondisi politik Tahun 2014 sangat dinamis, menyedot hampir seluruh energi politik nasional. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden menjadi gravitasi dan puncak dari seluruh persiapan partai-partai politik yang sudah mulai terlihat sebelum tahun Pemilu. Sekalipun demikian kita bersyukur kedua kegiatan itu berlangsung dengan lancar dan tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat. Menjelang dan sesudah penyelenggaraan Pemilu, banyak data politik yang menarik didokumentasikan secara statistik. Bukan hanya terkait hasil, namun berbagai data dalam tahapan proses Pemilu merupakan data berharga. Informasi semacam ini dapat membantu kita mengidentifikasi fenomena politik yang sedang berkembang, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan program pembangunan bidang politik pada masa mendatang. Secara konsisten Publikasi Statistik Politik terus memberikan perhatian pada representasi perempuan di ruang politik. Sebagai contoh dalam setiap kali terbit, publikasi ini senantiasa menyajikan rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepala desa, anggota DPR/DPRD dan kepengurusan partai politik terpilah jenis kelamin. Pada tahun ini disajikan pula rekapitulasi calon legislatif pada pemilu 2014. Pada Tahun 2014 dari 43 daerah yang seyogyanya melaksanakan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) hampir semua menunda pelaksanaannya, kecuali beberapa daerah seperti Lampung. Penundaan ini didasarkan pada imbauan Menteri Dalam Negeri, mengingat pada tahun 2014 secara nasional dilaksanakan dua kali pemilu, pemilu legislatif dan pemilu pasangan presiden dan wakil presiden. Karena itu data tentang Pilkada tahun 2014 tidak banyak mengalami perubahan. Publikasi Statistik Politik ini diharapkan dapat menjadi sumber data untuk melakukan monitoring, evaluasi maupun analisis perkembangan politik terkini. Akhirnya kami berharap buku ini bermanfaat bagi penyusunan program pembangunan politik pada masa mendatang, sehingga politik Indonesia menjadi semakin matang dan menyejahterakan. -

Political Statistics 2015
http://www.bps.go.id http://www.bps.go.id STATISTIK POLITIK 2015 ISSN : 2303.2448 Nomor Publikasi : 04330.1503 Katalog BPS : 4601003 Ukuran Buku : 16 x 24 cm Jumlah Halaman : xvi + 175 Naskah: Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Gambar Kulit: Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan Diterbitkan Oleh: Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia http://www.bps.go.id ii Statistik Politik 2015 Ringkasan Eksekutif Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik. Statistik Politik Tahun 2015. Demokratisasi Indonesia ditandai dengan berbagai perubahan sistem dan budaya politik. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) power yang sebelumnya tersentral pada Presiden, yang dilakukan pada dua level, vertikal dan horizontal. Pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan tahun 2015 telah terdapat 34 provinsi, 410 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet. Dengan terdistribusinya kekuasaan maka Presiden dan eksekutif memungkinkan untuk dikontrol dalam mengelola pemerintahan. Selain dari lembaga Negara, kontrol dari masyarakat, organisasi masyarakat, hingga pers juga semakin leluasa. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, menunjukkan kepedulian dan pemahaman yang baik terhadap hak-hak masyarakat dalam politik. Pemerintah juga dituntut netral dalam Pemilu, yang merupakan mekanisme paling akuntabel untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan politik secara damai. Pemilu Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia, dilakukan dengan sistem daftar terbuka. Artinya, setiap pemilih bisa memilih figure calon legislatif yang diajukanhttp://www.bps.go.id oleh partai politik.