SNP Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Draf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
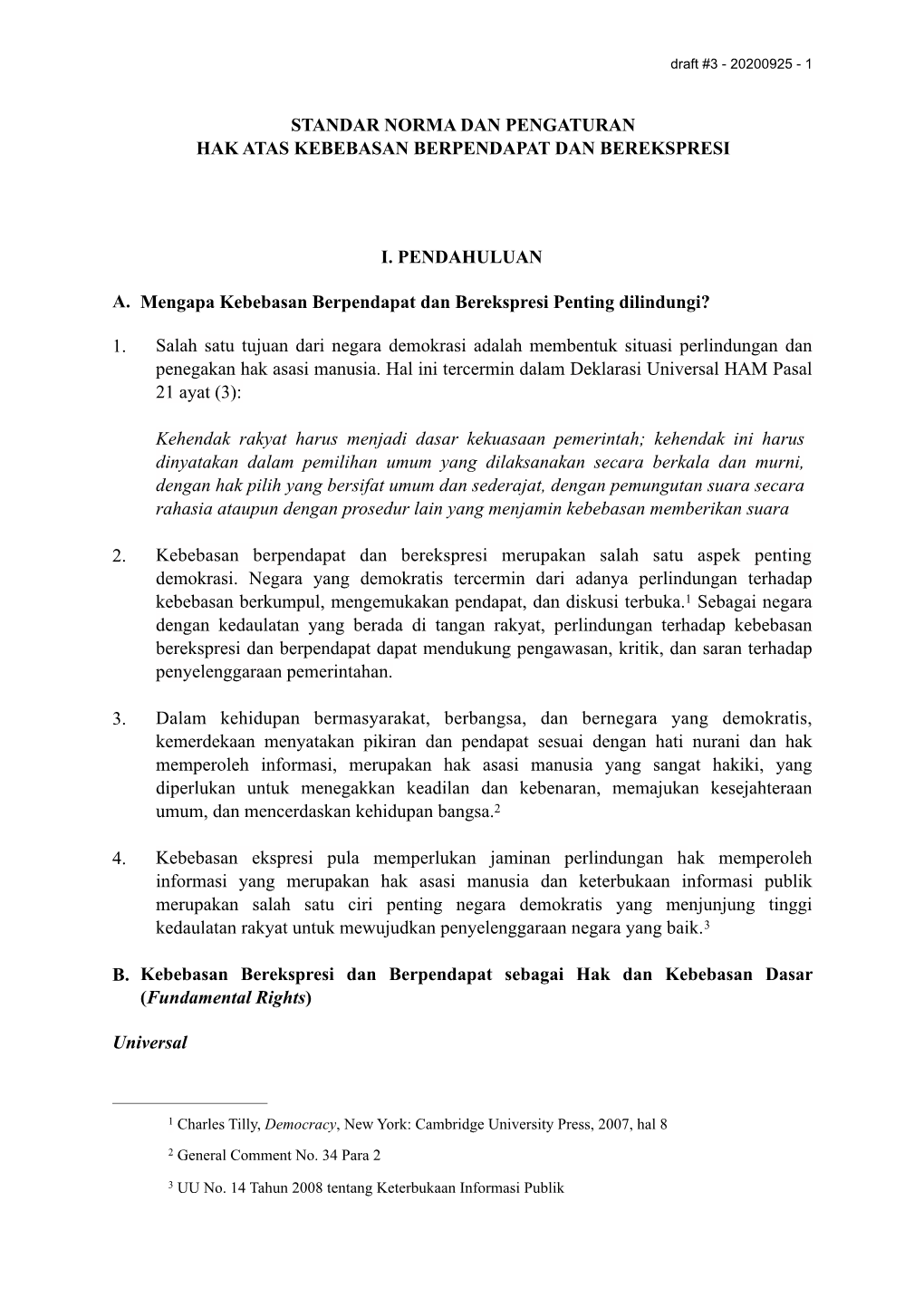
Load more
Recommended publications
-

Amnesty International Report 2016/17 Amnesty International
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2016/17 AMNESTY INTERNATIONAL Amnesty International is a global movement of more than 7 million people who campaign for a world where human rights are enjoyed by all. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations. First published in 2017 by Except where otherwise noted, This report documents Amnesty Amnesty International Ltd content in this document is International’s work and Peter Benenson House, licensed under a Creative concerns through 2016. 1, Easton Street, Commons (attribution, non- The absence of an entry in this London WC1X 0DW commercial, no derivatives, report on a particular country or United Kingdom international 4.0) licence. territory does not imply that no https://creativecommons.org/ © Amnesty International 2017 human rights violations of licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode concern to Amnesty International Index: POL 10/4800/2017 For more information please visit have taken place there during ISBN: 978-0-86210-496-2 the permissions page on our the year. Nor is the length of a website: www.amnesty.org country entry any basis for a A catalogue record for this book comparison of the extent and is available from the British amnesty.org depth of Amnesty International’s Library. concerns in a country. Original language: English ii Amnesty International -

Minutes to Meeting 31St October 2012
Aylesbury Amnesty International Group Group Meeting 31st October 2012 7.30pm Friends Meeting House, 9 Rickfords Hill, Aylesbury, HP20 2RT Present Carol Tarrant Jim Edwards Bob Corn Annelies Varsey Jim Cobley Frances Booth David Barnard Gwyn Jenkins Apologies: Bronwen Lee, Hugh Cousins, Katherine Danflous, Grace Perrett Carol welcomed everyone to the meeting – she spoke briefly of the impressive demonstration in Whitehall, London earlier in the day – which she, David, Katherine, Grace, Bob and Jean Wyatt had attended with the almost 100 strong contingent; Amnesty International had joined with other NGO’s (Tapol, Survival International, Down to Earth, etc.) in forming a protest against the Human Rights record of Indonesia, as the Indonesian President was visiting Downing Street during his three day state visit to the UK. 1.0 Previous Minutes – Approved. 2.0 Johan Teterissa: Jim Cobley reported that he previously written two letters before taking up the case, and was now in discussion with Indonesia Country Coordinator Paul Hainsworth, and had written to David Lidington MP, asking him to ask the Foreign Secretary to take the case up with the Indonesian President during his visit. Jim is unclear as to which gaol Johan is currently incarcerated in (as he has been moved recently), the meeting suggesting that he write to Champa Patel, Head of Activism, AIUK, to Laura Haigh, officer at the International Secretariat, AI who is part of the team dealing with Indonesia, to Grace Perrett who is currently volunteering at AIUK, and to Andy Gray – a campaigner for Maluku. 3.0 Death Penalty: David reported that he had written a letter of behalf of two individuals on Death Row in Nigeria – in EDO State – asking for the abolition of the Death Penalty; the Group signed David’s letter. -

Indonesia 2013 Human Rights Report
INDONESIA 2013 HUMAN RIGHTS REPORT EXECUTIVE SUMMARY Indonesia is a multi-party democracy. In 2009 voters re-elected Susilo Bambang Yudhoyono as president. Domestic and international observers judged the 2009 legislative and presidential elections free and fair. Authorities generally maintained effective control over security forces; however, there were instances in which elements of the security forces committed human rights abuses. The government failed to conduct transparent and credible investigations into some allegations of extrajudicial killings by security forces. The government did not always protect the rights of religious and social minorities and economically marginalized citizens. The government applied treason and blasphemy laws to limit freedom of expression by peaceful independence advocates in the provinces of Papua and West Papua and by religious minority groups. Corruption, abuse of prisoners and detainees, harsh prison conditions, trafficking in persons, child labor, and failure to enforce labor standards and worker rights continued as problems. On some occasions the government punished officials who committed abuses, but judicial sentencing often was not commensurate with the severity of offenses, as was true in other types of crimes. Separatist guerrillas in Papua killed members of the security forces and injured others in several attacks. Section 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from: a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life There were several reports that the government or its agents committed arbitrary or unlawful killings during the year. Teams of investigators appointed by the Indonesian military (TNI) are responsible for investigating and evaluating whether killings by military personnel were justified. The Ethics Division of the Indonesian National Police (INP) is responsible for investigating and evaluating whether killings by police personnel were justified. -

Indonesia: It's Not Good Enough
INDONESIA IT’S NOT GOOD ENOUGH AMNESTY INTERNATIONAL SUBMISSION FOR THE UN UNIVERSAL PERIODIC REVIEW, 27TH SESSION OF THE UPR WORKING GROUP, MAY 2017 Amnesty International is a global movement of more than 7 million people who campaign for a world where human rights are enjoyed by all. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations. © Amnesty International 2016 Except where otherwise noted, content in this document is licensed under a Creative Commons (attribution, non-commercial, no derivatives, international 4.0) licence. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode For more information please visit the permissions page on our website: www.amnesty.org Where material is attributed to a copyright owner other than Amnesty International this material is not subject to the Creative Commons licence. First published in 2016 by Amnesty International Ltd Peter Benenson House, 1 Easton Street London WC1X 0DW, UK Index: ASA 21/5345/2016 September 2016 Original language: English amnesty.org CONTENTS INTRODUCTION 4 FOLLOW UP TO THE PREVIOUS REVIEW 4 THE NATIONAL HUMAN RIGHTS FRAMEWORK 5 HUMAN RIGHTS SITUATION ON THE GROUND 7 IMPUNITY FOR PAST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS 7 FREEDOM OF EXPRESSION, THOUGHT, CONSCIENCE AND RELIGION 8 THE HUMAN RIGHTS SITUATION IN PAPUA 10 THE DEATH PENALTY -
Tussen De Plooien Van De Geschiedenis Onderhandeling Van Herinnering En Integratie Bij De Gurkhas, De Molukkers En De Harkis
TUSSEN DE PLOOIEN VAN DE GESCHIEDENIS ONDERHANDELING VAN HERINNERING EN INTEGRATIE BIJ DE GURKHAS, DE MOLUKKERS EN DE HARKIS Aantal woorden: 51.505 Wouter Reggers Studentennummer: 01400196 Promotor: Prof. dr. Berber Bevernage Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de geschiedenis Academiejaar: 2017 - 2018 Inhoudstafel INLEIDING ..................................................................................................................................... 1 LUIK 1 – UITLIJNING VAN HET ONDERZOEK ....................................................................... 6 CONCEPTUEEL KADER & METHODOLOGIE ..................................................................................... 6 HERINNERING – CONCEPTUELE BENADERING EN METHODOLOGISCHE UITDAGINGEN ............................................. 6 FACTOREN VAN VERGELIJKING ................................................................................................................. 18 AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK .............................................................................................. 29 DE GURKHAS ....................................................................................................................................... 29 DE MOLUKKERS ................................................................................................................................... 34 DE HARKIS .......................................................................................................................................... 43 VERANTWOORDING -

Human Rights in Indonesia
HUMAN RIGHTS IN INDONESIA HEARING BEFORE THE TOM LANTOS HUMAN RIGHTS COMMISSION HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED AND THIRTEENTH CONGRESS FIRST SESSION _______ MAY 23, 2013 Available via the World Wide Web: http://www.tlhrc.house.gov i TOM LANTOS HUMAN RIGHTS COMMISSION JAMES P. McGOVERN, Massachusetts, Co-chairman FRANK R. WOLF, Virginia, Co-chairman JAN SCHAKOWSKY, Illinois CHRIS SMITH, New Jersey DONNA EDWARDS, Maryland JOSEPH R. PITTS, Pennsylvania KEITH ELLISON, Minnesota TRENT FRANKS, Arizona SUZANNE BONAMICI, Oregon JEFF DUNCAN, South Carolina JANICE KAGUYUTAN, Democratic Staff Director KALINDA STEPHENSON, Republican Staff Director KATYA MIGACHEVA, Lead/James Marshall Public Policy Fellow JAMES “J.P.” SHUSTER, Law Fellow DENISE BELL ii C O N T E N T S --------------- WITNESSES Deputy Assistant Secretary Dan Baer, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State…..…………. 3 Susan Sutton, Director, Office of Maritime Southeast Asia, U.S. Department of State……………………………………………. 6 John Sifton, Asia Advocacy Director, Human Rights Watch……………………………………………………………………... 12 T. Kumar, Director for International Advocacy, Amnesty International USA…………………………………………………… 24 Sri Suparyati, Deputy Coordinator, Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)………………...…… 47 Octovianus Mote, Yale University Law School Fellow………………………………………………………………………..…. 53 LETTERS, STATEMENTS, ETC., SUBMITTED FOR THE HEARING Prepared Statement of John Sifton………………………………………………………………………………………………… 15 Prepared Statement of T. Kumar………………………………………………………………………………………………….. 26 Prepared Statement of Sri Suparyati………………………………………………………………………………………………. 49 Prepared Statement of Octovianus Mote………………………………………………………………………………………….. 56 APPENDIX Hearing Notice…………………………………………………………………………………………………………………….. 80 iii HUMAN RIGHTS IN INDONESIA ____________ THURSDAY, MAY 23, 2013 HOUSE OF REPRESENTATIVES, TOM LANTOS HUMAN RIGHTS COMMISSION, Washington, D.C. The commission met, pursuant to call, at 10:00 a.m., in Room 2261 Rayburn House Office Building, Hon. -

Indonesia 9-Point Agenda EN Full Finalr
RIGHTS NOW 9-POINT HUMAN RIGHTS AGENDA FOR INDONESIA’S ELECTION CANDIDATES RIGHTS NOW: 9-POINT HUMAN RIGHTS AGENDA FOR INDONESIA’S ELECTION CANDIDATES Amnesty International 1 © Amnesty International Indonesia 2019 Except where otherwise noted, content in this document is licensed under a Cover photo: An Indonesian citizen entered a ballot after using her vote Creative Commons (attribution, non-commercial, no derivatives, international in the 2009 presidential election at Cipto Mangunkusumo Hospital 4.0) license. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode (RSCM) polling station, Jakarta, 8 July 2009. © TEMPO/Imam Sukamto For more information please visit the permissions page on our website: www.amnesty.org. Where material is attributed to a copyright owner other than Amnesty International this material is not subject to the Creative Commons license. First published in 2019 by Amnesty International Indonesia HDI Hive Menteng 3rd Floor, Probolinggo 18 Jakarta Pusat 10350 Index: ASA 21/0153/2019 Original language: English RIGHTSPrinted NOW: by Amnesty International Indonesia 9-POINT HUMAN RIGHTS AGENDA FOR INDONESIA’S ELECTION CANDIDATES Amnestyamnesty.org International — amnestyindonesia.org 2 CONTENTS 1. UPHOLD THE RIGHT TO FREEDOM OF EXPRESSION AND PROTECT HUMAN RIGHTS DEFENDERS 5 2. RESPECT AND PROTECT THE RIGHT TO FREEDOM OF THOUGHT, CONSCIENCE, RELIGION AND BELIEF 9 3. ENSURE ACCOUNTABILITY FOR HUMAN RIGHTS VIOLATIONS COMMITTED BY SECURITY FORCES 12 4. ESTABLISH ACCOUNTABILITY FOR PAST HUMAN RIGHTS VIOLATIONS 15 5. UPHOLD THE RIGHTS OF WOMEN AND GIRLS 17 6. RESPECT HUMAN RIGHTS IN PAPUA 21 7. CLOSE THE ACCOUNTABILITY GAP FOR HUMAN RIGHTS ABUSES BY COMPANIES IN PALM OIL SECTOR 24 8. -

Universal Periodic Review Submission Republic of Indonesia May 2017 A. Introduction and Summary 1. the Alifuru People Are
Universal Periodic Review Submission Republic of Indonesia May 2017 A. Introduction and Summary 1. The Alifuru people are the Indigenous peoples living on the Maluku archipelago situated between the Philippines and East Timor. There are an estimated 1027 islands, with a total area of 850,000 km2, 90% of which is sea. Maluku's population is 2,571,593 (2010), and over 100 languages are spoken across the islands. The Alifuru culture has been purposely suppressed by Indonesian authorities, and the forests in which they have resided for time immemorial have been exploited by logging companies, and government projects. T he Alifuru adhere to their traditional religion which is mostly based on a belief that the ancestors control every day life and if the traditions they handed down are not followed correctly the living will be punished. 2. Saniri Alifuru (Alifuru Council) is a consortium of traditional chiefs and leaders of the Maluku islands, that has existed since time immemorial, established in the pre-colonial era committed to ensure the survival of the Alifuru people through the promotion and protection of their social, economic, cultural, educational, spiritual, and political needs. The Saniri has a unique oral constitution that provides for the functioning of the Council. Saniri Alifuru aims to include all traditional chiefs and leaders in its work including from Wetar, Kisar, Romang, Leti/Moa/Lakor, Damar, Teun/Nila/Serua, Babar, Tanimbar, Kei, Aru, Banda, Watubela, Gorom, Geser, Lease, Ambon islands and from Buru the districts Ambelau/Namrole, Kapalamada/Airbuaya, Namlea/Teluk Kayeli, Tg. Walwalat/Leksula, Buano/Kelang/Manipa, on Seram the districts of Alune/Makahala, Wemale, Nuaulu, Huaulu, Sima Sima, Nusamwele, Manusela, Hatuolo, Tanahbaru, Waerama, Uhei Kahlakim, Bobot, Bonfia, and Seti. -

Amnesty International Report 2015/16 the State of the World’S Human Rights
AMNESTY INTERNATIONAL Amnesty International is a global movement of more than 7 million people who campaign for a world where human rights are enjoyed by all. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. Amnesty International’s mission is to conduct research and take action to prevent and end grave abuses of all human rights – civil, political, social, cultural and economic. From freedom of expression and association to physical and mental integrity, from protection from discrimination to the right to housing – these rights are indivisible. Amnesty International is funded mainly by its membership and public donations. No funds are sought or accepted from governments for investigating and campaigning against human rights abuses. Amnesty International is independent of any government, political ideology, economic interest or religion. Amnesty International is a democratic movement whose major policy decisions are taken by representatives from all national sections at International Council Meetings held every two years. Check online for current details. First published in 2016 by Except where otherwise noted, This report documents Amnesty Amnesty International Ltd content in this document is International’s work and Peter Benenson House, 1 Easton licensed under a Creative concerns through 2015. Street, London WC1X 0DW Commons (attribution, non- The absence of an entry in this United Kingdom commercial, no derivatives, report on a particular country or international 4.0) licence. © Amnesty International 2016 territory does not imply that no https://creativecommons.org/lice human rights violations of Index: POL 10/2552/2016 nses/by-nc-nd/4.0/legalcode concern to Amnesty International ISBN: 978-0-86210-492-4 For more information please visit have taken place there during the A catalogue record for this book the permissions page on our year. -

108Th Hrcttee AI Submission INDONESIA
INDONESIA SUBMISSION TO THE UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COMMITTEE FOR THE 108TH SESSION OF THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE (8-26 JULY 2013) Amnesty International Publications First published in 2013 by Amnesty International Publications International Secretariat Peter Benenson House 1 Easton Street London WC1X 0DW United Kingdom www.amnesty.org © Amnesty International Publications 2013 Index: ASA 21/018/2013 Original Language: English Printed by Amnesty International, International Secretariat, United Kingdom All rights reserved. This publication is copyright, but may be reproduced by any method without fee for advocacy, campaigning and teaching purposes, but not for resale. The copyright holders request that all such use be registered with them for impact assessment purposes. For copying in any other circumstances, or for reuse in other publications, or for translation or adaptation, prior written permission must be obtained from the publishers, and a fee may be payable. To request permission, or for any other inquiries, please contact [email protected] Amnesty International is a global movement of more than 3 million supporters, members and activists in more than 150 countries and territories who campaign to end grave abuses of human rights. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public -

Amnesty International Report 2016/17 Amnesty International
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2016/17 AMNESTY INTERNATIONAL Amnesty International is a global movement of more than 7 million people who campaign for a world where human rights are enjoyed by all. Our vision is for every person to enjoy all the rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights standards. We are independent of any government, political ideology, economic interest or religion and are funded mainly by our membership and public donations. First published in 2017 by Except where otherwise noted, This report documents Amnesty Amnesty International Ltd content in this document is International’s work and Peter Benenson House, licensed under a Creative concerns through 2016. 1, Easton Street, Commons (attribution, non- The absence of an entry in this London WC1X 0DW commercial, no derivatives, report on a particular country or United Kingdom international 4.0) licence. territory does not imply that no https://creativecommons.org/ © Amnesty International 2017 human rights violations of licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode concern to Amnesty International Index: POL 10/4800/2017 For more information please visit have taken place there during ISBN: 978-0-86210-496-2 the permissions page on our the year. Nor is the length of a website: www.amnesty.org country entry any basis for a A catalogue record for this book comparison of the extent and is available from the British amnesty.org depth of Amnesty International’s Library. concerns in a country. Original language: English ii Amnesty International -

Urgent Action
First UA: 82/21 Index: ASA 21/4474/2021 Indonesia Date: July 19, 2021 URGENT ACTION THREE MOLUCCANS ARBITRARILY ARRESTED AND DETAINED Pieter, Alexander and Benjamin, pro-independence political activists from Molucca, have been arbitrarily arrested and charged with treason for their role in keeping a Republic of South Maluku (RMS) flag “Benang Raja” in a private house. Charged with treason “makar”, they face up to 20 years of imprisonment. The Indonesian authorities have used the criminal code provisions, mainly Articles 106 and 110 KUHP, to prosecute tens of peaceful pro-independence political activists in Maluku and Papua simply for peacefully exercising their rights to freedom of expression, association and peaceful assembly. TAKE ACTION: 1. Write a letter in your own words or using the sample below as a guide to one or both government officials listed. You can also email, fax, call or Tweet them. 2. Click here to let us know the actions you took on Urgent Action 82.21. It’s important to report because we share the total number with the officials we are trying to persuade and the people we are trying to help. General (Pol). Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. Chargés d’Affaires Iwan Freddy Hari Susanto Chief of Indonesian National Police Embassy of the Republic of Indonesia Jalan Trunojoyo No. 3 South Jakarta, 2020 Massachusetts Ave. NW Indonesia 12110 Washington, DC 20036 Phone: 202 775 5200 Twitter: @IndonesiainDC Facebook: @IndonesiainDC Salutation: Dear Mr. Dear General (Pol). Prabowo, I am writing to express my deep concern regarding the case of three pro-independence activists named Pieter Likumahua, Alexander Workala and Benjamin Naene who have been arrested and accused of treason (makar) allegedly due to their affiliation with the Republic of South Maluku (RMS).