Bab I Pendahuluan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

About Just Mercy
TOOLKIT ALWAYS DO THE RIGHT THING, EVEN WHEN THE RIGHT THING IS THE HARD THING HARD THE IS THING RIGHT THE WHEN EVEN ABOUT JUST MERCY The film Just Mercy is based on an award-winning book of the same name by attorney Bryan Stevenson, played by Michael B. Jordan. Raised in rural Delaware, Stevenson regularly attended the African Methodist Episcopal Church, where he developed a strong sense of justice and compassion. He earned a law degree and a Masters in Public Policy from Harvard, and in 1989 he launched the Equal Justice Initiative (EJI) in Montgomery, Alabama, which is committed to ending mass incarceration and excessive punishment in the United States, along with challenging racial and economic injustice, and protecting basic human rights for the most vulnerable people in American society. EJI has won reversals, relief, or release from prison for over 140 wrongly condemned prisoners on death row. One of those stories is at the center of Just Mercy. Walter McMillian, played by Jamie Foxx, was convicted and sentenced to death for a murder he did not commit. For more than four years, Bryan Stevenson fought for justice and mercy against a system stacked against him and his client at every turn. Stevenson has gained international recognition for his work defending the poor and un- fairly incarcerated, and has said, “The opposite of poverty is not wealth...the opposite of poverty is justice.” JUST MERCY embodies the mission of forgiveness and redemption for people who have been incarcerated, and demands a fair legal system, free of extreme sentences. -

Racial Justice Resources
Racial Justice Resources “White supremacy is not the elephant in the room. It is the room.” - Nelba Marquez-Greene The members of the Racial Justice Team are asked for resources that would help people to learn about racism and white supremacy: to help us all to look at race and racism and its impact on all of us. The resources listed below were compiled by Monica Sargent and her colleagues and she has allowed us to share them with you. Some items have been added to Monica’s lists. Movies that can help educate viewers about racism: Do the Right Thing (1989) Fruitvale Station (2013) Moonlight (2016) Dead Presidents (1995) In the Heat of the Night (1967) Get Out (2017) 13th (2016) To Sleep with Anger (1990) The Hate U Give (2018) To Kill a Mockingbird (1962) Malcolm X (1992) Let the Fire Burn (2013) Just Mercy (2019) Race: The Power of an Illusion (2003 documentary) racepowerofanillusion.org Books to Broaden Your Knowledge of Racism: Non-Fiction: White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism by Robin DiAngelo How to Be an Antiracist by Ibram X. Kendi Biased: Uncovering the Hidden Prejudice That Shapes What We See, Think, and Do by Jennifer L. Eberhardt Raising White Kids by Jennifer Harvey So You Want to Talk About Race by Ijeoma Oluo The Black and the Blue: A Cop Reveals the Crimes, Racism, and Injustice in America’s Law Enforcement by Matthew Horace and Ron Harris Just Mercy: A Story of Justice and Redemption by Bryan Stevenson (also a 2019 movie) The Fire Next Time by James Baldwin Why I’m No Longer Talking to -

Called to Worship, Empowered to Serve the 21-Day Challenge Inspires Change Makers for Racial Equity
Star Press THE OFFICIAL NEWSLETTER OF STARMOUNT PRESBYTERIAN CHURCH July 2020 “We must always give thanks to God for you, brothers and sisters, as is right, because your faith is growing abundantly, and the love of every one of you for one another is increasing. 4 Therefore we ourselves boast of you among the churches of God for your steadfastness and faith during all your persecutions and the afflictions that you are enduring.” -2 Thessalonians 1:3-4 This passage comes from the introduction to Paul’s letter to the church in Thessalonica. In this introduction, Paul is expressing his gratitude towards those in the church for their faithfulness even in the midst of persecution. Even though our sufferings may not compare to the level of persecution experienced by the Thessalonians, it is safe to say that we do indeed find ourselves in the midst of difficult circumstances. In the midst of these difficult circumstances, I find myself, like Paul, wanting to give thanks to God for you, congregation of Starmount Presbyterian Church, because so too is your faith growing abundantly and the love you are showing towards one another (and the community) increasing. Website: Website: www.starmountpres.org I give thanks for the ways you are caring for one another and staying connected to this community. I give thanks for the phone calls and notes you are writing to each other. I give thanks for 5:00 Fellowship Zoom gatherings where we get to laugh and discuss. I give thanks for a new Starmount Facebook group and for social media savvy folks who facilitate engagement. -

Anti-Racist Resources and Reads: Lists for All Ages
Anti-racist Resources and Reads: Lists for All Ages By Elizabeth Bird See the whole list here: Antiracist Resources and Reads: Lists for All Ages | A Fuse #8 Production Books for Children (Fiction): Blended by Sharon M. Draper DB093013 From the Desk of Zoe Washington by Janae Marks DB098670 A Good Kind of Trouble by Lisa Marie Ramee DB094289 It All Comes Down to This by Karen English DB088659 New Kid by Jerry Craft (Hoopla ebook) DB094151 One Crazy Summer by Rita Williams-Garcia BR019326 DB071082 The Other Side by Jacqueline Woodson BR013093 Other Words for Home by Jasmine Warga DB096396 Books for Children (Facts): A Ride to Remember by Sharon Langley DB098530 Books for Teens (Fiction): All American Boys by Jason Reynolds DB083370 The Color Purple by Alice Walker ● BR007222 ● BR012265 ● DB018576 ● DB040883 (Spanish) ● DB058842 ● DV000297 ● LP000438 Dear Martin by Nic Stone DB089400 Ghost Boys by Jewell Parker Rhodes BR022276 DB090875 The Hate U Give by Angie Thomas BR021874 DB087441 DB087967 (Spanish) How It Went Down by Kekla Magoon DB080691 BR020666 Monster by Walter Dean Myers BR012515 Piecing Me Together by Renee Watson BR022201 DB088750 The Poet X by Elizabeth Acevedo BR022420 DB092221 Their Eyes Were Watching God by Zora Neale Hurston BR022592 DB035745 Tyler Johnson Was Here by Jay Coles BR022250 DB090391 Books for Teens (Facts) Discovering Wes Moore by Wes Moore BR019701 Hidden Figures by Margot Lee Shetterly BR021798 DB085959 (Spanish) DB086234 In The Shadow of Liberty by Kenneth C. -
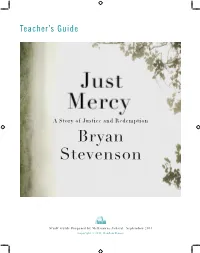
Bryan Stevenson
Teacher’s Guide A Story of Justice and Redemption Bryan Stevenson Study Guide Prepared by Melissanne Scheld September 2014 Copyright © 2014, Random House A NOTE TO EDUCATORS The following guide has been prepared in conjunction with the national Common Core Standards. Each chapter contains summary points, discussion questions for the class and activities requiring various skills and interpretation of the text. The following list of Standards correlates to the discussion questions as a whole whereas, for each of the activities, the relevant and specific Standards are indicated for each of the exercises. English Language Arts: College and Career Readiness Anchor Standards for Reading: Key Ideas & Details: CCRA.R.1-R.3, Integrations of Knowledge and Ideas: CCRA.R.7, CCRA.R.8, Range of Reading and Level of Text Complexity: CCRA.R.10 English Language Arts: College and Career Readiness Anchor Standards for Writing: Text Types and Purposes: CCRA.W.1-CCRA.W.3, Production and Distribution of Writing: CCRA.W.4, Research to Build and Present Knowledge: CCRA.W.7-CCRA.W.9, Range of Writing: CCRA.W.10 English Language Arts: College and Career Readiness Anchor Standards for Speaking and Listening: Comprehension and Collaboration: CCRA.SL.1-CCRA.SL.3, Presentation of Knowledge and Ideas: CCRA.L.4 English Language Arts: College and Career Readiness Anchor Standards for Language: Conventions of Standard English: CCRA.L.1, CCRA.L.2, CCRA.L.6, Vocabulary Acquisition and Use: CCRA.L.6 English Language Arts: Reading: Literature: Key Ideas and Details: RL.11-12.1, -

MUMC Social Just Ice Media Discussion Guide
MUMC Social Just ice Media Discussion Guide A resource by Nick Reinahrdt-Swierk Sept em ber 2020: Race Manchesterumc.org WELCOME! This guide is intended to help you, your friends, and your family to use movie night as an opportunity for reflection and discussion on racial justice issues! Each page cont ains a guide for one film . Guides include: Film Title Rating Information Streaming Platform Synopsis 1-2 Paragraph Background Information 4-5 Discussion Questions. Movies in t his Guide: Movies are listed in ascending order of intensity. Coco Zootopia Black Panther The Hate You Give Loving Big Sick Just Mercy Selma Wind River Get Out Dear White People Sorry to Bother You If you are using t his resource w it h a group, let us know ! Em ail m e at Nicki.Reinhardt sw ierk@Manchest erum c.org Manchesterumc.org Coco Category: Family PG (2017) Disney+ Race, Culture, and Family Synopsis: In Disney/Pixar?s vibrant tale of family, fun and adventure, an aspiring young musician named Migue embarks on an extraordinary journey to the magical land of his ancestors. There, the charming trickster Hector becomes an unexpected friend who helps Miguel uncover the mysteries behind his family?s stories and traditions. Background Info: Day of the Dead (Dia De Los Muertos) is a two day holiday that reunites the living and dead. Families create ofrendas (Offerings) to honor their departed family members that have passed. These altars are decorated with bright yellow marigold flowers, photos of the departed, and the favorite foods and drinks of the one being honored. -

Resources for Families Created By: Jonelle Harris, Director Of
Resources for Families Created by: Jonelle Harris, Director of Diversity & Inclusivity, and Debbie Krieg, Discovery Center Coordinator (UPDATED 10/7/20 updates are highlighted in RED) Book Suggestions Lower Division - all ages You Matter by Christian Robinson Come with Me by Holly McGhee The Last Stop on Market Street by Matt de la Peña, illustrated by Christian Robinson Each Kindness by Jacqueline Woodson, illustrated by E.B. Lewis The Day You Begin by Jacqueline Woodson, illustrated by Rafael López Dreamers by Yuyi Morales What Can a Citizen Do? by Dave Eggers Book trailer at: What Can A Citizen Do?: A picture book about the power of good citizenship by Dave Eggers Upper Division - Fiction Blended by Sharon Draper Planet Omar: Accidental Trouble Magnet by Zanib Mian and Nasaya Mafaridik New Kid by Jerry Craft Black Brother, Black Brother by Jewell Parker Rhodes Genesis Begins Again by Alicia D. Williams Upper Division - Nonfiction Not My Idea: A Book about Whiteness by Anastasia Higginbotham Book trailer at: Not My Idea Dictionary for a Better World: Poems, Quotes and Anecdotes from A to Z by Irene Latham and Charles Waters Let's Talk About Race by Julius Lester We Rise, We Resist, We Raise Our Voices edited by Wade Hudson and Cheryl Wells Hudson ; foreword by Ashley Bryan Summary: What do we tell our children when the world seems bleak, and prejudice and racism run rampant? With 96 lavishly designed pages of original art and prose, fifty diverse creators lend voice to young activists. Featuring poems, letters, personal essays, art, and other works from such industry leaders as Jacqueline Woodson (Brown Girl Dreaming), Jason Reynolds (All American Boys), Kwame Alexander (The Crossover), Andrea Pippins (I Love My Hair), Sharon Draper (Out of My Mind), Rita Williams-Garcia (One Crazy Summer), Ellen Oh (cofounder of We Need Diverse Books), and artists Ekua Holmes, Rafael Lopez, James Ransome, Javaka Steptoe, and more, this anthology empowers the nation's youth to listen, learn, and build a better tomorrow. -

Just Mercy (Bryan Stevenson) Lesson Plans
Just Mercy (Bryan Stevenson) Lesson Plans Just Mercy (Bryan Stevenson) by Bryan Stevenson (c)2017 BookRags, Inc. All rights reserved. Contents Just Mercy (Bryan Stevenson) Lesson Plans ............................................................................... 1 Contents ...................................................................................................................................... 2 Introduction .................................................................................................................................. 4 Lesson Calendar .......................................................................................................................... 9 Chapter Abstracts ...................................................................................................................... 18 Characters ................................................................................................................................. 31 Symbols/Objects ........................................................................................................................ 34 Daily Lessons ............................................................................................................................ 36 Fun Activities .............................................................................................................................. 55 Essay Topics .............................................................................................................................. 58 Short Essay -
June 16, 2021 5B
The Telegraph ALTON TELEGRAPH CLASS 01 061621 Wednesday, June 16, 2021 5B LEGALS LEGALS AUTOMOTIVE EMPLOYMENT NOTICE IN THE CIRCUIT COURT 1966 Mustang THIRD JUDICIAL CIRCUIT M A D I S O N C O U N T Y , Convertible, Excellent Public Notice is hereby I L L I N O I S Condition given that East Alton JUVENILE DIVISION Call For Details Anderson Hospital SD #13 will receive 618-979-5774 TO: FATHER, ISAAC ROSE, Nursing Servies Patient Financial Services/ proposals for the AND TO ALL WHOM IT MAY Workerʼs CONCERN 20' Heavy Duty Trailer (All shifts including PRN): Revenue Systems: Compensation w/ Reese Hitch, $5,900; • Medical*** • Reimbursement Analyst*** insurance coverage. IN THE INTEREST OF: TEM- 2004 F-350 Diesel, • Medical Surgical*** • Insurance Reviewer & Denials PERANCE ROSE, A MINOR Proposal specifications Good Condition $9,500; • Cancer Center Analyst*** may be obtained upon CASE NUMBER: 19-JA-275 Combo OR Sold Seper- • Care Coordination • Revenue Systems Physician Liason ately 618-781-2795 request from Bushue • Cardiac Cath Lab*** HR, Inc., P.O. Box 89 NOTICE FOR PUBLICATION Radiology Positions: • Chest Pain Center Effingham, IL 62401. "The last 2 times I • Mammography Tech Take notice that on MAY 10, • ED*** Phone (217) 342-3046. 2021, a petition was filed un- put a car for sale in • Radiology Tech*** Please reference code der the Juvenile Court Act by The Telegraph it • Express Care-Troy • Sonographer CKE916 when calling. Thomas A. Haine in the Cir- sold in 1 day!!!" • GI Lab • PET/CT Tech cuit Court of Madison County • Cardiopulmonary Rehab All proposals are to be entitled "In the Interest of -J.S. -

Just Mercy Free Download Just Mercy Free Download
just mercy free download Just mercy free download. Just Mercy is a movie starring Jamie Foxx, Charlie Pye Jr., and Michael Harding. World-renowned civil rights defense attorney Bryan Stevenson works to free a wrongly condemned death row prisoner. A powerful and thought-provoking true-story, "Just Mercy" follows young lawyer Bryan Stevenson (Jordan) and his history-making battle for justice. After graduating from Harvard, Bryan might have had his pick of lucrative jobs. Instead, he heads to Alabama to defend those wrongly condemned, with the support of local advocate Eva Ansley (Larson.) One of his first, and most incendiary, cases is that of Walter McMillian (Foxx,) who, in 1987, was sentenced to die for the notorious murder of an 18-year-old girl, despite a preponderance of evidence proving his innocence and the fact that the only testimony against him came from a criminal with a motive to lie. In the years that follow, Bryan becomes embroiled in a labyrinth of legal and political maneuverings and overt and unabashed racism as he fights for Walter, and others like him, with the odds-and the system-stacked against them. Just Mercy streaming: Can you watch the full movie online? Is it legal? We use your sign-up to provide content in ways you've consented to and to improve our understanding of you. This may include adverts from us and 3rd parties based on our understanding. You can unsubscribe at any time. More info. Just Mercy is a new movie starring Jamie Foxx, Michael B. Jordan and Brie Larson, and has a harrowing real-life connection. -

Letter Bill 0..4
HB5817 *LRB10121874CMG72835b* 101ST GENERAL ASSEMBLY State of Illinois 2019 and 2020 HB5817 Introduced 11/10/2020, by Rep. Mary E. Flowers SYNOPSIS AS INTRODUCED: 105 ILCS 5/27-23.15 new Amends the School Code. Sets forth a list of nonfiction, fiction, and children's books about racism that shall be required reading for students in every public elementary and secondary school beginning with the 2021-2022 school year. Requires that the instruction in the material presented by each book be age appropriate and taught at the appropriate grade level. Effectively immediately. LRB101 21874 CMG 72835 b FISCAL NOTE ACT STATE MANDATES MAY APPLY ACT MAY REQUIRE REIMBURSEMENT A BILL FOR HB5817 LRB101 21874 CMG 72835 b 1 AN ACT concerning education. 2 Be it enacted by the People of the State of Illinois, 3 represented in the General Assembly: 4 Section 5. The School Code is amended by adding Section 5 27-23.15 as follows: 6 (105 ILCS 5/27-23.15 new) 7 Sec. 27-23.15. Books about racism; required reading. 8 (a) Beginning with the 2021-2022 school year, every public 9 elementary and secondary school shall include as required 10 reading in its appropriate grade-level curriculum the 11 following books about racism: 12 (1) Nonfiction books: 13 (A) "Ain't I a Woman: Black Women and Feminism" by 14 bell hooks. 15 (B) "Between the World and Me" by Ta-Nehisi Coates. 16 (C) "Biased: Uncovering the Hidden Prejudice That 17 Shapes What We See, Think, and Do" by Jennifer L. 18 Eberhardt, Ph.D. -

DISCUSSION QUESTIONS 1. Stevenson Remembers His
DISCUSSION QUESTIONS 1. Stevenson remembers his grandmother telling him throughout his childhood, “You can’t understand most of the important things from a distance, Bryan. You have to get close.” How do we see the author getting close to issues of punishment and mass incarceration throughout the book? What are some examples of Stevenson getting close to the incarcerated people he works with? How does getting close to Walter McMillian affect his life? Stevenson writes that injustice occurs when “we allow fear, anger, and distance to shape the way we treat the most vulnerable among us.” As you begin your collegiate studies, how will you get close to the issues that are most important to you? 2. After working with low-income and incarcerated people for many years, Stevenson came to believe that “the opposite of poverty is not wealth; the opposite of poverty is justice.” How do you see poverty affecting people’s lives in Just Mercy? Are there any examples of poverty and justice existing at the same time? What are some of the different meanings of the word “just” used throughout the book? Have Stevenson’s experiences influenced your own definition of justice? 3. As you read the book, what were your reactions to descriptions of the criminal justice system? Why does the author compare his own brokenness to the brokenness of the system? Do you believe that broken people can be healed? What does it mean to show mercy within a broken system? 4. Stevenson writes that there are four primary institutions that shape the conversation around race and justice today: slavery, racial terror and the threat of violence against people of color, Jim Crow laws that legalized segregation, and mass incarceration.